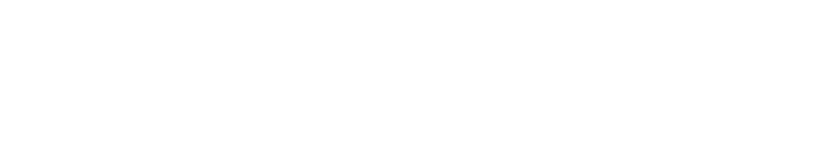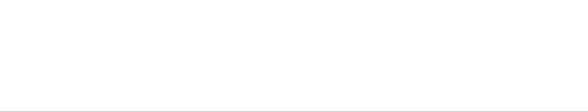Di sebuah ruangan kecil, seorang ustadz menjelaskan kepada orang-orang yang tengah belajar, “Apakah qunut hukumnya sunnah (mustahab)? Apa dalilnya?” tanya salah seorang yang hadir. Mendengar pertanyaan itu, Ustadz tersebut menjelaskan bahwa yang dibawakan hanya fatwa-fatwa dari seorang mujtahid (baca; marja’) yang siap pakai saja. Ia merasa tidak berkompeten untuk menjelaskan dalil-dalil dari setiap fatwa, karena itu adalah urusan para mujtahid. Tetapi ia berusaha meyakinkan penanya bahwa setiap fatwa tersebut pasti mempunyai dasar dan dalil syar’i. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa mengetahui dalil sebuah hukum tidak semudah yang dibayangkan, karena banyak tahapan-tahapan ijtihadi ―deretan argumentasi yang harus dilalui untuk sampai pada kesimpulan bahwa fatwa-fatwa tersebut memiliki rangkaian dalilnya tertentu. Dan tahapan-tahapan yang harus dilaluinya membutuhkan waktu, keahlian (malakah), dan penguasaan sejumlah disiplin ilmu agama yang memadai. Tidak sekadar membuka kitab hadis Bulughul Maram (apalagi lewat terjemahannya), lalu menyimpulkan sebuah hukum berdasarkan satu atau dua hadis dari kitab itu. Disamping secara metodologis memang tidak benar, pada saat yang bersamaan seseorang tersebut telah terperangkap dalam ra’yu. Padahal untuk memperoleh hukum atau fatwa. harus dilakukap dengan melakukan ijtihad, bukan ra’yu.
Ilustrasi di atas menggambarkan satu dari beberapa kasus yang sering terjadi di majelis-majelis taklim di negeri kita ini. Khususnya dari kalangan pengikut mazhab pembaharu seperti Persis dan Muhammadiyah. Tetapi kasus ini amat jarang terjadi di kalangan kaum nahdhiyyin (kalangan yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan NU atau Nahdhatul Ulama, red.). Untuk itu, perlu dipertegas apakah setiap muslim harus mengetahui dalil-dalil semua hukum syariat dan semua urusan ‘ubudiyyah? Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan masalah ijtihad dalam kaitannya dengan keberagamaan kaum muslimin di Indonesia.
Definisi Ijtihad
Ijtihad adalah terminologi yang sangat akrab di telinga kaum muslimin. Kata ini, dalam persepsi mereka sudah keluar dari arti asalnya, yakni “bersungguh-sungguh”. Kata ijtihad sudah menjadi istilah yang baku dalam kajian yurisprudensi Islam atau hukum fiqh Islam. Meskipun disana-sini, kata tersebut acapkali dipakai dalam disiplin ilmu Islam dan ilmu sosial lain. Misalnya, ijtihad politik, ijtihad filsafat, dan lainnya.
Berdasarkan terminologi fiqh Islam, ijtihad mempunyai pengertian yang khas dan unik. Al-Ghazali menjelaskan ijtihad sebagai, “mencurahkan segenap kemampuan dalam melakukan sebuah perbuatan...” Kemudian dia melanjutkan, “tetapi kata ini dalam ‘uruf para ulama digunakan secara spesifik untuk seorang mujtahid yang mencurahkan segenap kemampuannya dalam mencari ilmu tentang hukum-hukum syariat.”[1]
Al-Dahlawi memberikan penjelasan yang lebih tegas dan rinci dengan berkata, “Hakikat ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci, yang secara global kembali keempat macam dalil; Kitab, sunnah, ijma’dan qiyas.”[2]
Al-Qodhi Abdurrahman bin Ahmad al-Syafi’i al-Adhudi berkata, “ijtihad adalah mencurahkan segenap usaha dan kemampuan dalam rangka mendapatkan hukum syariat yang dzanni.”[3]
Dalam catatan kaki kitab al-Rasail, Imam Khomeini mengatakan, “ijtihad adalah keahlian (malakah) atau kemampilan yang dengannya dia dapat menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalil.”[4] Banyak lagi keterangan para ulama seputar makna ijtihad, yang kesemuanya bersepakat bahwa untuk mendapatkan hukum syariat dari sumber-sumbernya membutuhkan kesungguhan yang maksimal. Yang diperoleh secara tegas dari keterangan mereka adalah bahwa ijtihad bukan perbuatan yang dilakukan sekedar membuka-buka kitab tafsir atau hadis lalu dengan mudah ditarik sebuah kesimpulan hukum. Sebaliknya, dalam ijtihad dibutuhkan kesungguhan dan keseriusan dengan mencurahkan segenap kernampuan dan usaha untuk mendapatkan hukum-hukum syariat. Hal itu menunjukkan bahwa masalah ijtihad bukan perkara yang mudah, tetapi ijtihad juga harus diupayakan pada setiap generasi, agar ajaran Islam tetap dinamis, tidak stagnan, dan siap memberikan solusi atas segala problematika kontemporer.
Ijtihad Bukan Ra’yu
Ijtihad dan ra’yu adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Seringkali ra’yu dianggap sebagai ijtihad. Padahal terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya. Ra’yu menurut Ibnu Qoyyim al-Jauzi dalam kitab ‘A’lamu al-Mawqi’ain, adalah, “sesuatu yang dianggap oleh hati setelah berpikir, merenung, dan mencari demi mengetahui arah yang benar.”[5]
Dari defenisi ibnu Qoyyim jelas bahwa ra’yu hanyalah hasil perenungan seseorang untuk mencari pembenaran/justifikasi atas kelakuannya. Oleh karena itu, ra’yu sangat subjektif dan tidak bisa digeneralisasi, karena hasil perenungan dan pikiran manusia yang bisa berbeda-beda, selain itu penetapan hukum syariat berdasarkan ra’yu mengandung resiko yang sangat tinggi, itu sama dengan menetapkan hukum syariat menurut hasil pikiran manusia. Penetapan hukum berdasarkan ra’yu banyak macamnya, antara lain:
1. Usaha seseorang untuk mendapatkan hukum terhadap sebuah kasus, dengan mencari keterangan dari ayat atau hadis, setelah mendapatkan ayat yang berkenaan dengan kasus dimaksud, segera menyimpulkan bahwa kasus tersebut hukumnya demikian. Itu dilakukan terlepas apakah sebelumnya ia telah melakukan kategorisasi jenis ayat atau hadis itu (apakah bersifat umum atau khusus, nasikh atau mansukh, mutlak atau muqayyad dan lain sebagainya), yang harus diteliti oleh seseorang yang akan masuk ke samudera ayat dan hadis yang luas.
2. Mengikuti suara hati, berdasarkan hadis yang populer “tanyalah hatimu” (istafti qolbaka). Hadis ini menganjurkan seseorang yang bimbang untuk mengetjakan suatu perbuatan yang hukumnya mubah agar bertanya pada hatinya. Seandainya shahih, maka setiap orang akan mempunyai hukum sendiri yang akan berbeda dengan orang lain, tetapi namanya bukan hukum syar’i, tapi qalbi.
3. Membaca sebuah ayat atau hadis tentang hukum lain menarik sebuah kesimpulan hukum.
4. Memilih satu hukum dari dua hukum untuk satu kasus berdasarkan maslahat (istihsan).
Empat contoh ini jelas bukan ijtihad dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum syariat.
Perbedaan lain antara keduanya adalah, ijtihad merupakan spesialisasi yang menuntut keahlian dan penguasaan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk berijtihad. Selain itu, ijtihad dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti yang telah disebutkan dalarn defenisinya. Sedangkan ra’yu hanya berdasarkan pandangan seseorang yang tidak membutuhkan spesialisasi apapun. Setiap orang bisa saja memberikan ra’yu-nya terhadap segala permasalahan; politik, sosial, ekonomi, agama. Namun pandangannya tidak valid, atau bahkan validitas pandangannya tidak mempunyai nilai dan bobot sama sekali. Apalagi di dunia modern ini pengetahuan (knowledge) berkembang sangat pesat dan luas sehingga setiap bidang pengetahuan membutuhkan spesialisasi (tahkashshush), dan pada bidang tersebut hanya orang-orang tertentu saja yang layak memberikan pendapatnya sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya. Tidak dibenarkan seseorang dengan spesialisasi kedokteran berpendapat tentang konstruksi bangunan atau sebaliknya, atau memberikan pendapat tentang filsafat yang transenden. Karena itu berarti pelecehan terhadap ilmu pengetahuan dan penghinaan terhadap institusi-institusi keilmuan. Demikian pula halnya ilmu fiqih dan hukum syariat yang sumbemya adalah al-Quran dan Hadis yang sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu dalam menetapkan hukum syariat Islam, tidak dibenarkan setiap orang berbicara menurut ra’yu-nya.
Hadis Muadz Bin Jabal
Untuk mencari pembenaran, ada beberapa hadis yang dianggap dapat dijadikan sebagai alasan diperbolehkannya menggunakan ra’yu. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Muadz bin Jabal ―hadis yang paling populer dijadikan sebagai dasar dibenarkannya penerapan hukum dengan ra’yu. Hadis ini di riwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dan Sunan al- Darimi yang bunyinya, “Sesungguhnya Rasulullah saww mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda, ‘Bagaimana anda nanti memberikan keputusan ?”
“Aku memberi keputusan dengan kitabullah.”
“Bagaimana kalau tidak ada dalam kitabullah?”
“Maka dengan sunnah Rasulullah saww.”
“Bagaimana kalau tidak ada dalam sunnah Rasulullah?”
“Aku berusaha dengan ra’yu-ku dan aku tidak akan menyerah.”
Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan bersabda, “segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah.”[6]
Sayyid Murtadha al-Askari berusaha memberikan tanggapan yang tajam terhadap hadis ini dengan mengutip komentar kritis dari ibnu Hazm, “Adapun Riwayat Muadz, maka tidak bisa dijadikan dasar (hujjah), karena hadis ini tidak diriwayatkan kecuali dari jalur Harits bin Amr, pribadi yang misterius (majhul). Tidak seorang pun yang mengetahui siapa dia. Mengenai biografinya, al-Bukhari berkata, “Harits tidak dikenali kecuali dengan hadis ini saja dan hadisnya tidak shahih.” Kemudian Harits meriwayatkan dari orang- orang Himash, tidak diketahui siapa mereka...?”[7]
Kemudian jika hadis ini shahih, maka arti ijtihad dengan ra’yu harus diartikan “berijtihad dengan merujuk ke Quran dan hadis”. Atau jika hadis ini shahih, maka ada dua kemungkinan, ijtihad dengan ra’yu diperuntukkan hanya untuk Muadz saja dan yang lain harus mengitkuti ra’yu-nya, atau ijtihad ini juga diperuntukkan untuk selain Muadz, maka setiap orang boleh menggunakan ra’yu-nya untuk menentukan hukum. Kedua kemungkinan ini jelas tidak logis dan tidak dapat dibenarkan.
Kecuali itu, banyak hadis-hadis yang mengecam penggunaan ra’yu, diantaranya:
1. “Jika agama itu didasarkan pada ra’yu, maka mengusap bagian bawah sepatu lebih pantas dari bagian atas.”[8]
2. “Barangsiapa menafsirkan ra’yu-nya, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka.”[9]
Oleh karena fiqh atau hukum syariat adalah hukum Allah swt, maka siapapun tidak berhak berpendapat atau menggunakan ra’yu-nya. Nabi sendiri tidak menggunakan ra’yu dan malah beliau pundalam masalah syariat tidak berijtihad. Demikian itu, karena segala perbuatan dan ucapan Nabi (sunnah) merupakan pengejawantahan dari wahyu itu sendiri, sehingga pada gilirannya sunnah beliau menjadi dalil dan sumber hukum Islam. Ijtihad hanya berlaku pada hal-hal yang belum disebutkan secara jelas dalam al- Quran dan sunnah, atau ajaran yang tidak termasuk “al ma’lum minaddini bi al dharurah” , dan juga ijtihad tidak dibenarkan jika bertentangan dengan nash (hukum yang sudah dijelaskan dalam Quran dan sunnah).
Syarat-Syarat Ijtihad
Ijtihad sebagaimana defenisinya, menuntut keahlian dan penguasaan terhadap beberapa disiplin ilmu yang diperlukan dalam berijtihad. Al-Ghazali berkata, “Seorang mujtahid harus memiliki dua syarat: pertama, hendaknya dia menguasai sumber-sumber syariat (kitab, sunnah, ijma’, dan aqal). Kedua, hendaknya dia seorang yang adil dan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang menggugurkan keadilan.”[10] Dalam keterangannya yang panjang, beliau menjelaskan bahwa syarat kedua adalah syarat diterimanya fatwa mujtahid, bukan syarat menjadi mujtahid. Artinya bisa saja seorang yang (fasik) menjadi mujtahid, namun fatwanya tidak bisa diterima. Juga beliau menjelaskan bahwa untuk memahami kitab dan sunnah, harus terlebih dulu menguasai bahasa Arab dengan semua bagian-bagiannya, serta harus menguasai ushul fiqh, ulumul hadis, dan lain sebagainya.
Untuk lebih detail, kami jelaskan syarat-syarat ijtihad dalam beberapa noktah di bawah ini:
1. Menguasai bahasa Arab dengan bagian-bagiannya, seperti tata bahasa Arab (nahwu, shorf, dan i’lal), balaghah (ma’ani, bayan, dan badi’), serta tradisi dan percakapan orang-orang Arab. Syarat ini diperlukan karena Quran dan hadis diucapkan dan ditulis dengan bahasa Arab yang sangat tinggi dan indah. Kami merasa tidak perlu menjelaskan bagaimana para ahli bahasa Arab muslim maupun non muslim mengagumi keindahan bahasa al-Quran sejak diturunkan sampai sekarang. Menggunakan kitab terjemahan al-Quran dan kitab terjemahan hadis tidak cukup menjadikan seseorang memahami al-Quran dengan baik, karena masih mengandalkan terjemahan orang lain.
2. Mengetahui asbabun nuzul ayat-ayat Quran.
3. Mengetahui ilmu manthiq (logika) sesuai yang dibutuhkan untuk memahami al-Quran dan sunnah.
4. Mengetahui ilmu ushul fiqh (dasar-dasar hukum syariat). Ilmu ini membahas tentang apa saja yang harus diketahui atau dikuasai seorang mujtahid sebelum mengambil hukum dari al-Quran dan sunnah. Ilmu ini mencakup masalah-masalah seperti, umum, khusus, nasikh, mansukh, mutlaq, muqqayad. Dan juga bagaimana menangkap perintah Allah, apakah perintah itu mengandung arti wajib atau tidak? Dan apakah larangannya mengandung arti haram atau tidak? Walhasil, ilmu ushul fiqh mengandung ruang lingkup pembahasan yang sangat luas karena apapun yang diperlukan seorang mujtahid untuk mengambil hukum syariat termasuk bagian dari ushulfiqh.[11]
5. Mengetahui ilmu rijal. Ilmu yang membahas tentang biografi para perawi hadis. Yang menjadi fokus ilmu ini adalah mencari tahu tentang kejujuran dan ketakwaan para perawi hadis, karena hat ini berkaitan erat dengan kedudukan sebuah hadis, apakah shahih, muwatstsaq, hasan, atau dhaif.
6. Menguasai ulum al-hadits atau mushthalahul hadits. Ucapan, perbuatan, dan persetujuan (sunnah) Nabi saww telah dicatat dalam beberapa kitab hadis dan jumlahnya mencapai ribuan. Dalam ilmu ini dibahas tentang macam-macam hadis dan juga ada hadis-hadis yang sifatnya umum, khusus, mutlaq, muqayyad, dan lain sebagainya.
7. Menguasai tafsir dan maksud-maksud al-Quran.[12] Syarat ini juga dikemukakan ulama kontemporer kenamaan, Dr. Yusuf Qadhawi dalam kitabnya, Al-ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyah.[13]
Penguasaan prinsip-prinsip diatas mutlak sifatnya. Itu berarti, tanpa penguasaan terhadapnya tidak mungkin seseorang dapat mengambil hukum langsung dari al-Quran dan sunnah. Para ulama dengan penuh dedikasi dan intensitas tinggi mengembangkan ilmu ushul fiqh sedemikian rupa. Mereka telah menulis berjilid-jilid kitab. Sekedar informasi, di dunia syi’ah ―yang masih meyakini perlunya ijtihad dalam setiap generasi karena menurut mereka ijtihad adalah fardu kifayah― untuk menjadi mujtahid, seseorang diharuskan belajar malalui tahapan-tahapan tertentu dan pada setiap tahapan harus mempelajari beberapa kitab ushul fiqh dengan baik, dari yang sederhana sampai yang paling pelik. Tahapan-tahapan itu dilalui antara lima belas sampai dua puluh tahun. Itupun harus diikuti secara intensif sepanjang tahun. Dan kami kira intensitas belajar tahunan seperti itu terjadi juga pada bidang ilmu pengetahuan lain, sehingga dengan belajar seperti ini akan melahirkan ilmuwan berkualitas dan handal, tidak tanggung-tanggung, serta setiap pendapat dan gagasan mereka bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tradisi keilmuan seperti ini, barangkali tidak ada di negeri kita. Seseorang dengan mudah dikatakan pakar ilmu tertentu khususnya ilmu agama (seperti fiqih, filsafat Islam, tasawwuf) hanya karena ia telah membaca secara otodidak beberapa buku yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Memang di negeri kita, belum ada lembaga ilmu agama yang melahirkan mujtahid atau pakar dalam arti yang sebenarnya, karena tradisi keagamaan kita belum mengarah ke situ. Bahkan hampir dalam semua bidang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu tentang keindonesiaan, kita masih berkiblat pada pakar di luar negeri.
Ijtihad dalam Konteks Keagamaan di Indonesia
Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sekaligus menjadikannya sebagai jumlah terbesar di dunia, hampir seluruhnya bermazhab sunni (baca: ahlussunnah waljama’ah) kecuali beberapa ribu saja yang menganut Syi’ah.[14] Meski mereka mengaku sebagai pengikut sunni, namun secara de facto, kesunnian mereka berbeda-beda dan malah saling bertentangan. Indonesia barangkali negara Islam sunni yang paling unik dibandingkan negara-negara Islam sunni lainnya, seperti Saudi Arabia, Mesir, Pakistan, dan lainnya, karena pemahaman keislaman mereka beragam.
Keberagaman dan perbedaan pemahaman ini barangkali lantaran dipengaruhi perbedaan latar belakang kultur dan etnis. Ada aliran yang hanya mengacu pada al-Quran dan sunnah saja seperti Persis, Muhammadiyah, al-Irsyad, Islam jama’ah, dan kelompok-kelompok harakah.[15] Dan ada pula aliran yang disamping berpegangan pada al-Quran dan sunnah, juga membatasi pemahaman keagamaan mereka diseputar fiqih kepada salah satu dari empat imam mazhab saja (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) seperti kaum nahdhiyyin.
Kehadiran dan perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kehadiran wali songo dan para pendakwah lain. Apa mazhab dan aliran mereka? Sulit mendapatkan jawaban pasti. Tapi dengan melihat cara-cara ibadahnya, maka diduga kuat para penyebar Islam itu, atau mayoritas mereka, beraliran Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam berbagai perspektif. Seperti terlihat pada kalangan nahdhiyyin. Gerakan Muhammadiyah (1912) atau Persis (1920) yang dikenal sebagai kaum pembaharu, muncul belakangan pada paruh pertama abad kedua puluh. Gerakan pembaharu ini muncul karena terilhami oleh gerakan pembaharuan yang diprakarsai Muhammad Abduh (1849-1905) di Mesir. Memang secara kelembagaan, NU yang berdiri (1926) lebih muda dari Muhammadiyah dan Persis, tetapi tradisi dan corak keagamaan di Indonesia belum ada sebelum munculnya kaum pembaharu bercirikan nahdhiyyin.[16] Di beberapa tempat ditemukan adanya upacara-upacara seremonial yang mirip atau sama dengan yang biasa dilakukan kaum syi’ah, tapi kemiripan atau kesamaan upacara-apacara tersebut tidak bisa dijadikan petunjuk kuat bahwa para penyebar Islam di Indonesia adalah Syi’ah. Kalaupun ada diantara mereka yang beraliran Syi’ah, pada masa kemudian pengaruhnya lenyap dan hanya meninggalkan hal-hal yang non fiqih dan non aqidah, sepeni upacara tabut pada sepuluh pertama bulan Muharram di Sumatera dan bubur Syuro di Jawa.
Tulisan ini tidak akan memperdebatkan masalah mazhab dan aliran para penyebar Islam di Indonesia.[17]
Dengan jumlah kaum muslimin di Indonesia yang cukup besar, akan tetapi terlalu sedikit yang secara teologis terikat dengan kelompok organisasi tersebut, kecuali sekadar terikat secara emosional. Kebanyakan mereka melakukan upacara ritual keagamaan hanya lantaran ikut-ikutan tanpa pengetahuan mendalam. Mereka tidal tahu siapa Imam Syafi’i, dan apa mazhab sunni itu. Apa perbedaan mendasar antara setiap lembaga dan organisasi, dan lain sebagainya. Keberagamaan mereka hanya dihayati dan dipraktekkan secara sangat simpel sekali; melakukan shalat lima kali sehari, berpuasa, melakukan haji, dan mereka meyakini bahwa zina, khamar, dan babi diharamkan, serta lain sebagainya. Semua itu mereka terima dan lakukan begitu saja berdasarkan apa yang dipahami dan dilakukan para pendahulunya. Kenyataan ini memberikan indikasi kuat bahwa pemikiran dan dakwah dari kelompok-kelompok diatas belum banyak menyentuh masyarakat luas, apalagi mengakar. Pemikiran mereka hanya berpengaruh kepada para aktivis dan orang-orang “dalam” saja. Yang sangat memprihatinkan adalah rendahnya pemahaman mayoritas kaum muslimin terhadap masalah fiqih. Hal itu dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari mereka; dari masalah ubudiyyah mahdhah sepeni thaharah (istinja, wudhu, mandi wajib) dan shalat, sampai dengan masalah mu’amalah seperti, makanan, pemikahan, dan jual beli. Masih sering kita lihat, orang Islam buang air kecil di sembarang tempat tanpa memperhatikan kesucian, dan melakukan shalat dengan keliru. Belum diketahui jawaban yang pasti mengenai penyebab kelonggaran dan ketiadaan pengenian terhadap fiqih. Apakah lantaran para tokoh dan ulama dari kelompok-kelompok di alas tidak concern terhadap masalah fiqih, atau karena mereka memprioritaskan dakwah tentang masalah akhlak dan sosial saja? Atau ada alasan lain?
Berkenaan dengan perkembangan pemikiran tentang ijtihad di Indonesia, seperti yang telah disebutkan sebelumnya tentang adanya dua aliran yang berbeda dalam mengambil hukum syariat. Pertama, kaum pembaharu yang cenderung mengambil hukum langsung dari al-Quran dan sunnah, pengharaman terhadap konsep taqlid, serta meyakini bahwa pintu ijtihad terus terbuka sampai hari kiamat. Kedua kaum tradisional yang mengharuskan taqlid kepada salah satu dari empat mazhab yang mu’tabar ―menurut mereka― yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah ditutup.
Dua sikap berbeda ini, baik langsung atau tidak, tak bisa dipisahkan dari perkembangan ijtihad di dunia sunni. Dalam tradisi sunni, ijtihad telah dimulai sejak zaman Rasulullah saww, yaitu ketika Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal (seperti disebutkan diatas) dan beliau membolehkannya. Pada masa khulafa al-rasyidin, sejumlah sahabat melakukan ijtihad, khususnya pada masa khalifah kedua Umar bin Khattab. Umar sering berijtihad termasuk masalah yang telah dijelaskan dalam nash.[18] Kemudian kebebasan ijtihad ini berlanjut sampai abad keempat, dan yang terakhir menjadi mujtahid mutlak adalah Muhammad bin Jarir al-Thabari (wafat tahun 310 H/922 M), yang terkenal dengan karyanya yang monumental Tarikh al-Thabari tentang sejarah Islam.[19] Sebelum abad keempat, bukan hanya “empat imam” mujtahid dengan berbagai corak dan pendekatan yang berbeda-beda dalam mengambil hukum syariat. Abu Hanifah (wafat 150 H)[20], misalnya cenderung menggunakan ijtihad bil ra’yu, karena ia hidup di Irak yang jauh dari Madinah sebagai pusat hadis, dan karena latar belakangnya sebagai ahli ilmu kalam dan logika.[21] Atau Imam Malik bin Anas yang sangat anti ra’yu. Dia ahli hadis dan tinggal di Madinah.[22] Kemudian setelah abad keempat, tidak ada lagi mujtahid, karena kaum muslimin sudah merasa cukup dengan empat imam mazhab, selain pula para pengikut empat imam itu terus bertambah, sehingga muncul keengganan berijtihad. Kevakuman ijtihad ini diteruskan dengan pernyataan resmi dari penguasa Mesir. Al-Malik al-Zahir pada tahun 665 H/1257 M, bahwa selain empat mazhab tersebut, (mazhab lain, red.) tidak diakui, dan bahwa tidak seorang hakim pun dibenarkan memberikan keputusan kecuali berdasarkan empat mazhab tersebut. Syah Waliyullah al-Dahlawi dalam risalahnya yang berjudul Al-inshaf fi Bayan Sabab al-Ikhtilaf menyambut baik ditutupnya pintu ijtihad.[23]
Sebelum kehadiran kaum pembaharu, kaum muslimin secara umum di Indonesia adalah pengikut Mazhab Syafi’i, karena kehadiran Islam di Asia Tenggara berkat interaksi mereka dengan pendatang ―sebagai pedagang maupun sebagai pendakwah― dari Yaman dan Hijaz[24] bermazhab Syafi’i.[25] Kepengikutan terhadap mazhab Imam Syafi’i inilah yang tetap dipertahankan oleh kaum nahdhiyyin. Dan dalam anggaran dasar NU disebutkan bahwa mereka mengikuti mazhab Syafi’i atau salah satu dari tiga mazhab lainnya (Hanafi, Maliki, dan Hanbali).[26] Mereka berpendapat bahwa pintu ijtihad telah ditutup, yang diperbolehkan adalah ijtihad dalam mazhab atau intern mazhab Syafi’i belaka, seperti Imam Nawawi dan Imam Rofi’i.
Oleh karena itu, perkembangan fiqih dikalangan nahdhiyyin tidak akan keluar dari koridor mazhab Syafi’i. Untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer, mereka seringkali mengadakan apa yang mereka sebut “bahtsul masaail”. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan Kyai NU dari berbagai daerah untuk membahas masalah- masalah baru, dan yang menjadi bahan referensi mereka adalah kitab- kitab fiqih klasik (kitab kuning).[27] Pertemuan diadakan dalam skala regional ataupun nasional, tergantung besaran isu yang dijadikan subyek pembahasan. Kyai atau pemimpin pesantren dalam tradisi mereka mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali. Kaum awam, santri, dan masyarakat biasa akan mengikuti secara patuh apa yang difatwakan, karena merekalah yang dapat bersentuhan langsung dengan kitab-kitab rujukan yang nota bene kesemuanya berbahasa Arab. Menarik bahwa para Kyai NU sangat fanatik dengan kitab berbahasa Arab. Mereka bersikap sinis dan curiga terhadap buku- buku berbahasa Indonesia, baik karya langsung maupun terjemahan dari bahasa Arab. Dalam pandangan mereka, buku-buku agama berbahasa Indonesia tidak orisinil dan muatan ilmiahnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pelajaran bahasa Arab seperti nahwu dan shorf, di pesantren-pesantren NU menjadi prioritas utama. Seseorang bagaimanapun pandainya tentang ilmu agama, tidak berarti bagi mereka selagi tidak menguasai bahasa Arab atau tidak bisa membaca kitab-kitab kuning.
Santri dan masyarakat biasa bertaqlid kepada para kyai. Apa yang dikatakan kyai yang berkenaan dengan agama adalah benar belaka. Mereka tidak berani bertanya soal dasar dan dalil pendapatnya. Demikian pula para kyai sendiri dalam memahami masalah fiqih bertaqlid pada imam Syafi’i dan ulama Syafi’iyyah,[28] karena mereka mujtahid. Merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah tidak umum dikalangan mereka, masalah inilah yang ingin dirombak oleh kaum pembaharu, yang nanti akan dibahas.
Sekedar melengkapi keterangan ini, simak penjelasan pengamat nahdhiyyin, Andree Feillard, “Para santri belajar pada guru-guru mereka, para kyai yang kadang-kadang juga merupakan syeikh sebuah tarekat. Sekolah-sekolah itu hidup terutama dari hasil pengelolaan tanah mereka dan sumbangan-sumbangan, bukan dari uang sekolah para santri. Biasanya para santri berasal dari pedesaan. Para kyai memegang kekuasaan yang sangat besar. Otoritasnya hanya dapat disangkal oleh seorang kyai lain yang lebih berpengaruh. Di masyarakat pedesaan ini, peran mereka sangat banyak; menjadi anutan dibidang keagamaan, memimpin upacara-upacara keagamaan, dan bahkan juga menjadi penasehat pribadi para anggota masyarakatnya”.[29]
Seperti telah disebutkan bahwa tradisi kepatuhan dan taqlid kepada kyai berlangsung jauh sebelum terbentuknya NU. Tradisi inilah yang ingin dirombak kalangan pembaharu; Muhammadiyah dan Persis. Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912 setelah pulang belajar dari Mekkah pada tahun 1895. Selama di Mekkah, ia banyak dipengaruhi gurunya, Syekh Akhmad Khatib yang bermazhab Syafi’i. Namun ia sendiri pengagum pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Muhammadiyah sejak didirikannya sampai sekarang banyak terlibat dalam gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan dan sosial. Barangkali pada perkembangan berikutnya, Muhammadiyah telah dipengaruhi gerakan Wahabi, menyusul berkuasanya keluarga Sa’ud yang menjadi raja di Semenanjung Arabia. Meski mereka dalam beragama menekankan agar kaum Muslim merujuk pada al-Quran dan sunnah secara langsung, tapi mereka tidak begitu keras menentang taqlid kepada Imam Syafi’i. Itu lantaran sikap toleransi yang ditunjukkan KH Ahmad Dahlan yang diteruskan para tokoh lainnya.
Berbeda dengan Muhammadiyah, Persis banyak melibatkan diri pada perdebatan dengan kaum tradisional. Pengaruh Wahabiyah yang sangat kental membuat Persis membid’ahkan beberapa praktek keagamaan yang dilakukan kaum nahdhiyyin seperti ziarah, tahlil, talqin, qunut, dan lainnya. Termasuk yang diserang adalah taqlid. Mereka mengharuskan ijtihad atau paling tidak ittiba’.[30]
Haruskah Setiap Muslim Berijtihad?
Semua sepakat bahwa sumber hukum syariat adalah al-Quran dan sunnah, kecuali kaum akhbariyyin dari kalangan Syi’ah, yang hanya berpegang pada sunnah saja, serta golongan inkarussunnah dari kalangan sunni, yang tidak menerima hadis. Tapi jumlah mereka amat sedikit. Permasalahannya, apakah setiap orang mampu atau mempunyai kesempatan untuk menjadi mujtahid sehingga dapat secara langsung mengambil hukum dari ayat dan hadis? Tidakkah jika setiap individu muslim diharuskan berijtihad akan merusak tatanan sosial masyarakat muslim? Artinya, jika semua jadi mujtahid, lantas siapa yang akan menyibukkan diri menjadi pedagang, pengusaha, dokter, teknokrat, dan lain-lain?
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa al-Quran diturunkan, disampaikan, dan ditulis dalam bahasa Arab yang sangat tinggi dan indah.[31] Ketinggian dan keindahan bahasa al-Quran diakui, sekalipun oleh non muslim. Dari sisi ini pula, al-Quran merupakan mukjizat yang abadi dan tidak terkalahkan, sebagaimana dibuktikan tatkala manusia dan bangsa jin tidak mampu menyusun satu surat sekalipun yang sama dengan al-Quran.[32]
Oleh karena itu, syarat minimal untuk memahami al-Quran adalah menguasai bahasa Arab secara sempurna. Selain bahasa Arab, juga harus dikuasai asbabun nuzul, tafsir, dan segala disiplin ilmu yang diperlukan untuk memahami al-Quran, disamping kebersihan dan kesucian hati sebagai syarat penting untuk memahami al-Quran sebagai kalamullah. Tidak berhati-hati dalam usaha memahami al- Quran, kemudian mengklaim penafsirannya sebagai mutlak hukum Allah, akan mengandung resiko yang sangat berat dan tinggi. Demikian pula untuk memahami sunnah Nabi saww, diperlukan sejumlah disiplin ilmu tertentu.
Mewajibkan setiap individu muslim untuk berijtihad, tentu akan memberatkan. Mereka harus duduk bertahun-tahun, belajar ilmu-ilmu tersebut sehingga mempunyai malakah (keahlian) dalam bidang syariat. Untuk itu mereka harus meninggalkan semua pekerjaan dan profesi yang digeluti. Juga bakat yang dimiliki harus dikesampingkan untuk belajar agama sampai menjadi mujtahid. Hal demikian ini sangat tidak rasional dan tidak realistis, mengingat manusia diciptakan Allah swt dengan bakat alami yang berbeda-beda, dan tidak semua orang ahli dalam bidang agama, malah tidak tepat, jika semua orang harus menjadi ulama dan mujtahid. Al-Quran sendiri hanya menganjurkan agar sebagian orang saja yang memperdalam ilmu agama.[33]
Adapun istilah ittiba’ yang umum digunakan kalangan ulama Persis sebagai lawan kala taqlid, tapi sesungguhnya mereka juga taklid kepada fatwa-fatwa ulamanya, karena ittiba’ bukanlah hal yang mudah dilakukan semua orang. Dalam menerima atau menolak sebuah hukum syariat dari al-Quran atau sunnah, mereka bergantung pada ulama, karena untuk mengecek kebenaran dasar itu, sangat sulit dan jarang sekali dilakukan oleh orang kebanyakan. Jadi mereka juga pada dasarnya bertaqlid kepada ulama tentang kebenaran dalil dan keshahihan sunah. Konsekuensi logis dan praktis dari diwajibkannya ijtihad atau ittiba’ bagi setiap muslim adalah harus mengetahui dalil al-Quran atau sunnah tentang hukum taklif[34] dari semua perbuatan yang dilakukan. Sekali lagi, itu tidak rasional dan tidak realistis. Oleh karena beratnya persyaratan untuk berijtihad, maka ijtihad harus diupayakan olehorang-orang yang memiliki talenta dan minat, serta kemampuan yang cukup.
Pada sisi lain, kaum nahdhiyyin telah menutup rapat-rapat pintu ijtihad kecuali harus taqlid kepada empat imam mazhab. Ini dilakukan karena khawatir akan munculnya mujtahid-mujtahid gadungan. Kekhawatiran ini sebenarnya bisa diatasi dengan dibentuknya institusi pendidikan yang berkualitas, kurikulum pelajaran yang diperlukan bagi calon mujtahid, serta seleksi dan pengujian yang ketal. Pembatasan taqlid kepada empat imam mazhab sama dengan memposisikan fatwa-fatwa mereka sebagai sesuatu yang abadi. Padahal fatwa mereka hanya sekedar ‘interpretasi’ (ijtihad) terhadap ayat atau riwayat, yang bisa salah dan bisa benar. Dan seringkali ijtihad mereka dipengaruhi kondisi sosial dan kultural. Walaupun mereka sendiri menolak disebut seperti itu.
Ijtihad tetap diperlukan sepanjang zaman, mengingat beberapa masalah antara lain; sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik, dan semua aspek kehidupan senantiasa berkembang dan membutuhkan penyelesaian yang Islami. Dibukanya pintu ijtihad akan mendorong kaum muslimin untuk terus mengkaji dan menggali ayat-ayat al-Quran dan sunnah, dan memberikan kepada mereka rasa tanggung jawab sebagai pemilik al-Quran dan sunnah, untuk menjelaskan kepada dunia tentang pandangan al-Quran menyangkut segala sesuatu dalam setiap aspek kehidupan.[35]
Taqlid Masyru’ (Yang diperbolehkan)
Bagi kaum muslimin yang tidak berminat atau tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad, diharuskan bertaqlid. Bertaqlid merupakan suatu hal yang rasional dan realistis, dan itu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang tidak mengetahui (jahil) akan bertanya pada yang tahu (alim). Seorang ulama meskipun pandai dalam ilmu agama, ketika sakit tentu akan pergi ke dokter. Demikian pula ketika hendak membangun mesjid atau pesantren, ia akan berkonsultasi dengan seorang arsitektur (ahli bangunan). Bertanya, berkonsultasi, dan merujuk pada yang pandai merupakan taqlid. Dalam urusan syariat yang sumbernya adalah al- Quran dan sunnah yang begitu rumit, jalan untuknya yang harus ditempuh kalangan awam adalah dengan bertaqlid pada mujtahid. Taqlid dalam masalah ini menjadi mutlak dalam Islam.
Syahid Murtadha Muthahhari membagi taqlid dalam dua hal; taqlid mamnu’ (yang dilarang) dan taqlid masyru’ (yang dibolehkan). Termasuk taqlid mamnu’ adalah mengikuti tradisi dan kebiasaan yang berlaku umum di tengah masyarakat dan lingkungan secara buta. Taqlid semacam ini dilarang oleh al-Quran, “Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami atas suatu agama, dan sesungguhnya kami mengambil petunjuk atas dasar kebiasaan mereka.” (QS. al-Zukhruf: 22)
Taqlid kepada agama secara buta, tidak kritis terhadap perbuatan mereka yang melanggar agama termasuk dalam kategori taqlid mamnu’. Imam Ja’far Shodiq menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat, “Dan sesungguhnya mereka yang buta huruf (ummi). Mereka tidak mengetahui kitab kecuali dongeng-dongeng belaka, dan mereka hanya menduga-duga.” (QS. al-Baqarah: 78) adalah orang-orang Yahudi yang mengikuti para pendeta (ahli kitab) secara buta, padahal mereka menyaksikan dalam berbagai praktik bahwa para pendeta itu berdusta, tidak menahan hawa nafsu, menerima suap, dan merubah hukum demi meraup keuntungan, serta lain sebagainya.
Taqlid yang dibenarkan agama adalah mengikuti mujtahid yang menjaga diri, membela agama, tidak mengikuti hawa nafsu, dan mentaati perintah Allah swt.[36] Ukuran “menjaga diri” dan tidak mengikuti hawa nafsu bagi seorang mujtahid berbeda dengan ukuran orang awam. Seorang mujtahid panutan tidak sekadar meninggalkan khamar, judi, zina, makan uang haram, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama secara tegas. Tapi juga harus hidup sederhana, tidak menggunakan harta secara berlebihan meskipun halal, tidak menyukai popularitas, tidak mencari pengaruh dan kedudukan, ketat dalam menjalankan syariat, dalam mengeluarkan fatwa tidak didasarkan atas kepentingan pribadi, dan membenarkan perilaku kelompok tertentu (yang keliru dan melanggar hukum Islam, red.) dalam masyarakat.
CATATAN :
1. Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Al-Mustashfa, 2/350.
2. Sayyid Murtadha al-‘Askari, Ma’alam al-Madrasatain, 2/25.
3. Ayatullah Ibrahim Jannati, Adwaar-e ijtihad Azdidghah-e Mazaahib-e Islami, 9.
4. Ayatullah Khomeini, Al-Rasail, 95.
5. Ayatullah Ibrahimjannati, Adwaar-e ijtihad Azdidghah-e Mazaahib-e Islami, 27.
6. Sunan al-Damiri I/6 dan Musnad Ahmad, 5/230 dan 276.
7. Ma’alim al Madrasatain, 2/293.
8. Ibnu Hajar al-‘Asqallani, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram, 1/58.
9. Allamah Thaba’thaba’l, Tafsir Mizan, 3/75.
10. Imam Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa, 2/350-352.
11. Ayatullah Muhammad Baqir Shadr, Durus fi Ilmil Ushul, 1/38-42.
12. Lihat, Al Rasail, 96-99.
13. Mukhtar Adam, “ljtihad: Antara Teks dan Konteks”, dalam Ijtihad dalam Sorotan.
14. Secara global kaum muslimin dibagi menjadi dua golongan besar; Sunni dan Syi’ah. Sunni adalah golongan yang meyakini empat khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) sebagai penerus Nabi Muhammad saww. Mereka menganggap bahwa lewat empat khalifah dan para sahabat nabi yang lain sampai kepada kaum muslimin. Syi’ah adalah golongan yang meyakini bahwa setelah nabi Muhammad saww, Ahlul Bait sebagai pengganti beliau dan dari merekalah golongan Syi’ah menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia yang berbeda-beda tidak keluar dari golongan sunni. Meskipun sesama mereka merasa lebih Sunni dari yang lain.
15. Mereka adalah kelompok-kelompok kecil, eksklusif, dan bergerak secara sembunyi-sembunyi yang banyak digandrungi kalangan aktivis kampus di kota-kota besar; Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Kelompok ini satu sama lain berkompetisi mencari pengikut dan jama’ah. Tujuan mereka sama, melaksanakan ajaran Islam secara kaffah. Termasuk dalam kelompok ini adalah DI/TII, Ikhwanul Muslimin, dan Komando Jihad. Dalam memahami agama, mereka cenderung merujuk langsung pada al-Quran dan sunah.
16. Dr. Deliar Noer dalam disertasinya pada Universitas Cornell di Ithaca, New York, yang telah dibukukan dengan judul, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, menjelaskan panjang lebar tentang gerakan pembaharuan di Sumatera dan Jawa, serta reaksi terhadap gerakan ini dari kalangan Islam tradisional dan kalangan nasionalis yang netral agama. Ciri-ciri kaum Muslimin tradisional adalah dalam masalah fiqih bermazhab Syafi’i, pengaruh kiyai sangat kuat, mereka suka berziarah, tahlilan, wiridan dengan kitab dalail khairaat, bertawasul dengan para wali, dan mereka sangal butuh pada keberadaan para kiyai.
17. Untuk lebih lengkap lihat makalah Hamka, Abdullah bin Nuh, Abu Bakar Aceh, Dhiya’ Shahab, dan lainnya, yang disampaikan pada seminar masuknya Islam di Indonesia di Medan 1962.
18. Lihat Ma’alim at Madrasataian, jilid II, dan “Otoritas dan Ruang Ungkup ijtihad”, Muhammad Baqir, dalam buku ijtihad dalam Sorotan.
19. Lihat, Prinsip-prinsip Ijtihad, Murtadho Muthahhari.
20. Abu Hanifah seorang ahli kalam dan ahli fiqih. Kitab tentang kalam disebut dengan Al-Fiqhu al-Akhbar dan kitabnya tentang fiqih disebut AI-Fiqhu al-Asghar. Lihat, Ja’far Subhani, AI-Milal wa al-Nihal, 3/9.
21. Lihat, Prinsip-prinsip Ijtihad, op. cit.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Hijaz adalah nama lama dari semenanjung Arab. Sebelum tahun 1924 dipimpin oleh Syarif Husein. Setetah dikalahkan kabilah Ibnu Sa’ud yang mendapat bantuan dari Inggris, nama Hijaz dirubah menjadi Kerajaan Saudi Arabia (mamlakah al-A’rabiyyah al-Saudiyyah). Dalam hal ini, ibnu Sa’ud beraliran Wahabi. Lihat, Dr. Deliar Noer, Gerakan Modem Islam di Indonesia 1900-1942, hal. 242-243, dan Tarikh Aali Sa’ud.
25. Lihat, Andree Feillard, NU vis-á-vis Negara.
26. Lihat, Qonun Asasi atau AD/ART NU.
27. Dikatakan kitab kuning karena kertas kitab-kitab ini pada umumnya berwarna kuning, meskipun sekarang sudah dicetak dengan kertas putih. Kitab-kitab ini membahas masalah fiqih, teori, dan tasawwuf. AI-Fiqhu al-Asghar. Lihat, Ja’far Subhani, AI-Milal wa al-Nihal, 3/9.
28. Syafi’iyyah adalah fatwa-fatwa yang tidak langsung dari Imam Syafi’i, yang diupayakan para ulama atau mujtahid mazhab yang tidak keluar dari koridor mazhab Syafi’i. Mereka, umpamanya, Nawawi, Rofi’i, Ibnu Hajar al Haitami dan lainnya.
29. NU vis-á-vis Negara, Andree Feillard hal4.
30. Ittiba’ adalah menerima pendapat orang lain atas dasar Qur’an dan hadis. (Gerakan Modem Islam di Indonesia hal 109.
31. QS al Syua’ra : 195.
32. QS al Baqarah : 23, Yunus : 38 dan al Isra’: 88.
33. QS al-Taubah : 122.
34. Hukum taklif ada lima: wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah.
35. QS al Nahl : 89
36. Lihat Prinsip-Prinsip Ijtihad haI 42-48.