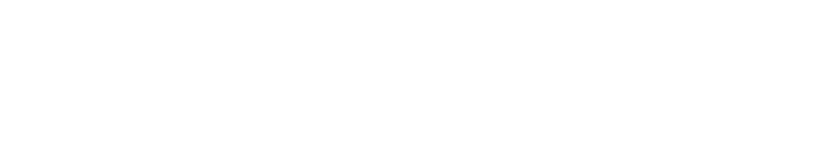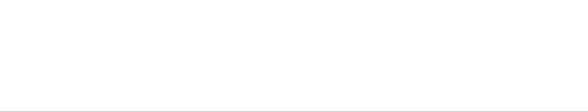Oleh: Dede Azwar Nurmansyah
SAYA sengaja memilih judul yang terkesan aneh ini untuk tulisan saya seputar peristiwa Karbala dengan beberapa pertimbangan. Pertama, peristiwa paling hitam di Karbala (Irak) yang terjadi kira-kira 14 abad silam di hari Asyura (saya kira pembaca sudah tahu, apa yang terjadi waktu dan di tempat itu) bukan lagi sebatas sebuah legenda atau cerita turun temurun. Tapi lebih merupakan semangat religius dan ajaran falsafi tentang bagaimana membaca, menghayati, dan menempuh arung kehidupan. Dengan kata lain, dari sudut penghayatan, tragedi Karbala bukan hanya peristiwa yang terjadi di masa lalu dan "di sana", tapi terus berlangsung sekarang dan "di sini".
Karbala adalah sebuah narasi agung keagamaan yang telah menyatu dengan gerak tubuh, gejolak hati, dan terawang pikiran. Kedua, peristiwa Karbala menjadi bagian dari textual tradition kalangan pecinta Ahlul Bait. Dengan tradisi yang umum diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Muharram ini, mereka berupaya mempertahankan ingatan kolektifnya dan mengekspresikan kesedihan personal masing-masing-setidaknya untuk mengikuti anjuran sejumlah riwayat-tentangnya. Ketiga, Karbala merupakan sebuah doktrin religius kontekstual yang dijelmakan menjadi simbol perlawanan dan pembebasan. Peristiwa Karbala identik dengan semangat tanpa batas Imam Husain (salah satu imam dua belas Ahlul Bait) beserta segelintir kerabat dan sahabatnya untuk membenturkan diri secara apa adanya ke tembok tirani dan kezaliman yang konon paling keras dalam sejarah Islam. Karenanya, siapapun yang mengklaim dirinya berdiri di garis keyakinan Ahlul Bait, dipastikan akan mengusung simbol ini mati-matian.Berdasarkan tiga pertimbangan ini, dapat disimpulkan bahwa peristiwa Karbala merupakan sebuah isme yang mencakupi sekaligus pandangan hidup, tradisi, dan simbol.
Sekarang, saya akan mencoba semampu saya dalam ruang tulis terbatas ini untuk menguraikan semua itu, satu demi satu, lebih jauh lagi-namun ringkas-di bawah ini.
Sebagai Pandangan Hidup
Sebagai cara memandang hidup, apa yang kita pahami secara linguistik tentang Karbala akan menentukan bentuk dan kadar apresiasi kita terhadapnya. Misal, bila kita mencecapnya sebagai upaya menuntut hak kepemimpinan politik, maka mau tak mau kita akan mengapresiasi Karbala sebagai belaka drama pergumulan atau rebutan kuasa.
Sekalipun sah-sah saja, wawasan semacam ini cenderung mengerdilkan atau setidaknya menetralisir status dan hakikat perjuangan Imam Husain yang sarat hikmah (saya tak akan mengemukakan alasannya mengingat masalah ini telah dikemukakan secara menarik oleh Syahid Murtadha Muthahhari, dalam bukunya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Falsafah Pergerakan Islam).
Sudah tentu kiprah yang dilakukan imam dua belas, termasuk Imam Husain, selalu bertumpu di atas prinsip keyakinan religius-tentunya yang otentik. Fenomena atau bentuk bisa saja sama, tapi konten boleh jadi berbeda bahkan bertentangan; begitu kata sebuah adagium. Perjuangan menuntut hak, menantang dan menghadapi musuh bersenjata lengkap yang jumlahnya jauh lebih banyak, menyerahkan diri untuk "dibunuh", dan sebagainya, bukan semata fenomena an sich dan hanya terjadi di Karbala.
Sementara dalam konteks falsafah Karbala dan Imam Husain, semua itu hanyalah gejala lahiriah, instrumen, atau medium belaka-kendati dari sisi lain tetap signifikan dan bernilai. Sementara tujuan utama di baliknya hanya dan hanya Tuhan. Jadi, ajaran Karbala adalah ajaran tentang bagaimana menjalin dan mempertahankan hubungan batin yang dekat dan harmonis dengan-Nya (taqarrub ilallâh). Tanpa peduli, apakah itu harus ditempuh lewat "kekerasan" perang yang hingar bingar dan pengorbanan diri secara total atau lewat diam di tengah kesunyian malam.
Berdasarkan visi ketuhanan, tragedi Karbala memang "harus" terjadi. Keharusan ini tentunya tak hanya bersifat deterministik (berdasarkan syarat ruang dan waktu). Tapi lebih merupakan pilihan. Ini tercermin dari ungkapan Imam Husain sendiri yang begitu mantap, "Allah ingin melihatku terbunuh dan keluargaku tertawan!"Dari logika manusiawi, ungkapan ini dapat dianggap sebagai apologi (upaya membela diri). Namun dalam konteks penghayatan personal, justru ungkapan ini menunjukkan tingkat keimanan Imam Husain yang bertengger di puncaknya.
Di matanya, sesuai kualitas keimanannya, tak ada lagi apapun dan siapapun kecuali Tuhan. Karenanya, apapun yang telah, sedang, dan akan dilakukannya bukan bersumber dari inisiatif pribadi dirinya, melainkan semata-mata inisiatif Tuhan. Tentunya dengan proses sebagaimana analogi berikut; Tuhan telah menyusun skenario Karbala, terserah apakah Imam Husain berkenan mementaskannya atau tidak-dan ternyata Imam dengan sadar dan sukarela mengambil peran paling sentral di dalamnya.
Argumen ini kiranya hanya dapat dipahami dalam kerangka teoritis keimamahan. Alhasil, berbagai faktor yang terlibat dalam peristiwa Karbala tak lain merupakan matarantai yang mengarah pada satu titik; Tuhan. Memang, perjuangan Imam salah satunya adalah menuntut hak kuasa politiknya. Namun sangat kontras dengan maksud-maksud Yazid bin Muawiyah (musuh Imam yang otomatis menjadi musuh pecinta Imam), Imam tidak memburunya demi kuasa itu sendiri, melainkan untuk dijadikan sarana menuntun umat manusia melangkah di jalan kebenaran.
Dengan demikian, peristiwa Karbala adalah cara memandang kehidupan dari sudut yang khas dan bercorak Ilahi (divine angle). Jelasnya, ia bukan hanya layak ditatap dari paradigma ketuhanan, melainkan bahkan seutuhnya merupakan paradigma atau cara pandang ketuhanan itu sendiri. Sebagai TradisiLalu partikel-partikel yang berhamburan dari peristiwa Karbala masuk ke pori-pori tubuh, untuk kemudian merasuki jauh ke lubuk hati dan pikiran para pecinta Ahlul Bait lewat proses pewarisan dari generasi ke generasi. Proses perasukan dan pewarisan ini menjadi begitu krusial mengingat tragedi Karbala, sebagaimana telah dikemukakan, merupakan cara pandang ketuhanan.
Persoalannya, bagaimana kita yang hidup di alam [pasca]modern ini dan jauh dari zaman terjadinya peristiwa itu, membaca dan memperlakukan tradisi atau warisan berharga ini? Bila tradisi ini dibaca agak kekiri-kirian (Marxisme), akan diperoleh kesimpulan bahwa Karbala adalah representasi dari perjuangan kelas tertindas secara ekonomi (memang, Imam Husain dan kebanyakan pengikutnya adalah kaum terpinggir secara ekonomi, sekalipun bukan karena terpaksa, melainkan karena pilihan sadarnya) vis a vis kelas penindas dari kalangan istana. Karenanya, tradisi ini harus dibiarkan hidup sejauh dapat dijadikan instrumen perubahan dan perjuangan revolusioner melawan kaum kapitalis demi meratakan jalan bagi terbangunnya classless society (masyarakat tanpa kelas). Namun jargon yang terkesan sangat garang namun bombastis ini, boleh dibilang, "berupaya melucuti isi masa lalunya (content of the past) demi kepentingan (politik) masa kini dan ke depan".
Menurut pandangan ini, apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Yang terpenting hanyalah bagaimana memanfaatkan tradisi apapun, baik yang bersifat religius maupun tidak, demi kepentingan revolusi (dalam pengertian Marxian). Gaya membaca (reading-style) ini pada akhirnya akan menggiring pada sebuah bentuk fundamentalisme Marxisme utopis yang hanya sibuk mempersoalkan pembuktian kekuatan metodiknya yang bersifat dialektis ketimbang penerapannya di tengah masyarakat. Lain lagi bila tradisi ini dibaca agak ke kanan-kananan (Liberalisme, yang ditengarai al-Jabiri sebagai European-style). Menurut pandangan ini, bila dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan konteks kemodernan, maka tradisi ini harus dicampakkan. Apapun tradisi yang dirasa usang dan tidak kompatibel dengan kondisi kekinian (tepatnya, kekinian ala Barat) dianggap mengganggu proses modernisasi (yang menurut anggapan sementara orang, sebenarnya identik dengan proses westernisasi).
Sudah saatnya, kata mereka yang menganut pandangan ini, untuk mencita dan mencipta-minimal mereformasi-tradisi. Kedua cara membaca yang kini banyak digandrungi kalangan muda nyaris di seantero jagat ini pada dasarnya bersikap sama di hadapan tradisi. Bahwa nasib sebuah tradisi, khususnya Karbala, sepenuhnya berada di tangan orang-orang yang mewarisinya. Bedanya, kalangan pembaca Marxian mengapresiasinya sebagai alat revolusi, sementara kalangan pembaca Liberal menilainya berdasarkan kegunaan, kompatibilitas, dan relevansinya dengan konteks kekinian. Kesamaannya, kedua kubu pembaca ini tampak menghindar dari keharusan menganalisis kompleksitas dan kekhasan peristiwa Karbala yang memang sangat sulit dilakukan.
Menurut hemat saya, kedua bentuk pembacaan dan penyikapan ini terlampau subjektif, berjarak, dan menyederhanakan, selain khas antroposentrik dan sosialistik. Bagi keduanya, kita harus membuat jarak dan bersikap kritis(?) terhadap tradisi Karbala yang dianggap bermanfaat sejauh menyangkut perubahan formasi sosial (kaum Marxian) dan perubahan manusia sebagai individu (Liberal). Jelas, dengan itu, keduanya mereduksi tradisi Karbala dalam konteks kepentingan manusia atau sosial, bukan "kepentingan" Tuhan. Konsekuensinya, tradisi dalam terang kedua pandangan ini sulit dikatakan sebagai bercorak religius, kendati bersumber dari sejarah Islam.
Seyogianya tradisi Karbala diletakkan dan dihayati pertama kali dalam konteks teologis keislaman. Baik di tingkat pemikiran, maupun praktik personal dan sosial. Merawat, menghayati, dan menghidupkan tradisi Karbala tentunya bukan hanya bermakna menggelar peringatan seremonial tahunan-sekalipun ini tetap terbilang penting demi mempertahankan ingatan kolektif dan hubungan spiritual terhadap keagungan dan kesyahidan Imam Husain sekaligus sebagai sarana mengekspresikan rasa marah, sesal, dan sedih yang mengental pada kesiapan mengorbankan diri secara total. Tapi juga bermakna membangun peradaban.
Imam Khomeini pernah mengatakan bahwa peristiwa Asyura atau Karbala bukan hanya tragedi, tapi juga peradaban. Di sini, terkandung asumsi bahwa peristiwa tersebut bukan hanya mengacu pada suatu keadaan tragis dan memilukan per se di masa lalu, tapi juga sebuah proses konstruktif yang merambat ke masa depan yang dekat maupun jauh. Ya, peristiwa Karbala 14 abad silam dengan Imam Husain sebagai lokomotifnya adalah tonggak awal berdirinya sebuah peradaban mahaakbar. Dengan begitu, menghayati tradisi Karbala berarti melanjutkan proses pembangunan peradaban yang berdiri di atas basis Islam yang hakiki. Justru kurang tepat bila kita terus asyik tenggelam dalam kedukaan yang mendalam serta menyesali begitu saja tragedi yang terjadi 14 abad silam itu. Sementara pada saat yang sama, kita mengabaikan persoalan yang sesungguhnya dan jauh lebih urgen; yakni mentransformasikan kepedihan, rasa marah, sesal, dan emosi mendalam, serta hasrat menggebu menjadi bahan baku dan inspirasi untuk menata bangunan peradaban ilahiah yang dilukiskan Imam Husain itu dengan darahnya yang suci. Sebagai Simbol
Simbol merupakan produk atau ekspresi dari kesadaran estetik yang dihasilkan lewat kekuatan imajinasi atau intuisi. Dalam hal ini, simbol erat berhubungan secara timbal balik dengan gagasan. Lewat sebuah proses kreatif, gagasan diubah dalam bentuk ringkas namun padat dan bernuansa magis ke dalam simbol; begitu pula sebaliknya, simbol diubah dan diurai menjadi sebuah gagasan.
Kesyahidan yang digagas Imam Husain dalam drama Karbala telah menjadi simbol perlawanan dan pembebasan kebenaran dari cengkraman tirani dan penindasan. Simbolisasi semacam ini tentu saja bersifat kontekstual, dalam arti, selalu relevan disuarakan dan diusung di setiap ruang dan waktu. Namun, yang patut disayangkan, banyak pihak (sebut saja, kaum kontekstualis) yang secara serampangan justru melakukan kontekstualisasi peristiwa Karbala jauh atau bahkan terputus dari teksnya (fenomena Karbala sebagaimana [dituturkan] apa adanya dan bersifat harfiah-kronologis). Selain barangkali dipicu semangat yang berlebihan untuk menjadikan Karbala sebagai tradisi yang hidup, munculnya gejala ini umumnya didorong oleh semacam kekhawatiran terjebak dalam apa yang disebut kaum liberal sebagai sindrom "pemberhalaan teks". Padahal dengan sikap semacam itu, justru mereka diam-diam terjebak dalam apa yang saya istilahkan dengan "pemberhalaan konteks".
Sebagaimana kaum Marxis dalam hal perubahan, atau kaum Liberal dalam hal kegunaan, kaum kontekstualis menganggp konteks sebagai segala-galanya. Akibatnya, nilai historis bahkan teologis peristiwa Karbala menjadi kabur dan tidak penting, serta para figur besar yang terlibat di dalamnya hanya menjadi sekadar bait-bait nama yang layak dikenang sebagai pahlawan! Darinya lantas bermunculan upaya analogi-simbol yang gegabah dan terkesan dipaksakan. Misal, kericuhan Ambon dan Poso di Indonesia dewasa ini (yang umum dipercaya kaum Muslimin sebagai peperangan antaragama) dianggap, entah bagaimana, sebagai analog Karbala di abad XXI. Bahwa kaum Muslimin di Ambon atau Poso tengah mengalami ketidakadilan dan penindasan, sebagaimana yang secara garis besar terjadi di Karbala. Analogi ini jelas-jelas sangat tidak memperhitungkan kualitas historis peristiwa Karbala yang otentik. Sejauh bermaksud membumikan semangat Karbala dalam konteks kekinian, analogi kuantitatif semacam itu memang layak dihargai. Tapi tidakkah ia menjadikan bobot historis Karbala itu sendiri menjadi nihil? Sebagai teks, peristiwa Karbala merupakan momentum kebangkitan melawan kezaliman dan penindasan di masa silam. Namun begitu, subjek dalam teks bukanlah kebangkitan itu sendiri (yang hakikatnya merupakan predikat), melainkan para figur yang mengikhtiarkannya. Karenanya, pertama-tama, apresiasi terhadap teks Karbala seyogianya terfokus pada subjek atau tokoh pemerannya. Baru setelah itu, apresiasi diarahkan pada peristiwa berikut makna yang dikandungnya. Perlu dicatat, peristiwa historis apapun tak mungkin lepas dari konteks yang meliputinya saat itu.
Nah, seyogianya upaya kontekstualisasi merujuk pada figur dan konteks yang khas peristiwa tersebut. Bila tidak, niscaya akan terjadi apa yang disebut sebagai fenomena ketercerabutan atas nama konteks. Inilah yang akan menghantarkan kita pada bentuk keterasingan identitas (aleniaty of identity) yang amat berbahaya. Bukan hanya identitas yang telah mengakar dalam tradisi Karbala di masa lalu, tapi juga yang mempengaruhi gerak sejarah dan peradaban.
Ala kulli hal, tugas selanjutnya yang terkait dengan relasi timbal balik antara simbol dan gagasan adalah menerjemah dan mengurai simbol Karbala menjadi gagasan yang kreatif dan membangun. Ikhtiar ini telah banyak dilakukan dari waktu ke waktu oleh para pemikir dan ulama besar sepanjang sejarah pasca-Karbala. Contohnya, sebagaimana ungkapan Imam Khomeini di atas. Tugas berat ini tentunya bukan sekadar tugas linguistik atau semiotik, karena bertaut erat dengan kualitas pencecapan, penghayatan, dan kecintaan kita pada manusia ilahi seperti Imam Husain. Inilah Karbalaisme… Wallâhu a'lam
Penulis adalah aktivis Ikatan Pemuda Ahlul Bait (IPABI) Bogor dan Komunitas Muslim Inklusif (Kosmik) Jakarta.
Pendidikan terakhir pascasarjana di Islamic College for Advanced Studies (ICAS) Jakarta.