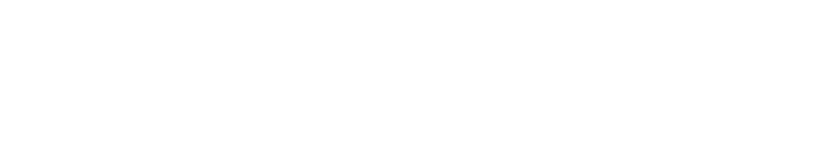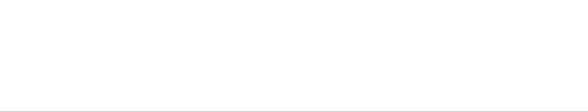Manusia setiap saat menjadi buah bibir semua agama. Para tokoh lintas agama selalu membicarakan dia tanpa ada habisnya. Agama, bila pembicaraannya tentang Tuhan, saat itu dipastikan sebenarnya ia sedang berbicara tentang dan kepada manusia. Begitu pula ketika berbicara tentang alam, hewan dan lainnya. Jadi, topik semua pembicaraan agama dan yang menjadi lawan bicaranya adalah manusia.
Entah berapa banyak agama di dunia ini dengan segala macam alirannya, semuanya adalah tentang manusia. Mereka seakan berebut untuk mendapat simpati dari manusia. Namun hal ini tidak ada dalam kamus agama samawi, bahwa agama “mengemis” kepada manusia supaya dianuti olehnya. Tetapi justru sebaliknya, manusia lah yang membutuhkan agama.
Dalam keyakinan terkait dengan dasar-dasar agama, dan sampai pada pilihan tak lebih dari dua kemungkinan, apakah yang ini ataukah yang itu, harus diuji kebenaran keyakinan seseorang pada satu di antara keduanya. Seperti adakah tuhan, haruskah wahyu di sanding akal, adakah kehidupan lain setelah kehidupan dunia, ataukah tidak? Mengharuskan ia buktikan apakah benar yang diyakininya. Atau, ia tergolong orang-orang yang dalam keagamaan mereka mengikuti para pendahulu mereka secara buta. Allah berfirman:
Bahkan mereka berkata, “Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka.”
Dua Penafsiran tentang Keadilan Tuhan
Salah satu pembicaraan klasik tentang manusia terkait dengan tindakan batinnya, apakah ia bebas berkehendak ataukah tidak? Jika tidak, berarti manusia adalah makhluk determinis, dalam keterpaksaan dan tidak mempunyai pilihan atau ikhtiar. Maka apapun yang dia lakukan bukan atas kehendaknya, melainkan atas kehendak di luar dirinya.
Pembahasan tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Syahid Mutahahari dalam bukunya “Keadilan Ilahi”, adalah perkara antropologis. Menjadi teologis apabila bersinggungan dengan masalah qadha` dan qadar serta kehendak Tuhan. jika menyangkut masalah hukum alam, seperti kausalitas dan faktor-faktor alami lainnya, apakah hukumnya meniadakan kebebasan manusia ataukah tidak, maka pembahasannya di ruang kosmologi.
Dengan kata lain, permasalahan jabr (determinsme) dan ikhtiar atau bebas berkehendak pada manusia, menyeret perhatian si pengkaji pada masalah keadilan Tuhan. Karena dua masalah ini saling berkaitan. Artinya, jika manusia tidak punya pilihan atau dalam keterpaksaan, berarti dia sepenuhnya dikendalikan oleh kehendak Tuhan, dan hukum alam menafikan ikhtiar baginya. Hal ini membawa kesimpulan bahwa semua taklif yang Allah berikan kepada manusia, dan pahala serta dosa atas apa yang dia perbuat menjadi tidak berarti.
Berbeda dengan apabila manusia di dalam berbuat, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan beretika baik ialah berdasarkan ikhtiarnya. Sehingga tidaklah sia-sia semua kebaikan yang telah dia lakukan selama hidupnya, dan menjadi berarti.
Dua sudut pandang tersebut terlihat jelas berseberangan. Kendati keduanya sama-sama meyakini keadilan Tuhan, dan bahwa kezaliman mustahil disifati oleh-Nya, tetapi di ranah penafsiran tentang keadilan-Nya, berbeda satu dengan lainnya.
Menurut teori determinis (jabr), keadilan ilahi bukanlah bahwa Allah bertindak sesuai aturan keadilan. Satu misal, seandainya Dia dengan kehendak-Nya tidak memberi pahala berupa surga bagi hamba-Nya yang taat, bagaimanapun yang Dia perbuat terhadapnya adalah adil. Secara ringkas, bahwa keadilan bukan tolok ukur tindakan Tuhan, tetapi tindakan-Nya lah sebagai tolok ukur keadilan.
Sedangkan menurut teori ikhtiar, keadilan ilahi adalah sebuah realitas dan bahwa Allah swt Maha adil dalam arti hanya Dia lah satu-satunya eksistensi adil yang sempurna (The Just) dan hikmah yang mutlak (All-wise). Dengan demikian Dia pasti dan selalu bertindak adil serta berdasarkan keadilan.
Pandangan Tafwidh
Masih terkait dengan dua teori tersebut secara lebih luas, dengan menoleh pada manusia dan tindakan lahirnya atau perbuatannya, bahwa apakah perbuatan-perbuatannya seperti jujur dan dusta, amanat dan khianat dan sebagainya adalah bersifat baik dan buruk secara esensial? Sepintas demikian, lalu apakah perbuatan-perbuatan itu dalam segala kondisi bernilai baik dan buruk, ataukah tidak?
Mampukah manusia dengan akalnya memberikan penilaian terhadap perbuatan-perbuatannya itu, ataukah tidak? Dalam arti bahwa dia yang berakal tidak memiliki independensi di dalam penilaian itu! Tetapi memerlukan petunjuk dari agama, karena hanya syariat agama yang memiliki kemampuan ini!
Determinisme –setelah penafsirannya di atas yang mengingkari keadilan sebagai tolok ukur tindakan- mengatakan bahwa baik dan buruk itu tidaklah esensial. Tetapi bersifat relatif dan kondisional, dan bahwa akal dalam menilai baik dan buruknya suatu perbuatan bergantung pada petunjuk syariat.
Sedangkan teori ikhtiar memandang esensialitas baik dan buruk, bahwa baik pada esensinya adalah baik dan buruk pada esensinya adalah buruk. Kemudian selain itu, akal manusia mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan yang buruk, tanpa ditunjuki oleh syarat agama.
Perselisihan antara dua teori ini memuncak ketika Mu’tazilah dengan teori ikhtiarnya melampaui batas, yang diistilahkan dengan tafwîdh. Yakni, totalitas kebebasan manusia dalam berkehendak yang lepas dari kehendak Tuhan. Dengan pandangannya yang “terjun bebas” ini, ia tak bisa menjawab kritikan dari Asyariyah, bahwa keadilan dalam arti mencakup: ikhtiar manusia, kelogisan baik dan buruk dan keterikatan tindakan Allah swt dengan tujuan-tujuan di balik semua tindakan-Nya, adalah bertentangan dengan tauhid af’ali (tauhid dalam perbuatan) Allah swt, bahkan bertentangan dengan kemaha esaan-Nya itu sendiri!.
Catatan kaki:
1-QS: az-Zukhruf 22: