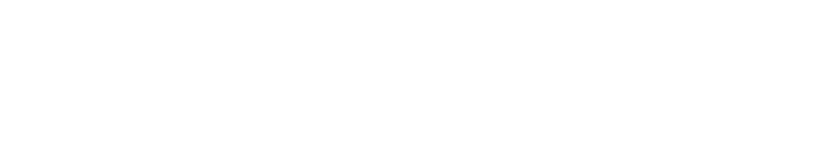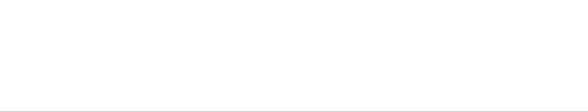Mayoritas pemikir abad 19 dan 20 memprediksi bahwa seiring dengan kemajuan sains dan tekhnologi, agama akan semakin terpinggirkan, bahkan musnah sama sekali. Auguste Comte meramalkan bahwa masa depan adalah masa kaum positivis-saintis, masa teologis segera akan menjadi masa lalu. Karl Marx mensistematisir perkembangan sejarah yang berakhir dengan terbentuknya masyarakat komunis internasional, di mana ketidakrelevanan agama dalam kehidupan publik akan semakin diakui, diapun menyebut agama sebagai candu. Nietzche dalam refleksi filsafatnya menyebut, Tuhan telah mati. Max Weber meramalkan semakin merebaknya kesadaran rasional individu, yang secara langsung mengikis motivasi teologis dalam kehidupan. Sedang Huston Smith dalam Why Religion Matters: The Fate of the Human Spirit in an Age of Disbelief mempertanyakan, apakah agama akan menemukan ajalnya?.
Namun dalam konteks Indonesia, ramalan para pemikir ini salah besar. Kita dapat menyaksikan bagaimana masyarakat kota dan pedesaan semakin religius. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, melalui survei nasional menunjukkan tentang adanya trend kenaikan religiusitas tersebut per tahun. Peningkatan religiusitas ini dapat diukur dengan fakta bahwa semakin banyak bermunculan gerakan-gerakan kegamaan yang diorganisir dalam bentuk organisasi-organisasi modern, kaum perempuan Islam yang mengenakan jilbab, semakin ramainya tempat-tempat ibadah, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ibadah, semakin banyak dan kuatnya komitmen masyarakat terhadap agama yang dianutnya dan lain-lain. Namun realitas ini sangat paradoks dengan tingkat intoleransi masyarakat yang juga meningkat. Berbagai bentuk kerusuhan disertai penjarahan bahkan pembunuhan banyak terjadi di beberapa daerah sejak tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998 sampai sekarang, menunjukkan peningkatan religiusitas berelevansi dengan kefanatikan dan tingkat intoleransi dengan penganut agama lain. Dan belum tampak semuanya akan berakhir, konflik laten bisa saja manifes dengan alasan yang sangat sederhana sekalipun Yang menyedihkan, tindakan anarkis dan kekerasan sering mengatasnamakan agama sebagai pembenar.
Lahirnya Indonesia dan Toleransi
Pada dasarnya, sejak dahulu rakyat di negeri ini sadar dengan adanya kemajemukan bangsa. Namun kemajemukan itu tidaklah dijadikan dalih untuk saling menyudutkan, justru dijadikan sebagai kekuatan pemersatu menuju terbentuknya republik. Kelompok nasionalis berlatar belakang sekuler, kalangan agamis (Islam), dan kelompok komunis melakukan konsolidasi di bawah payung ideologis bernama keindonesiaan. Perlulah kiranya selalu kita ingat bersama-sama bahwa Sumpah Pemuda, yang dilahirkan sebagai hasil Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta adalah manifestasi yang gemilang dari hasrat kuat kalangan muda Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama, untuk menggalang persatuan bangsa dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Atas prakarsa Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) inilah kongres pemuda itu telah melahirkan Sumpah Pemuda yang berisi: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa yaitu Indonesia.
Republik Indonesia lahir 17 tahun kemudian, yang dijiwai semangat kebersamaan, persatuan, dan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Semua pihak turut ambil andil dalam lahirnya republik. Meskipun ummat Islam mayoritas namun tak bisa dinafikan bahwa ada umat Khonghucu (Yap Tjwan Bing) yang menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Perlu dicatat pula bahwa sewaktu teks Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dibacakan, tempatnya di rumah seorang Tionghoa Khonghucu bernama Sie Kong Liong, di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta (yang sekarang dijadikan Museum Sumpah Pemuda). Ataupun kendaraan Kepresidenan pertama adalah mobil sumbangan seorang Tionghoa sebagai bentuk kecintaannya kepada republik yang baru terbentuk. Ini perlu dinukilkan karena masih saja ada anggapan, suku Tionghoa tidak memberi andil apa-apa dalam terbentuknya Republik Indonesia.
Toleransi kebangsaan lagi-lagi dipertontonkan para founding father negeri ini, dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. 10 November 1945 dalam kalender sejarah bangsa kita dicatat sebagai hari lahirnya pahlawan-pahlawan bangsa, yang rela mati demi tegaknya sebuah negeri bernama Indonesia. Tanpa mempersoalkan suku, agama dan ras rakyat Indonesia saling membahu dalam menghadapi musuh bersama. Tentara sekutu sesumbar dapat menguasai Surabaya dalam 3 hari, namun pertempuran memakan waktu berminggu-minggu, meskipun tentara sekutu mengerahkan kekuatan penuh, namun tidak mudah menundukkan semangat rakyat yang merajut kebersamaan dalam berbagai perbedaan. Tentara sekutu tersentak dan akhirnya paham. Indonesia yang baru berusia 3 bulan, bukan bangsa kecil. Persatuan dan semangat toleran adalah kekuataan yang maha dahsyat, yang tidak tertundukkan. Karenanya tak bisa dipungkiri, rangkaian perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah terbukti begitu kokoh dalam pijakan kemajemukan bangsa, mulai dari suku, agama, ras hingga budaya
Toleransi Antar Umat Beragama
Toleransi beragama yang tinggi sedari dulu telah ditunjukkan oleh umat beragama di Indonesia, baik yang Muslim, Kristiani maupun yang lainnya. Apabila satu pemeluk agama tertentu suatu ketika membangun tempat ibadah, tidak jarang kemudian dibantu oleh umat agama lain. Demikian halnya dalam pembangunan Mesjid Agung Istiqlal. Mesjid yang merupakan mesjid terbesar di Asia Tenggara pada masanya, dalam proses pembangunannya telah menyimpan satu sejarah toleransi beragama yang sangat tinggi. Disebutkan demikian, karena sang arsitek dari mesjid tersebut adalah seorang penganut Kristen Protestan yang taat. Friedrich Silaban yang oleh Bung Karno menjulukinya sebagai “by the grace of God” karena kemenangannya mengikuti sayembara desain Mesjid Istiqlal. Kebesaran jiwa dari umat Islam sangat jelas terlihat disini. Mereka mau menerima pemikiran atau desain tempat ibadah mereka dari seorang yang non muslim.
Mesjid yang diniatkan untuk melambangkan kejayaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mesjid yang merupakan suatu bangunan monumental kebanggaan seluruh umat Islam di Indonesia, di desain dan wakil kepala proyek pembangunannya dijabat oleh seorang Kristiani. Dia menciptakan karya besar untuk saudaranya sebangsa yang beragama Islam, tanpa mengorbankan keyakinannya pada agama yang dianutnya. Ummat Islampun menunjukkan kebesaran jiwanya dan penghargaan kepada Friedrich Silaban dengan menyebut Qubah Mesjid Istiqlal sebagai “Si1aban Dom”, atau Qubah Si1aban. Silaban dan kaum beragama di negeri ini mengukir sejarah, suatu sejarah yang lebih tinggi dari karya sebuah hasil seni atau teknologi. Sejarah kemanusiaan, kebersamaan, toleransi yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun.
Karenanya, keanekaragaman yang selama ini ada menjadi tonggak “bineka tunggal ika” yang kuat dalam menopang berdirinya bangsa Indonesia, mesti tetap dipertahankan. Pluralitas dan multikulturalitas bagi bangsa ini merupakan suatu keniscayaan; sesuatu yang memang harus ada dan tak terbantahkan. Pluralitas dan multikulturalitas yang kita miliki ini telah menciptakan mozaik yang indah dalam tampilan fisik manusia dan budaya Indonesia di sepanjang perjalanan sejarahnya. Sungguh memilukan melihat nilai-nilai pluralitas dan multikulturalitas yang telah tumbuh sejak awal terbentuknya republik ini, di kekekinian seolah-seolah tidak pernah ada. Sementara di sisi lain, eksklusivisme kelompok justru terlihat semakin menonjol. Maka sesungguhnya tak ada satu pun pihak, tak satupun suku, tak satupun agama, yang bisa mengakui keberadaannya tanpa andil pihak lain. Tak satupun.
Tak bisa kita pungkiri, kita adalah bagian dari orang lain; ada sebagian dari orang lain dalam diri kita. Mengutip Emha Ainun Nadjib, “Kamu adalah aku yang lain”. Sikap dan penerimaan kultural seperti ini tidak akan memberi izin atau permisi kepada siapa pun untuk arogan, menganggap dirinya lebih benar, dan merasa berhak untuk menghakimi pihak lain. Dengan sikap seperti itu, kita pun dapat terhindar dari pelbagai cedera sosial yang belakangan ini menimpa bangsa kita melalui konflik-konflik horizontal maupun vertikal, intelektual maupun fisikal.
source : abna24