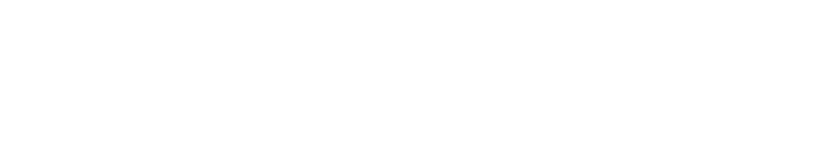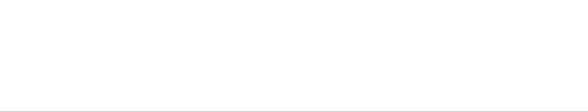Malcolm X penah memberikan pesan penting, “Jika engkau tidak hati-hati, koran-koran [media massa] akan membuatmu membenci orang yang sedang ditindas, dan mencintai orang yang menindas.” Pesan tersebut semakin relevan di tengah derasnya informasi dari media massa. Pasalnya, berita yang diproduksi media massa tidak lepas dari kepentingan ekonomi politik dan ideologi pihak pemegang kendali media, termasuk pemilik media dan wartawan sendiri.
Phillip Knightley dalam bukunya The First Casualty membeberkan sekitar 3.000 pekerja media menempel menjadi jurnalis tertanam (embedded Journalism) dalam Operation Allied Force NATO di Kosovo, yang berlangsung antara 24 Maret hingga 10 Juni 1999. Demikian pula dengan perang lainnya, seperti invasi AS ke Irak, hingga serangan NATO ke Libya yang memporak-porandakan negara kaya minyak itu. Meskipun harus diakui ada sejumlah jurnalis independen yang masih objektif, tapi jumlahnya kecil dan pengaruhnya kalah jauh dengan jurnalis media mainstream.
Para peneliti seperti Brandenburg (2007) dan Pfau (2004) menilai jurnalis tertanam cenderung mengaburkan batas-batas antara militer dan media.Wartawan justru menjadi bagian dari korp militer dan kehilangan jarak yang dibutuhkan terhadap subjek, serta menghasilkan bidikan yang lebih terbatas. Aday, Sean, Steven Livingston dan Maeve Hebert (2005) dalam penelitiannya “Embedding The Truth: A Cross-Cultural Analysis of Objectivity and Television of the Iraq War” memperlihatkan bagaimana jurnalisme tertanam cenderung fokus pada perspektif militer dalam pemberitaannya yang bias.
Barangkali, itulah sebabnya Stuart Hall dalam “The Rediscovery of Ideology (1982:64)” menyatakan bahwa realitas tidaklah secara sederhana dapat dilihat sebagai satu set fakta, tapi hasil dari ideologi atau pandangan tertentu. Media massa menentukan realitas melalui pemilahan dan pemilihan, mana yang boleh dan yang tidak boleh ditampilkan sebagai berita. Pemberitaan tentang operasiHumanitarian Intervention yang ditabuh media mainstream terhadap sebuah negara tertentu, tidak lain dari intervensi negara-negara kuat terhadap lawan politiknya yang harus disingkirkan, maupun definisi dari pemilik modal raksasa global terhadap negara yang akan dikeruk sumber dayanya. Fakta di Suriah, Libya dan Irak mempertontonkan bagaimana media arus besar melayani kepentingan imperialisme dan kapitalisme global. Tujuannya, bagaimana publik dunia percaya dengan “memori konon” yang diproduksi oleh media mainstream tersebut. Konon berkonotasi berita dari mulut ke mulut, gosip, kabar-kabur, tak jelas sumbernya. Dari memori konon inilah banyak orang percaya berita yang tidak pernah diverifikasi kebenarannya itu.
Pada kasus pemberitaan tentang nuklir sipil Iran oleh media mainstream, apa yang ditampilkan tidak lain dari suara kepentingan Washington sebagai lawan politik Tehran. Tapi, saking besarnya pengaruh media mainstream, begitu banyak orang yang percaya Iran berambisi membuat senjata nuklir. Padahal, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei sudah mengeluarkan fatwa haram memproduksi senjata nuklir. Selain itu, program nuklir Iran juga berada dalam pengawasan ketat IAEA. Pada saat yang sama, ancaman nuklir militer Israel nyaris tidak pernah muncul dalam memori kolektif masyarakat dunia. Mengapa media membiarkan Israel menolak penyelidikan instalasi nuklirnya oleh IAEA, padahal jelas bertujuan militer, dan terbukti memiliki ratusan hulu ledak nuklir. Menurut laporan Bulletin of the Atomic Science (2004), jumlah hulu ledak nuklir Israel menduduki urutan kelima di dunia. Demikian juga dengan AS, memori publik dunia jarang disodori pemberitaan tentang program nuklir AS yang terbukti memproduksi senjata nuklir terbesar di dunia, selain Rusia.
Tampaknya, memori kolektif publik dunia terlalu sesak dijejali berita konon dari media mainstream tentang kediktatoran Assad yang harus digulingkan oleh rakyatnya yang menginginkan demokratisasi. Pada saat yang sama, memori publik dunia tidak menyimpan penolakan negara-negara monarki Arab terhadap demokratisasi, karena memang tidak muncul dalam berita-berita media mainstream. Fakta ini memperkuat tesis Foucault bahwa realitas adalah konstruksi sosial yang dibentuk melalui wacana, sebagai penentu cara berpikir kebanyakan orang dengan jalan tertentu, bukan yang lain.
Kini, penyebaran memori konon menyebabkan konflik di sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Irak dan Suriah, semakin berkobar menjadi konflik internasional. Penyebaran memori konon “Assad yang Syiah yang menindas rakyat Sunni di Suriah” atau “konflik Sunni-Syiah di Irak” menjadi pemantik, meski bukan satu-satunya, keterlibatan para militan dari berbagai negara, termasuk Indonesia untuk berjihad. Gendang itu semakin keras bertalu-talu di Tanah Air.
Memori Konon dan Media Intoleran
Keran kebebasan pers yang dibuka lebar-lebar pasca jatuhnya Orde Baru, ternyata tidak didukung oleh kedewasaan sebagian media massa Indonesia. Kondisi tersebut diperparah dengan menjamurnya media-media “kompor” sektarian yang memanaskan suhu intoleransi di Tanah Air. Laporan berbagai LSM seperti Setara Institute misalnya, menunjukkan terjadinya eskalasi intolerasi di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Di sejumlah kota besar digelar pertemuan yang berisi ujaran kebencian (hate speech) terhadap kelompok minoritas.
Studi Critical Analysis Discourse menunjukkan akutnya pola eksklusi (exclusion) yang dilakukan media-media garis keras Islam terhadap kelompok lain yang dipandang berbeda seperti Syiah, dengan menyematkan memori konon, berbentuk “Syiah Sesat”. Keabsahan memori konon ini tidak diverifikasi. Misalnya, Syiah dinilai sesat karena konon al-Qurannya berbeda. Padahal tudingan tersebut tidak pernah terbukti hingga kini. Faktanya, al-Quran yang ada di Iran sebagai negara dengan mayoritas penganut Syiah terbesar di dunia, sama dengan Sunni. Pada tahap yang lebih jauh, setelah eksklusi terjadi marjinalisasi dan delegitimasi dengan membenturkan representasi publik dan ikatan sosial dalam bentuk slogan “Syiah bukan Islam”.
Belajar dari krisis yang menimpa sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara, isu sektarian menjadi sumbu yang paling efektif untuk menghancurkan sebuah bangsa. Mari kita jaga keutuhan NKRI. Seperti pesan Malcolm X di awal tulisan ini, “If you’re not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed, and loving the people who are doing the oppressing.”
*Purkon Hidayat, Peneliti Indonesia Centre for Middle East Studies
source : abna