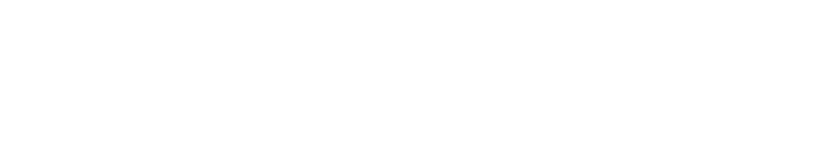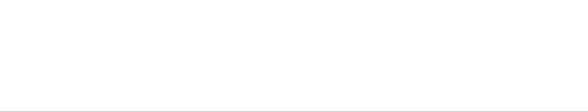Waktu itu, malam tahun baru. Usai sholat maghrib, kami
mengadakan pengajian singkat menyambut tahun baru. Saya
menyarankan agar masing-masing merenungkan makna tahun
baru bagi dirinya. Jamaah diam. Pengajian tampak
seperti upacara mengheningkan cipta. Kami tesentak
ketika Wak Haji, yang tertua diantara kami, memecahkan
kesunyian, “Saya kira tidak layak menyambut tahun baru
dengan pesta. Bukankah tahun baru adalah berita duka?
Bukankah setiap tahun baru mengantarkan kita lebih
dekat ke kuburan? Pada tahun-tahun yang lalu, maut
telah mengambil kawan kawan atau keluarga kita. Lalu,
siapa yang akan dijemput maut tahun ini?”
Wak Haji sudah berusia 89 tahun, walaupun tampak sehat
dan kuat. Ia taat beribadah, selalu salat berjama’ah.
Ia datang ke Mesjid sejam sebelum azan subuh. Walaupun
hidup dalam usai senja, ia senang bercanda. Karena itu
agak mengherankan bila tahun ini ia kedengaran pesimis.
Mungkinkah itu pertanda bahwa boleh jadi tahun ini ia
meninggalkan kami?
“Apakah orang saleh takut menghadapi kematian?” tanya
seseorang yang mengarahkan pertanyaanya kepada saya.
“Saya selalu dihantu rasa takut mati. Mungkin karena
saya tidak saleh. Wak Haji benar. Tahun baru adalah
berita duka. Seperti napi yang akan dihukum gantung,
saya melihat, setiap dentang jam membawa saya lebih
dekat ke tiang gantungan. Adakah kiat untuk mengobati
takut mati ?”
Saya jawab bahwa orang saleh pun takut mati. Salah
seorang cucu Rasulullah dikenal sebagai Wali Allah. Ia
banyak beribadah, sehingga diberi gelar Zayn
al-’Abidin. Tapi dengarkan doanya, “Kepada-Mu aku
berlindung dari habisnya usia sebelum siap sedia”. Jadi
orang saleh pun takut mati. Yang membedakan kita dengan
orang saleh adalah alasan yang menyebabkan takut mati
Kita takut mati karena keterikatan dengan dunia. Kalau
saya mati, siapa yang akan menjaga kepentingan anak-
anak saya, siapa yang akan mengurus perusahaan saya,
siapa yang mengamankan kekayaan saya. Orang saleh takut
mati karena ia merasa belum cukup bekal. Ia khawatir
akan “habisnya usia sebelum siap sedia”. Dalam doa yang
lain, Zayn al-’Abidin berkata, “Siapa gerangan yang
keadaannya lebih jelek dari diriku, jika dipindahkan
dalam keadaanku sepeti ini, aku dipindahkan ke
kuburanku. Aku belum menyiapkan pembaringanku. Aku
belum menghamparkan amal saleh untuk tikarku. Bagaimana
aku tidak menangis, padahal aku tidak tahu akhir
perjalananku. Kulihat nafsu menipuku dan hari-hari
melengahkanku. Padahal maut telah mengepak-ngepakan
sayapnya di atas kepalaku. Bagaimana aku tidak
menangis, kalau kukenang saat aku menghembuskan nafas
yang terakhir. Aku menangis karena kegelapan kubur, aku
menangis karena kesempitan lahadku; aku menangis karena
aku akan keluar dari kuburku dalam keadaan telanjang,
hina, sambil memikul dosa di atas punggungku.”
Walhasil, kalau takut mati karena belum cukup bekal,
peliharalah rasa takut itu. Tidak perlu kita
menghilangkannya. Ingat kepada kematian mendorong
manusia berbuat baik. Ia akan menjadikan amal saleh
sebagai bekal untuk kehidupan sesudah kematian. Sadar
akan kematian berarti sadar akan ketiaadaan Ego dan
“non-being”. Bila kita harus mengakhiri semuanya dengan
kematian, masih absahkah kebiasaan kita untuk terus-
menerus mengorbankan orang lain buat kepentingan kita?
Bukankah hidup kita menjadi lebih bermakna bila kita
“memberikan diri” kita buat kebahagiaan orang lain?
Dengan menghancurkan Ego, kita memasukkan orang lain
(the otherness) ke dalam eksistensi kita.
Joel Kovel mengamati dengan cermat dunia modern yang
disebutnya sebagai “dunia tanpa ruh”. Dalam “History
and Spirit: An Inquiry into the Spirit of Liberation”,
Kovel menawarkan pembebasan manusia dari Egonya dengan
memasukkan spiritulitas ke dalam kehidupan. Salah satu
caranya ialah menyadarkan manusia akan kematian.
“Termasuk ke dalam spiritualitas adalah kesediaan untuk
mati. Hidup yang bermakna adalah kehidupan yang telah
menerima orang lain dan mempersiapkan dirinya untuk
mati. Ini tidak berarti bahwa dia adalah wujud yang
ingin mati. Sebaliknya, jiwa sempurna memandang hidup
ini lebih indah dan lebih intens. Sungguh, kesadaran
akan adanya kematian, visi tentang bayangan maut, tidak
lain daripada menjadikan kehidupan sebagai titik
pandang utama”.
Tuhan mendampingkan kematian dan kehidupan pada ayat
yang sama, tetapi Dia menyebut kematian lebih dahulu
daripada kehidupan. Dia menegaskan bahwa kehidupan
hanya bermakna dengan latar belakang kematian. Keduanya
didampingkan sebagai ujian untuk mendorong manusia
beramal saleh. “Dia yang menjadikan kematian dan
kehidupan supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu
yang lebih baik amalnya” (QS 67:2). Rasulullah saw
mendampingkan maut dengan Al-Qur’an. Rasulullah
bersabda, “Aku tinggalkan bagi kalian dua pemberi
peringatan. Yang pertama memberikan peringatan dengan
pembicaraannya. Yang kedua memberikan peringatan dengan
kebisuannya. Yang pertama, Al-Qur’an dan yang kedua
adalah kematian”.
Ternyata Wak Haji yang tampak sehat dalam usianya yang
hampir seabad adalah orang yang mendengarkan peringatan
Al-Quran tentang kematian. Ketika permulaan tahun baru
mengingatkan banyak orang akan rencana hidupnya, Wak
Haji mengingatkan kita akan rencana kematian kita. Di
dekat Baitullah, saya melihat seorang mantan pejabat
tinggi berdoa dengan khusyuk. Air mata tergenang di
pelupuknya. Ia menyadari, ia berada pada hari-hari
akhir hidupnya. Ia pulang ke tanah air. Di hadapan
anak-anaknya, ia berkata, “Hidup kita akan lebih
bermakna bila kita bermanfa’at bagi orang lain”.
Seperti Wak Haji, Al-Quran dan kematian telah
memberikan kepadanya kehidupan yang lebih manis dan
lebih mendalam. (*)
source : alhassanain