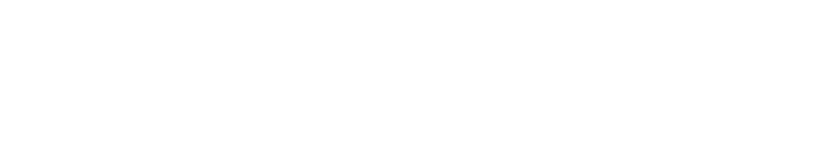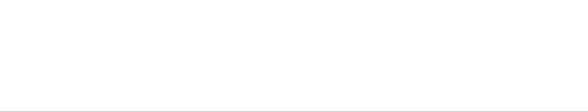Kata jihad cukup populer di dunia Islam temasuk di
Indonesia, bahkan tidak keliru jika dikatakan bahwa
jihad merupakan salah satu prinsip dasar ajaran Islam.
Sayang, kata ini sering kali dikerdilkan maknanya atau
dan digunakan bukan pada tempatnya.
Kata jihad terambil dari Bahasa Arab: jahd, yang pada
mulanya berarti kesulitan/kesukaran atau juhud, yakni
kemampuan. Kedua makna tersebut mengisyaratkan bahwa
jihad yang sebenarnya tidaklah mudah, tetapi dapat
menjadikan sang mujahid berhadapan dengan aneka
kesulitan dan kesukaran. Sang Mujahid juga dituntut
untuk tidak berhenti sebelum kemampuannya berakhir atau
cita-citanya terpenuhi. Itu sebabnya dalam perjuangan
merebut kemerdekaan, para mujahid/pejuang bangsa kita
berpekik, “Merdeka atau mati.”
Merujuk pada sumber-sumber ajaran Islam―al-Qur’an dan
Sunnah Nabi saw.―ditemukan aneka ragam jihad bermula
dari jihad dengan hati untuk melahirkan/mengukuhkan
tekad, dengan lidah untuk menjelaskan dan membuktikan
kebenaran, dengan tenaga, dengan harta, sampai dengan
nyawa, demi tegaknya nilai-nilai ajaran Islam:
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
“Siapa yang berjuang demi tegaknya kalimat Allah, maka
dia telah menelusuri sabilillah/jalan Allah.”
Demikian sabda Nabi saw. Jadi, tujuannya bukan
menumpahkan darah, apalagi membunuh, tetapi meninggikan
nilai-nilai agama Allah. Perlu dicatat bahwa salah satu
dari ajaran agama Allah adalah memberi kebebasan kepada
setiap penganut agama/kepercayaan untuk melaksanakan
tuntunan agama/kepercayaan mereka―walau tuntunan
tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Itu yang
ditegaskan oleh firman Allah yang pada mulanya
ditujukan kepada para kaum musyrik penyembah berhala,
“Lakum dînukum wa liya dîn.” Memang jika mereka
menghalangi kaum Muslimin untuk melaksanakan tuntunan
agama, maka sikap mereka harus dihadapi dengan cara apa
pun walau sampai tingkat pertempuran.
Atas dasar yang dikemukakan di atas adalah sangat
keliru membatasi makna jihad hanya pada peperangan
bersenjata. Bukankah Allah telah memerintahkan Nabi
Muhammad saw. untuk berjihad dengan menggunakan al-
Qur’an ketika beliau masih di Mekkah―dimana kekuatan
bersenjata ketika itu belum beliau miliki? Allah
berfirman:
فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًاكَبِيرًا
Janganlah patuh kepada orang-orang kafir dan
berjihadlah menghadapi mereka dengan al-Qur’an jihad
yang besar (QS. al-Furqân [25]: 52).
Jihad yang dimaksud di sini pasti bukan penggunaan
kekerasan, tetapi ia adalah berusaha dengan semua
kemampuan membulatkan tekad menghadapi kesulitan serta
upaya menjelaskan nilai-nilai agama kepada mereka yang
menentangnya.
Bukankah Allah memerintahkan Nabi saw. untuk berjihad
menghadapi orang-orang musyrik dan munafik?
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
Wahai Muhammad, berjuanglah melawan orang-orang kafir
yang menyatakan kekafirannya dan orang-orang munafik
yang menyembunyikan hakikat mereka dengan segala
kekuatan dan bukti yang kamu miliki. Bersikap keraslah
dalam berjuang melawan kedua kelompok tersebut. Tempat
tinggal mereka adalah Jahannam. Seburuk-buruk tempat
kembali adalah tempat mereka. (QS. at-Tahrîm [66]: 9)
Wahai Nabi, berjihadlah menghadapi orang-orang kafir
dan orang munafik dan bersikap tegaslah terhadap
mereka! Tempat mereka kelak di Jahannam dan itu adalah
seburuk-buruk tempat kembali (QS. at-Tahrîm [66]: 9 dan
at-Taubah [9]: 73).
Sejarah menjelaskan bahwa tidak seorang munafik pun
yang beliau hukum mati―walau pelanggaran beratnya telah
berulang kali seperti halnya pemimpin kaum munafik,
Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Sayyidina Umar
mengusulkan kepada Nabi saw. agar yang bersangkutan
dihukum mati, beliau bersabda: “Nanti orang akan
berkata bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya.”
Jika demikian, arti jihad pada ayat di atas pun
bukanlah penggunaan senjata/pertempuran.
Bukankah sangat populer riwayat yang menyatakan bahwa
Nabi saw. bersabda ketika kembali dari Perang Tabuk
bahwa: “Kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju
jihad yang besar?” Di sisi lain diriwayatkan bahwa
istri Nabi saw., as-Sayyidah ‘Aisyah pernah bertanya
kepada Nabi saw., “Apakah wanita wajib juga berjihad?”
Nabi memberi salah satu contoh dari jihad perempuan
dengan bersabda: “Jihad mereka Haji dan Umrah.” “Apakah
ada jihad tanpa peperangan?” Nabi menegaskan: “Ya. Ada
jihad tanpa pertempuran.”
Hal lain yang menunjukkan bahwa jihad bukanlah
bertujuan dasar membunuh atau melakukan kekerasan
adalah bahwa Nabi saw. dalam aneka pertempuran selalu
menawarkan kepada lawan―sebelum bertempur tiga
alternatif: a) Memeluk Islam atau b) Tetap memeluk
agama/kepercayaan mereka, tapi menjadi penduduk yang
baik dengan membayar jizyah (pajak sebagai imbalan
pembelaan terhadap mereka serta penggunaan mereka
terhadap fasilitas umum), atau c) Ditindak/diperangi
jika mereka menolak kedua tawaran tersebut. Penindakan
itu pun tidak otomatis berarti pembunuhan.
Dalam al-Qur’an, kata jihad dalam berbagai bentuknya
terulang sebanyak 41 kali. Umumnya bermakna upaya
sungguh-sungguh menjelaskan nilai-nilai ajaran Islam
serta membelanya. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa
yang dimaksud oleh al-Qur’an dan Sunnah dengan jihad
adalah berjuang menggunakan segala kemampuan dan daya
yang dimiliki untuk menghadapi segala macam musuh Islam
dan musuh kemanusiaan dalam berbagai bidang, segala
macam keburukan atau yang mengantar kepada keburukan.
Setiap Muslim berkewajiban melawan nafsu setan,
kebodohan, penyakit, kemiskinan dan lain-lain. Ini
berarti bahwa setiap Muslim wajib berjihad sepanjang
hayatnya. Ini demikian karena manusia memiliki dalam
dirinya potensi negatif dan positif. Dunia adalah arena
pertarungan antara kebaikan dan keburukan sehingga
dengan demikian jihad harus dilakukan sepanjang hayat
dan jihad harus berlanjut sampai kiamat karena
keburukan selalu ada dan beraneka ragam.
Jihad dan Ijtihad
Pada masa kejayaan Islam, jihad dalam berbagai bidang
itu terlaksana dengan baik serta didukung oleh apa yang
dinamai ijtihad, yang secara umum dapat diartikan
sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh guna
menemukan solusi keagamaan/hukum untuk aneka masalah
yang dihadapi umat/masyarakat. Tetapi ketika kelemahan
intelektual muncul dan kesimpang-siuran fatwa
merajalela sehingga membingungkan umat, lahirlah ide
menutup pintu ijtihad. Sehingga, ketika itu hampir
tidak ada lagi ide-ide baru yang sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Nah, ketika itu terjadi,
kepincangan antara kekuatan fisik negara dengan akal,
antara pedang dan pena. Salah satu akibatnya adalah
mengerdilkan makna jihad menjadi kekuatan fisik dan
pertempuran semata-mata, tidak lagi dipahami sebagai
upaya sungguh-sungguh menghadapi aneka musuh agama dan
kemanusiaan.
Dampak dari kenyataan di atas terlihat, antara lain
pada bangkitnya upaya memurnikan agama dan
mempertahankan apa yang diamalkan oleh Rasul saw. dan
sahabat-sahabat beliau. Mereka menolak pembaharuan,
bahkan mengabaikan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh
ulama-ulama―masa lampau sekalipun―yang menyatakan bahwa
ketetapan hukum harus mempertimbangkan ‘illat/sebab
ditetapkannya sehingga jika ‘illat-nya tidak ada lagi,
maka hukum pun tidak berlaku lagi.
Sebagai contoh, patung-patung dilarang karena dahulu ia
disembah, sehingga kini jika tidak disembah lagi, maka
mestinya yang ada tidak harus dihancurkan. Inilah yang
dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi saw., antara lain
oleh mereka yang ke Mesir yang hingga kini patung-
patung tersebut terpelihara dengan baik. Menurut para
pemurni agama itu, “Agama telah sempurna. Semua telah
dijelaskan dan dicontohkan oleh Rasul saw. sehingga
semua yang tidak beliau lakukan dan atau tidak
dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau adalah bid’ah
yang harus dilarang. Mereka bermaksud mengembalikan
masyarakat Islam ke masa Nabi saw. dan sahabat-sahabat
beliau yang mereka nilai bahwa itulah masa keemasan
Islam yang diperjuangkan dengan jihad dalam maknanya
yang terbatas. Kekhalifahan harus dikembalikan tanpa
mempertimbangkan berkembang dan mantapnya paham
Nasionalisme di seluruh persada bumi. Menghormati
bendera adalah syirik, Pancasila adalah kekufuran,
patung-patung bersejarah harus dihancurkan, perempuan
harus sangat dibatasi kegiatannya dan bisa jadi ada
yang berkata: Poligami harus digalakkan karena Nabi
saw. berpoligami dan lain sebagainya. Ini berarti bahwa
dasar-dasar kehidupan masyarakat yang diajarkan Islam
dan yang diterapkan untuk runtuh. Kebhinekaan dihapus,
candi-candi dan gereja-gereja dihancurkan. Sikap
semacam itu bukanlah isapan jempol, tetapi benar-benar
terbukti dalam kenyataan di wilayah-wilayah yang
dikuasai oleh ISIS Al-Qaedah di Timur Tengah dan Boko
Haram di Nigeria.
Persoalan tidak akan terlalu parah jika pandangan
mereka itu tidak disertai dengan semangat menggebu-gebu
untuk memperjuangkannya dengan berbagai cara kekerasan.
Gejala-gejala semacam itu mulai amat terasa dan
terlihat di Indonesia, antara lain dengan
bermunculannya aneka tulisan, lebih-lebih melalui dunia
maya yang menghidangkan kekerasan serta gencarnya
secara tuduhan dan fitnah terhadap sekian banyak tokoh
yang tidak sepaham dengan mereka. Padahal tokoh
tersebut tidak melakukan, kecuali mengajak umat
bersikap berpegang teguh dengan pandangan mayoritas
umat Islam sedunia, serta bersikap toleran dan
menghormati semua pendapat selama pendapat tersebut
bercirikan kedamaian. Tentu saja penghormatan itu tidak
otomatis berarti menerimanya.
Jihad dan Mujahadah
Mereka yang menyalahpahami pengertian jihad sebagaimana
yang diajarkan Islam, sering kali juga melupakan syarat
mutlak bagi tegaknya jihad dalam berbagai ragam dan
aspeknya, yakni apa yang diistilahkan dengan mujahadah.
Mujahadah adalah upaya menekan gejolak nafsu dan aneka
rayuan yang dapat mengalihkan seseorang dari tujuan
yang benar. Mujahadah dibutuhkan setiap saat, termasuk
ketika melaksanakan jihad, lebih-lebih dalam konteks
pertempuran. Ia dibutuhkan sebelum, pada saat, dan
sesudah pertempuran. Sebelum pertempuran, sang mujahid
dituntut memahami dan menghayati tujuan sambil
membentengi jiwanya dari aneka ambisi duniawi,
kepentingan pribadi atau kelompok. Saat pertempuran ia
harus selalu mengingat tujuan pertempuran sehingga ia
tidak terdorong untuk melakukannya akibat dendam
pribadi serta bersedia segera menghentikannya jika
tujuan telah tercapai atau jika tujuan telah menyimpang
dari apa yang dibenarkan agama. Sedang setelah usainya
pertempuran, ia masih dituntut untuk terus memelihara
hatinya agar jangan sampai kemenangan menjadikannya
angkuh atau berlaku sewenang-wenang terhadap pihak
lain.
Kesalahpahaman tentang Makna Jihad
Kesalahpahaman tentang makna jihad itu diperparah juga
melalui sekian banyak kitab, bahkan melalui terjemahan
beberapa ayat al-Qur’an. Misalnya kata qitâl tidak
jarang mereka pahami dalam arti pembunuhan, padahal
kata itu bermakna peperangan/kutukan, sikap tegas yang
tidak selalu mengakibatkan pembunuhan. Kata anfusikum
diartikan sebagai jiwa/nyawa, padahal ia berarti
seluruh totalitas manusia, yakni nyawa, atau fisik,
ilmu, tenaga, pikiran, bahkan waktu karena semua hal
tersebut tidak dapat dipisahkan dari totalitas manusia.
Para Radikalist itu memahami iman sebagai pembenaran
hati atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw.
disertai dengan pengamalannya sehingga menurut mereka
seseorang tidaklah dinilai beriman apabila tidak
melaksanakan ajaran Islam secara baik dan benar. Mereka
menilai bahwa kemusyrikan bukan sekadar keyakinan
tentang berbilangnya Tuhan, tetapi juga yang mengakui
keesaan-Nya tanpa mengamalkan syariat adalah seorang
yang boleh dibunuh. Tulisan menyangkut ide di atas
ditemukan, antara lain dalam buku yang tersebar di
sekian banyak sekolah di Indonesia, termasuk Jawa
Timur.
Mereka mengumandangkan bahwa “La hukma illâ lillâh”.
Semua pemerintahan yang tidak menetapkan hukum berdasar
ketentuan Allah adalah Thagût (melampaui batas ajaran
Islam) dan dinilai kafir, lagi harus diperangi.
Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,
Pemerintahannya pun mereka nilai Thagût/Tirani dan
kafir. Mereka merujuk pada firman Allah: “Siapa yang
tidak menetapkan sesuai dengan apa yang diturunkan
Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir) QS. al-
Mâ’idah [5]: 44). Kekeliruan mereka menurut para pakar
di bidang al-Qur’an dan Sunnah adalah memahami kata
kafir dalam arti sempit, padahal al-Qur’an menggunakan
kata itu untuk berbagai makna, seperti “tidak
bersyukur” (QS. Ibrâhîm [14]: 7) atau “berpecah belah”
(QS. Âli ‘Imrân [3]: 106). Memang kekufuran beraneka
ragam dan bertingkat-tingkat sehingga pada akhirnya
kekufuran dapat disimpulkan dalam arti melakukan
kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai/tujuan.
Puncaknya adalah mengingkari wujud/Keesaan Allah, dan
inilah yang menjadikan seseorang dinilai keluar dari
agama, itu pun tidak serta merta harus dibunuh.
Pemimpin Tertinggi Al-Azhar dewasa ini (sejak 2010 M),
Syaikh Ahmad ath-Thayyib, dalam makalahnya yang
disampaikan pada Muktamar Al-Azhar menghadapi
ekstremisme dan terorisme (Desember 2014 M), menyatakan
bahwa: “Kelompok Pengafiran modern pada mulanya lahir
di penjara-penjara dan tahanan-tahanan, didorong oleh
siasat penyiksaan yang diperlakukan terhadap pemuda-
pemuda yang bergabung dengan pergerakan-pergerakan
Islam. Mereka dituntut―ketika itu―(sebelum 1967 M)
untuk mengumumkan dukungan mereka terhadap penguasa.
Nah, ketika itu sebagian besar bersegera menandatangi
surat dukungan, tetapi sebagian kecil menolak dan
menilai sikap mereka yang mendukung itu adalah sikap
lemah dan menghindari pembelaan agama. Mereka bertahan
dalam pendiriannya dan berkeras mempertahankan sikap
penolakan. Lalu berberapa waktu kemudian, mereka
menjauh dari teman-teman mereka yang mendukung itu dan
menyatakan bahwa teman-teman mereka itu telah kafir
karena mendukung penguasa kafir. Mereka juga menilai
masyarakat dengan semua anggotanya telah kafir karena
mendukung penguasa kafir. Tidak ada gunanya shalat,
tidak juga puasa bagi mereka yang mendukung penguasa.
Cara untuk keluar dari kekufuran adalah bergabung
dengan para “mujahidin”. Inilah awal dari kemunculan
kelompok Pengafiran setelah kelompok al-Khawarij (masa
lalu) terbenam ditelan sejarah. Demikianlah lahir
fenomena pengafiran baru melalui pemuda-pemuda yang
tidak memiliki kemampuan ilmiah dan budaya―kecuali
semangat―dan reaksi yang tidak tepat serta balas dendam
si lemah atas penyiksa yang sewenang-wenang. Mereka
melakukan pengafiran karena itulah cara yang tercepat
untuk melukiskan keadaan mereka yang pahit itu.”
Jadi, radikalisme dan pengafiran bukan atas dasar
pemikiran yang sehat, atau argumen keagamaan yang
sahih, tetapi semata-mata keinginan balas dendam. Itu
kemudian disambut dengan antusias oleh mereka yang
tidak paham agama dan tergiur oleh janji-janji
perolehan surga serta sambutan bidadari-bidadari.
Demikian sedikit yang dapat diuraikan menyangkut makna
jihad dan implikasinya dalam kehidupan bermasyarakat.
Wa Allâh A’lam.
*Disampaikan dalam Sarasehan Formpimda dengan seluruh
elemen masyarakat daerah Jawa Timur oleh Kapolda Jatim di Surabaya.
source : alhassanain