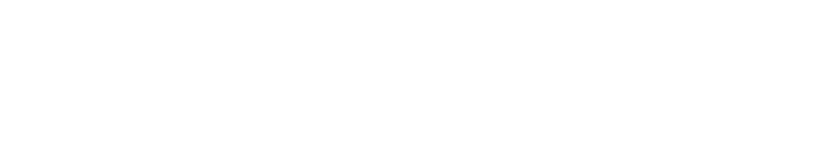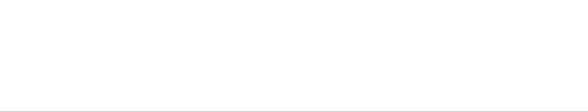ABSTRAK
Visi antropokosmik menegaskan dunia sebagai objek tidak dapat dipisahkan dengan manusia sebagai subjek. Kegunaan pengetahuan tidak untuk memanipulasi dunia tetapi untuk memahami dunia dan diri kita sendiri sedemikian sehingga kita dapat memenuhi kesempurnaan kemanusiaan kita. Penulis menyoroti masalah ini dalam kerangka hikmah (wisdom) karena disiplin ini menghasilkan tokoh-tokoh yang dirujuk oleh sejarahwan Barat dan ilmuwan dunia modern Muslim sekarang ini. Pendekatan ini telah mendiskusikan signifikansi keberadaan dan kemenjadian tanpa mengisyarakatkan kepercayaan kepada dogma Islam.
+++
SAYA mengambil ungkapan “visi antropokosmik” dari Tu Weiming, Direktur Harvard-Institute Yenching dan Profesor Sejarah dan Filsafat Cina dan Penelitian Konfusu pada Universitas Harvard. Sudah lama Profesor Tu menggunakan ungkapan ini untuk membungkus pandangan dunia Asia Timur dan memberi penekanan perbedaannya yang potensial dengan pandangan dunia Barat yang teosentrik dan antroposentrik. Dengan mengatakan bahwa tradisi Cina secara umum dan Konfusu secara khusus memandang benda-benda “secara antropokosmik”, dia bermaksud mengatakan bahwa manusia dan kosmos dipahami sebagai satu kesatuan yang tunggal dan organik. Tujuan manusia hidup adalah untuk mengharmonisasi dirinya sendiri dengan langit dan bumi serta kembali kepada sumber pencipta manusia maupun jagad raya. Sepanjang kebudayaan Cina tetap benar bagi dirinya sendiri, ia tidak akan pernah mengembangkan “rasionalitas instrumental”, pandangan aliran Pencerahan di dunia Barat yang memandang bahwa dunia sebagai suatu konglomerasi objek-objek dan menganggap bahwa ilmu sebagai cara untuk memanipulasi dan mengontrol objek-objek. Dalam visi antropokosmik, dunia sebagai objek tidak dapat dipisahkan dengan manusia sebagai subjek. Kegunaan pengetahuan tidak untuk memanipulasi dunia tetapi untuk memahami dunia dan diri kita sendiri sedemikian sehingga kita dapat memenuhi kesempurnaan kemanusiaan kita. Tujuan arikel ini — dengan menggunakan salah satu frase yang menjadi favorit Tu Weiming — adalah “untuk belajar bagaimana menjadi manusia.” Sebagaimana dia telah menulis, “Jalan atau metode adalah sesuatu yang lebih merupakan aktualisasi otentisitas sifat alami manusia.”1
Dengan sedikit revisi dalam terminologi, gambaran Tu Weiming tentang visi antropokosmik Konfusu dapat dengan mudah digunakan untuk menggambarkan cakupan pandangan dunia peradaban Islam secara umum dan pemikiran Islam secara khusus.2 Kata pemikiran Islam yang saya gunakan tidak merujuk pada berbagai disiplin keilmuan yang telah dikembangkan dalam dunia Islam, tetapi lebih mengacu pada pemikiran yang spesifik yang menyoal pertanyaan manusia yang paling dalam tentang tujuan akhir dan makna. Persoalan-persoalan ini merupakan pertanyaan yang menjadi perhatian para pemikir besar, filosof dan para ahli hikmah pada seluruh peradaban, khususnya pada tradisi filsafat/hikmah (wisdom) Islam. Saya paham bahwa kata “wisdom” dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai Hikmah yang mencakup filsafat yang telah terhelenisasikan dan berbagai perspektif lainnya, secara khusus disebut sufisme teoritis (apa yang sering dirujuk sebagai “irfan” atau “gnosis”). Saya memfokuskan pada tradisi hikmah (wisdom) dengan dua alasan. Pertama, di antara seluruh pendekatan Islam terhadap pengetahuan, hanya disiplin ini yang menghasilkan tokoh-tokoh yang dirujuk oleh sejarahwan Barat dan ilmuwan dunia modern Muslim sekarang ini. Kedua, hanya pendekatan ini yang telah mendiskusikan signifikansi keberadaan dan kemenjadian tanpa mengisyarakatkan kepercayaan kepada dogma Islam, sedemikian sehingga bahasannya dapat dengan mudah dipahami diluar konteks citra Islam yang khusus.
Dalam tataran terminologi ilmu-ilmu Islam, tradisi hikmah umumnya diklasifikasikan sebagai intelektual (aqliyyah) daripada bersifat periwayatan atau naqliyyah. Pengajaran yang berdasarkan periwayatan adalah seluruh pengetahuan yang disebarluaskan dari generasi awal yang tidak diperoleh melalui pemfungsian pikiran manusia pada dirinya sendiri. Contoh yang khas dari pengertian ini adalah bahasa, wahyu dan hukum. Pengajaran “Intelektual” adalah seluruh pengetahuan yang secara prinsip dapat diperoleh oleh kesadaran intelek manusia tanpa bantuan generasi terdahulu atau wahyu. Contoh yang gamblang adalah matematika dan astronomi. Akan tetapi, pengajaran intelektual juga termasuk apa yang kita sebut “metafisik”, “kosmologi” dan “psikologi”. Inilah tiga domain yang sangat eksplisit diinformasikan oleh visi antropokosmik yang akan saya diskusikan.
Pada kebudayaan Barat, sudah merupakan sesuatu yang umum untuk menggambarkan suatu perbedaan yang tajam antara pikiran dan wahyu, atau antara Athena dan Yerusalem. Pemahaman tentang perspektif Islam yang dominan dalam melihat pikiran dan wahyu sebagai sesuatu yang harmonis dan saling melengkapi —bukan sesuatu yang antagonistik — diperlukan untuk memahami peranan yang diperankan oleh ilmu-ilmu yang bersifat “intelektual” dalam tradisi Islam. Kandungan pesan-pesan al-Quran menghasilkan suatu cara pandang yang sangat berbeda yang dalam tradisi Kristen Barat menjadi suatu yang normatif. Tanpa memahami divergensi cara pandang, akan sangat sulit untuk memahami peranan yang telah diperankan oleh tradisi hikmah dalam Islam.
Jika Kristianitas mempertimbangkan pendikotomian pengertian pengetahuan intelektual dan pengetahuan periwayatan, maka apa yang melintas dalam benak kita adalah bahwa kebenaran pimer bersesuaian dengan hal-hal periwayatan yang ditransmisikan dari generasi ke generasi, bukan sesuatu yang bersifat inteleksi. Gagasan yang jelas dari pandangan dunia Kristen adalah inkarnasi yang dipahami sebagai suatu kejadian historis yang diketahui hadir pada dasar pengetahuan periwayatan. Lebih jelasnya, inkarnasi dipandang sebagai suatu intervensi Ketuhanan yang telah mengubah sejarah, dan ia juga dipahami sebagai kejadian yang sarat dengan aktualitas yang menyejarah. Ketika inkarnasi telah diakui, adalah mungkin untuk melihat bagaimana ia disimbolisasi ke dalam Keesaan Tuhan melalui logos dan trinitas. Meskipun keseluruhan tradisi pemikiran yang telah berkembang yang dimulai dengan ide-ide dalam intelek Ketuhanan yang dapat disebut “Kristianis Platonisme”, kandungan Kristen yang memuati tradisi ini tergantung pada fakta historis inkarnasi.
Tradisi Islam mempunyai perbedaan yang mencolok pada sudut pandangnya. Seringkali diasumsikan baik oleh Muslim atau non-Muslim bahwa Islam dimulai dengan fakta historis Muhammad dan al-Quran. Tentu saja hal ini mengandung beberapa kebenaran, akan tetapi hal ini bukanlah cara al-Quran merepresentasikan gagasannya, demikian juga hal ini bukanlah cara sebagian besar orang Islam memahami agamanya. Islam lebih tampak dimulai dengan penciptaan dunia. Dalam pengertian al-Quran yang paling luas, kata Islam (“penyerahan”, “kepenyerahan”, “menyerah”) menunjuk pada keuniversalan dan keberadaan makhluk berhadapan dengan Khaliq.3 Hal ini membantu penjelasan mengapa dogma agama yang utama dan mendasar tidak berhubungan dengan fakta-fakta historis Muhammad dan al-Quran. Secara sederhana inilah pengakuan suatu kebenaran universal, suatu kebenaran yang mengekspresikan sifat alami sesuatu untuk setiap waktu dan setiap kekekalan.4
Kebenaran utama yang menjadi sandaran pembentukan tradisi Islam dinyatakan dengan sangat singkat pada satu bagian pertama Syahadah, persaksian kepercayaan yang merupakan basis seluruh pengajaran dan praktik Islam. Pernyataan la ilaha illa Allah “Tidak ada Tuhan kecuali Allah”, suatu formula yang dikenal sebagai kalimat tauhid, kalimat yang menyatakan Keesaan Tuhan. Pernyataan ini menjadi deklarasi situasi aktual seluruh eksistensi, sebab setiap eksistensi itu telah berserah diri kepada Keesaan Tuhan dengan fakta eksistensinya. Seluruh makhluk mendeklarasikan Keesaan Khaliq dengan kepenciptaannya. Akan tetapi hal ini bukanlah suatu deklarasi ynag bebas, tetapi lebih merupakan suatu yang ditentukan oleh situasi aktual dari seluruh benda-benda. Hanya manusia yang mempunyai situasi khusus yang memungkinkan untuk menerima atau menolak kebenaran. Penerimaan bebasnya dideklarasikan dengan menyempurnakan bagian pertama syahadah dan oleh karena itu membuktikan bahwa Tuhan merupakan sumber yang unik bagi seluruh realitas. Al-Quran mengajarkan tauhid — pengakuan Keesaan Tuhan — dan penerimaan yang bebas sebagai konsekuensi tauhid kepada seluruh manusia yang telah memperoleh petunjuk dengan tepat yang orang pertamanya adalah Adam. Yang termasuk dari golongan ini adalah seluruh nabi — yang secara tradisional disebutkan berjumlah 124.000 — dan orang-orang yang mengikuti nabi dengan benar dan tulus.5
Dalam perspektif Islam, tauhid berdiri di luar sejarah dan periwayatan (naqliyyah). Inilah kebenaran yang universal yang tidak bersandar pada wahyu (yang bersifat tekstual, penerj.). Dengan demikian sesuatu yang mendasar adalah pengenalan kebenaran ini kepada situasi kemanusiaan yang secara khas menjadi kualitas yang inheren pada watak asli (fitrah) Adam dan seluruh keturunannya. Perlu diingat di sini bahwa dalam pandangan Islam, kejatuhan dari surga (al-jannah = kebun, penerj.) tidak merepresentasikan kelemahan yang serius. Akan tetapi hal itu menunjukkan ketergelinciran yang bersifat sementara, suatu tindakan tunggal kelupaan dan ketidakpatuhan. Adalah benar bahwa ketergelinciran mempunyai akibatnya sendiri, tetapi dengan segera ia diampuni oleh Tuhan, dan Adam ditunjuk sebagai nabi pertama. Tuhan telah menciptakan Adam dalam citra-Nya sendiri, dan citra ini tidak mungkin dicemari kesalahan, kecuali kalau citra Ketuhanan ini menjadi kabur pada sebagian besar cucu-cucu Adam.6
Berkenaan dengan tradisi historis Islam yang dimulai pada abad ketujuh dengan pewahyuan al-Quran. Persaksian keyakinan tidak diakui sampai ia mengakui bagian kedua syahadah yaitu pernyataan bahwa “Muhammad” adalah utusan Allah. Tauhid mendahului Muhammad dan pesan yang digambarkannya, sebab ia tidak berkaitan dengan sejarah. Tauhid lebih berkaitan dengan sifat alami realitas dan substansi intelegensi manusia.
Dalam perspektif ini, tauhid menerangkan seluruh struktur pengetahuan pada seluruh ruang dan waktu. Setiap nabi yang berjumlah 124.000 datang dengan suatu pesan yang didasarkan pada tauhid, dan setiap dari mereka mengajarkan tauhid secara eksplisit. Akan tetapi, mereka mengajarkan tauhid bukan karena manusia tidak mengetahui tentang tauhid. Mereka mengajarkan tauhid karena manusia telah lupa tentangnya dan mereka perlu diingatkan tentang tauhid itu. Kata dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mengungkap pengingatan adalah dzikr (bersama dengan derivatnya tadzkir, tadzkira dan dzikra) menunjukkan salah satu konsep yang paling penting dalam al-Quran. Ia menginformasikan kepada kaum Muslimin pada setiap tingkat kepercayaan dan praktis. Kata itu tidak hanya mengacu pada makna “remind”, tetapi juga mengacu pada makna “remember”. Makna yang mengacu pada “remind” mengindikasikan fungsi utama seorang nabi, dan makna yang mengacu pada “remember” menunjuk orang yang tepat dalam meresponi tugas kenabian. Seluruh proses “belajar menjadi manusia” pertama kali tergantung pada bagaimana mengingat tauhid dan selanjutnya tergantung pada pengingatan yang aktif dan bebas terhadap tauhid, suatu pernyataan tentang Keesaan Tuhan yang merupakan fitrah dari jiwa manusia.
Pada prinsipnya, tauhid, fundamen pengajaran Islam, berdiri di luar sejarah, sebab ia digelorakan di dalam sifat alami yang paling dalam pada setiap manusia dari Adam hingga manusia akhir zaman. Akan tetapi, untuk memahaminya tergantung pada pengingatan terhadapnya oleh seseorang yang mengetahuinya. Ketika ia dipahami, ia menjadi dikenali sebagai suatu kebenaran yang terbukti pada dirinya sendiri (swabukti), yang tidak ada kaitannya dengan wahyu yang menyejarah. Doktrin Islam yang menyatakan bahwa Adam merupakan nabi yang pertama menunjukkan suatu permisalan ide bahwa untuk menjadi manusia harus menghadirkan dalam dirinya sendiri — sebagai konsekuensi dari sesuatu yang diciptakan dari citra Tuhan — pengenalan Keesaan Tuhan.
Dengan memahami bahwa persaksian kepercayaan dalam Islam yang membedakan antara kebenaran yang universal – kebenaran yang tidak menyejarah – dan kebenaran yang partikular – kebenaran yang dikondisikan oleh sejarah – hal ini telah mengimplikasikan pembedaan antara pengetahuan yang bersifat intelektual dan pengetahuan yang didasarkan pada riwayat. Bagian pertama syahadah mendeklarasikan tauhid – suatu pengetahuan fitri yang ada di dalam watak asli manusia dan yang bebas dari partikularitas sejarah. Bagian kedua syahadah menunjuk pada fakta-fakta sejarah yang spesifik – fakta sejarah tentang kehadiran Muhammad dan pewahyuan al-Quran. Pengetahuan yang kedua ini tidak dapat diperoleh tanpa transmisi sejarah.
Meskipun pengetahuan yang diperoleh melalui riwayat dan yang diperoleh melalui intelek secara implisit dibedakan dalam prinsip pertama agama dan secara eksplisit dibedakan oleh tradisi terkemudian, hal ini tidak bermakna bahwa dua jenis pengetahuan itu dianggap sesuatu yang independen. Adalah jelas bahwa seluruh pemahaman agama tergantung pada periwayatan, jika yang dimaksud periwayatan itu adalah bahasa. Dan jelas pula bahwa periwayatan sendiri tidak menjamin terjadinya pemahaman. Hubungan antara dua modalitas pengetahuan ini mungkin dapat dipahami sebagai sesuatu yang komplementer, seperti yang ada pada yin-yang. Periwayatan diperlukan untuk mengaktualisasi pemahaman, dan pemahaman diperlukan untuk meresapi signifikansi riwayat.7
Di antara seluruh mazhab pemikiran Islam, filosof adalah kelompok yang paling hati-hati dalam membedakan pengajaran yang bersifat riwayat dan intelektual. Mereka sendiri tidak begitu tertarik dengan pengetahuan yang berdasarkan riwayat, sehingga mereka memberikan perhatian yang relatif kecil terhadap al-Quran, hadis dan disiplin yang lain seperti fiqh. Hal ini bukanlah untuk menolak bahwa sebagian besar mereka sangat menguasai ilmu yang berhubungan dengan al-Quran, atau bahwa sebagian dari mereka bahkan telah menulis tafsir al-Quran dan karya-karya dalam bidang fiqh. Meskipun beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa mereka tidak menaruh sikap antipati terhadap pengajaran yang bersifat riawayat, tampaknya mereka lebih menfokuskan perhatiannya di bidang lainnya. Mereka ingin mengembangkan visi intelektual mereka sendiri, dan mereka melihat bahwa hal ini sebagai tugas untuk mencapai apa yang diimplikasikan oleh tauhid.8 Jika mereka harus memahami signifikansi pengetahuan riwayat, mereka perlu mengivestigasi sifat alami Realitas yang tertinggi, struktur kosmos, dan realitas jiwa manusia. Inilah tiga domain yaitu metafisika, kosmologi dan psikologi yang telah disebutkan di muka. Akan tetapi, berkenaan dengan pemahaman, tauhid senantiasa akan mendasari aksioma. Filosof memahami bahwa tauhid adalah suatu anugrah pada setiap manusia, oleh karena itu setiap manusia dengan akal sehatnya akan melihat bahwa Keesaan Tuhan sebagai suatu kebenaran yang swabukti. Akan tetapi, mereka tidak mengenyampingkan untuk memperoleh sejumlah bukti lain untuk membantu intelek manusia dalam mengingat apa yang laten di dalam dirinya.
Hal yang paling mendasar di sini adalah bahwa intelek seorang Muslim – dalam pengertian yang spesifik tentang istilah intelek yang telah saya sebutkan – selalu melihat dirinya sendiri sebagai sesuatu yang sedang diinvestigasi dalam konteks deklarasi yang paling fundamental dalam tradisi Islam yaitu Keesaan Tuhan, Zat yang mengatur seluruh benda-benda. Intelek seorang Muslim tidak pernah melihat upayanya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dan kegunaan tradisi agama. Intelek tersebut menerima bahwa Nabi datang untuk mengingatkan manusia tentang tauhid dan mengajari mereka bagaimana menjadi manusia. Akan tetapi mereka percaya bahwa orang-orang awam mempunyai jalan yang berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh para elit filosof karena anugrah dan kecerdasan yang spesifik yang ada pada mereka. Mungkin sikap menjauhkan diri dari dogma agama dan menganggap ahli kalam dan ahli fiqh sebagai orang awam seringkali menyebabkan mereka menerima kritik yang pedas dari kaum Muslimin yang lain.
Dalam pandangan tradisi hikmah, para pencari pengetahuan intelektual mencoba untuk mempelajari bagaimana menjadi manusia dalam pengertian yang sesungguhnya sebagai seorang manusia yang diturunkan di atas bumi ini. Fokus utamanya selalu pada transformasi jiwa. Sebagaimana Tu Weiming katakan tentang visi antropokosmik konfusu, “Tindakan transformatif dipredikasi pada suatu visi transenden, yang dalam pengertian ontologis, kami adalah jauh lebih baik oleh karena itu lebih bermanfaat daripada kami dalam pengertian aktualnya.”9 Hal ini merupakan visi “humanistik”, dan humanisme diangkat jauh melebihi dunia, sebab “ukuran manusia” bukanlah manusia atau pemahaman rasional, tetapi lebih kepada sumber transenden bagi semuanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Tu:
Karena nilai manusia bukanlah sesuatu yang antroposentrik, pernyataan bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu bukanlah sesuatu yang cukup humanistik. Untuk benar-benar mengekspresikan humanitas kita, kita harus terlibat dalam suatu dialog dengan surga, sebab alam manusia — sebagaimana dianugrahkan oleh surga — menyadari alamnya bukan sebagai tempat pemberangkatan tetapi sebagai tempat kembali. Humanitas, sebagaimana dipahami, adalah suatu kepemilikan umum bagi kosmos bukan suatu kepemilikan pribadi dunia antropologis dan yang mengandung karakteristik keberadaan kita sebagai manifestasi kesadaran surgawi. Humanitas adalah bentuk surga ketersingkapan diri (self-disclosure), ekspresi diri (self-expression) dan kesadaran diri (self-realization). Jika kita gagal untuk menyempurnakan kemanusiaan kita, secara kosmologis kita gagal dalam misi kita sebagai khalifah (co-creator) di dunia dan surga dan secara moral dalam tugas kita sebagai peserta dalam transformasi kosmos yang agung.10
Dalam tradisi hikmah di dunia Islam, memahami secara utuh sifat alami humanitas kita mempersyaratkan adanya investigasi sifat alami seluruh benda dan realitas kita sendiri. Hal ini bermakna bahwa intelek tidak bisa membatasi dirinya sendiri hanya pada penerimaan pengajaran yang berupa riwayat. Intelek tidak bisa mengabaikan keinginan terdalam manusia untuk mencari pengetahuan dalam setiap domain, apalagi hal ini telah diperintahkan secara eksplisit oleh al-Quran untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam semesta sebagai cara untuk memahami Tuhan. Meskipun beberapa filosof sedikit memberi perhatian terhadap pengajaran yang didasarkan pada riwayat dan melihat dogma sebagai sesuatu yang menjijikkan, mereka tidak melangkah keluar dari tradisi Islam, sebab mereka tidak dapat meragukan aksioma yang universal dan ahistoris yang menjadi dasar dibangunnya tradisi Islam. Dengan kata lain, tidak ada celah sejarah dalam tameng inteleknya. Kemungkinan yang bersifat menyejarah tidak dapat menyentuh tauhid, karena ketika ia dipahami, ia akan tampak sebagai kebenaran yang swabukti yang pada muaranya secara fundamental ia menjadi ketentuan yang unik yang selalu menjadi sandaran jiwa.11
Sebagaimana ahli kalam dan ahli fiqh dan klaimnya terhadap otoritasnya dalam seluruh persoalan keagamaan, wakil dari tradisi hikmah melihat posisi mereka sebagai yang berhubungan dengan pengajaran riwayat, bukan pengajaran intelektual, dan mereka melihat tidak ada alasan untuk menyerahkan diri kepada pemahaman yang terbatas para pendogma yang saleh. Pada tingkat yang lebih luas mereka menjaga dirinya dari percekcokan dengan ahli kalam dan fiqh, dan kenyataan ini membantu untuk menerangkan mengapa mereka lebih menyukai menggunakan bahasa yang lebih diwarnai oleh gaya Yunani dari pada citra dan simbol-simbol dalam al-Quran.
Ketika kita memahami bahwa pengajaran “intelektual” Islam berada jauh dari pengajaran riwayat, kita dapat mulai mengerti mengapa upaya ilmu modern tidak pernah mempunyai tempat dalam Islam. Ilmu modern memperoleh kekuatannya dari penolakannya terhadap berbagai jenis teleologi, pemisahan yang jelas antara subjek dan objek, penolakan untuk mengakui bahwa kesadaran lebih real dibandingkan fakta-fakta material, perhatian yang eksklusif pada domain indera dan ketidakpedulian terhadap yang Mahaakhir dan transenden. Rasionalitas instrumental pengetahuan ilmiah dapat muncul di Barat hanya setelah bayi dipisahkan dari kamar mandi. Dengan menolak kamar mandi teologi – atau paling tidak relevansi dogma teologi terhadap kepekaan ilmiah – para filosof Barat dan ilmuwan juga menolak kebenaran tauhid dan dasar intelegensi manusia. Ketika tauhid dianggap sebagai surat yang usang, setiap domain pengajaran dapat dianggap sebagai sesuatu yang independen terhadap yang lainnya.
Tentu saja rasionalitas instrumental tidak muncul tiba-tiba di Barat. Sejarah yang panjang dan kompleks secara gradual menyebabkan pemisahan secara total domain pikiran dan wahyu. Banyak ilmuwan dan filosof tetap menjalankan ajaran-ajaran Kristen, tetapi hal ini tidak mencegah mereka untuk menganggap bahwa domain rasional sebagai sesuatu yang terbebas dari kungkungan hal-hal yang berhubungan dengan wahyu. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, sebab hal-hal yang berhubungan dengan wahyu akan disikapi sebagai sebuah pengajaran riwayat dalam terminologi yang dogmatis dan menyejarah yang memisahkan antara pikiran dan wahyu. Sebaliknya, tradisi intelektual Islam senantiasa berakar pada tauhid, bukan pada dogma teologis. Bukanlah persoalan jenis keraguan yang bagaimanakah yang telah diidap oleh para pemikir Muslim yang kritis yang mungkin telah menjadi stimulasi pertanyaan tentang kemungkinan historis bahasa Arab, kejadian-kejadian di sekitar kedatangan Muhammad, periwayatan pewahyuan al-Quran, dan interpretasi pewahyuan al-Quran oleh ahli kalam dan ahli fiqh, keraguan-keraguan ini tidak pernah dapat menggeser wawasan dasar tauhid mereka yang telah tercerahkan.
Selanjutnya kesimpulan awal saya adalah: Sebagian besar sejarahwan berpendapat bahwa pengajaran Islam abad pertengahan mengalami penurunan ketika ilmuwan Muslim mengabaikan untuk melakukan pengembangan penemuan-penemuan awal mereka. Akan tetapi hal ini terlalu bersandar pada sejarah Islam dalam terminologi ideologi kemajuan yang pada kenyataannya didasarkan pada saintisme kotemporer — yaitu kepercayaan bahwa sains mempunyai semacam kepastian yang unik yang menjadi suatu tempat untuk menerangkan kebenaran. Saintisme memberikan konsekuensi yang absolut kepada teori-teori sains dan merelatifkan seluruh pendekatan pengetahuan lain, jika teori-teori itu dianggap mendapat legitamasi dari selain kaidah-kaidah sains.
Selanjutnya, sejarawan yang menyatakan bahwa telah terjadi penurunan sains Islam mengabaikan dua konteks historis.12 Yang pertama adalah konteks Islam yang mana aksioma tauhid telah mendasari seluruh ikhtiar intelektual. Tauhid mendeklarasikan kesalinghubungan antar segala sesuatu, sebab ia menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari Prinsip Pertama, segala sesuatu disinambungkan secara konstan dan dipelihara oleh Prinsip Pertama, dan segala sesuatu akan kembali ke Prinsip Pertama. Dengan mengasumsikan bahwa intelektual Muslim memandang segala sesuatu berawal, tumbuh dan berakhir di dalam batas Satu Sumber, mereka tidak dapat membagi-bagi domain realitas kecuali dengan cara-cara yang tentatif. Mereka tidak dapat melepaskan pengetahuan tentang kosmos dari pengetahuan tentang Tuhan atau dari pengetahuan tentang jiwa manusia. Adalah tidak mungkin bagi mereka membayangkan dunia dan dirinya terpisah satu sama lain dan terpisah dari Prinsip Pertama. Sangat berbalikan dengan pemahaman Barat, semakin mereka menginvestigasi alam semesta, maka mereka semakin melihat alam semesta sebagai manifestasi prinsip-prinsip tauhid dan sifat alami manusia itu sendiri. Mereka mesti bersepakat dengan Tu Weiming yang menulis, “Untuk melihat alam sebagai suatu objek eksternal terdapat suatu keharusan untuk menciptakan batas buatan yang menghalangi visi kita yang benar dan membongkar kemampuan kemanusiaan kita untuk mengalami alam dari dalam.”13
Konteks kedua yang diabaikan oleh orang-orang ketika mereka mengklaim bahwa penurunan tradisi intelektual Muslim adalah Kristen. Peradaban Kristen qua peradaban Kristen pada kenyataannya mengalami penurunan, sebab ia mengalami keterpecahan pandangan dunia sintetik dan kemunduran Kristen yang Platonis. Periwayatan yang menjadi karakter dasar bagi basis agama yang ada tidak mampu bertahan terhadap pertanyaan-pertanyaan kritis pemikir-pemikir non-dogmatis. Dalam kasus Islam, intelektual Muslim tidak tergantung pada pewahyuan dan periwayatan untuk pemahaman tauhid, sehingga pertentangan teologis dan ketidakmestian sejarah tidak menjadi persoalan-persoalan yang serius.14
Untuk menyimpulkan beberapa implikasi visi antropokosmik, saya perlu memperluas perbedaan antara intelektual dan periwayatan. Ulama dalam pengertian seorang ahli dalam pengajaran riwayat telah mengklaim otoritas bagi pengetahuannya dengan menjunjung tinggi otentisitas riwayat dan kebenaran yang tinggi bagi orang yang menyediakan pengetahuan tersebut, yaitu Tuhan, Muhammad dan orang-orang terdahulu yang saleh. Mereka meminta agar setiap Muslim menerima pengetahuan ini sebagaimana ia telah diterima oleh mereka. Kwajiban dasar seorang Muslim adalah taqlid yaitu “mencontoh” atau tunduk kepada otoritas pengetahuan riwayat. Sebaliknya, tradisi intelektual menyeru kepada sejumlah kecil manusia yang mempunyai bakat intelektual. Pencarian pengetahuan merupakan sesuatu yang telah ditentukan tidak dalam terminologi taqlid atau imitasi tetapi dalam terminologi tahqiq, “verifikasi” dan “realisasi.”
Kunci penting untuk memahami perbedaan sudut pandang sains modern dan tradisi intelektual Islam terletak pada dua konsep. Kecuali jika kita memahami bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui verifikasi dan realisasi adalah sesuatu yang tidak sama dengan pengetahuan yang diperoleh dengan imitasi, kita tidak akan dapat memahami apa yang telah dicoba dilakukan oleh intelektual Muslim dan apa yang sedang dicoba dilakukan oleh ilmuwan dan sarjana modern. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menfalsifikasi posisi filosof Muslim dengan menempatkan mereka sebagai perintis jalan sains modern, seolah-olah mereka mencoba untuk mencari apa yang dicari oleh ilmuwan modern, dan seolah-olah mereka menerima penemuan pendahulu mereka dengan asas imitasi, sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan moderen.16
Kata dalam bahasa Arab tahqiq atau verifikasi/realisasi berasal dari kata haq. Haq adalah sebuah kata verbal sekaligus kata sifat. Ia berarti benar, kebenaran, menjadi benar; dan dengan permutasi yang sama (dalam bahasa Inggris, penerj.), dia bermakna real, right, proper, just, appropriate. Kata memainkan peranan penting dalam al-Quran dan pada seluruh cabang-cabang pengajaran Islam. Makna awal haq adalah sama dengan nama Tuhan. Tuhan sebagai al-Haq bermakna Kebenaran Absolut, Rightness, Reality, Properness, Justness, dan Appropriateness.
Tahqiq adalah kata kerja transitif dan intensif yang berasal dari kata haq. Ia bermakna menegaskan dan memastikan kebenaran, kenyataan dan ketepatan. Menegaskan adalah upaya untuk mengetahui sesuatu tanpa ragu. Satu-satunya tempat di mana kepastian dapat kita temukan adalah di dalam diri manusia, bukan di luar diri itu. Tahqiq adalah upaya untuk memahami dan mengaktualkan kebenaran dan realitas di dalam diri sendiri, menyadarinya dan membuatnya aktual pada dan di dalam diri sendiri.
Kata haq digunakan untuk Tuhan, sebab Tuhan adalah kebenaran, kenyataan dan ketepatan yang absolut. Tetapi ia juga digunakan untuk segala sesuatu selain Tuhan. Aplikasi kedua kata haq itu mengakui bahwa segala sesuatu di alam semesta mempunyai suatu kebenaran, kenyataan dan ketepatan. Jika Tuhan adalah al-Haq dalam pengertian yang absolut, sedangkan segala sesuatu selain Tuhan adalah haq dalam pengertian yang relatif. Tugas tahqiq adalah untuk membangun pengetahuan dengan tingkat kebenaran yang absolut, yang diawali dengan aksioma tauhid, dan memahami karakter yang benar dari kebenaran relatif yang bersinggungan dengan segala sesuatu, atau paling tidak dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kita, apakah itu bersifat spiritualitas, intelektualitas, psikologis, fisik atau sosiologis.
Formula tauhid dapat membantu kita untuk memahami tujuan tahqiq. Jika dikatakan “tidak ada tuhan selain Tuhan,“ hal ini bermakna, “tidak ada haq kecuali Haq yang absolut.” Kebenaran dan realitas yang haq hanyalah Tuhan sendiri. Haq yang absolut adalah transenden, tidak terbatas dan abadi. Di hadapan Haq yang absolut, tidak haq yang lain. Pada saat yang sama, segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, dan mereka menerima apa yang mereka punyai dari Tuhan. Tuhan menciptakan mereka dengan hikmah dan tujuan, dan setiap dari mereka mempunyai peranan di dalam alam semesta. Tidak ada yang eksis di alam ini mengandungi secara inheren sesuatu yang batil – lawan dari haq, yang berarti kesalahan, kesia-siaan, tidak nyata, tidak tepat.17 Kebenaran benda-benda individual ditentukan oleh kebijaksanaan Tuhan dalam penciptaan. Hal ini berhubungan dengan kebenaran-kebenaran (haq) individu yang telah diperintahkan Nabi kepada manusia “untuk memberikan kepada setiap segala sesuatu yang mempunyai haq haq-nya” (ita’ kull dzi haq haqqu). Memberikan setiap segala sesuatu haq-nya seringkali didefinisikan dengan tahqiq.
Memberikan kepada benda-benda haq-nya adalah jelas lebih dari sekadar suatu aktivitas kognitif yang sederhana. Kita tidak dapat memberikan kepada benda-benda haknya hanya dengan mengetahui kebenaran dan realitasnya. Jauh dari hanya sekadar mengetahui, tahqiq membutuhkan tindakan. Ia tidak sekadar memverifikasi dan menyadari kebenaran dan kerealitaan suatu benda dengan cara yang benar dan tepat. Tradisi intelektual selalu mempertimbangkan moralitas dan etika sebagai suatu bagian pencarian hikmah, dan sebagian besar wakil-wakil mereka melakukan upaya sadar untuk menyintesis pengajaran etika dan moral Yunani dan etika al-Quran.
Selanjutnya, tugas pencari hikmah adalah untuk memverifikasi dan menyadari benda-benda. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan mengutip opini Aristoteles atau Plato, atau bahkan dengan mencomot kata-kata dari al-Quran dan hadis. Memverifikasi dan menyadari benda-benda adalah dengan mengetahui benda-benda itu sebagaimana dia eksis dan bertindak dengan tepat. Yang lebih penting lagi, pencarian intelektual adalah suatu jalan mendisiplinan diri yang ketat dan tujuannya untuk mencapai pengetahuan yang benar tentang diri dan aktivitas yang tepat yang didasarkan pada pengetahuan yang telah diperoleh tersebut. Tak satu pun yang dapat menjadi tabir terhadap semangat pencarian intelektual dan pribahasa suci yang sangat terkenal yang dilekatkan pada diri Nabi, “Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia mengetahui Tuhannya”. Para sejarahwan menganggap bahwa pernyataan ini adalah versi Islam perkataan Socrates, “Mengetahui diri.” Tentunya, fakta bahwa versi pernyataan ini mengaitkan antara pengetahuan tentang diri dengan pengetahuan tentang Tuhan merupakan indikasi kepentingan yang primer yang selalu ada pada tauhid.
Adalah jelas bagi setiap orang bahwa seseorang tidak dapat mengetahui dirinya sendiri dan Tuhannya dengan menghafal opini-opini Ibn Sina. Tentu saja seseorang dapat mengambil para nabi dan filosof sebagai penunjuk pada jalan pengetahuan diri, tetapi seseorang tidak dapat mengklaim mengetahui tentang apa yang telah diketahu oleh para nabi dan filosof kecuali jika seseorang menemukan pengetahuan itu pada dan di dalam dirinya sendiri. Pencarian hikmah merupakan suatu aktivitas personal yang intensif, suatu disiplin spiritual yang membutuhkan latihan pikiran dan pengasahan jiwa seseorang. Memverifikasi dan menyadari benda-benda adalah upaya untuk mencapai visi yang otentik tentang realitas, persepsi yang benar tentang dunia, pemahaman tentang diri, dan pengetahuan yang benar tentang Prinsip Pertama. Pada saat yang sama, harus bertindak mengikuti seseorang yang telah sampai pada tingkat mengetahui. Hal ini membutuhkan suatu visi etis dan aktivitas yang benar.
Untuk memahami maksud tahqiq, akan bermanfaat untuk menggambarkan bagaimana para filosof memahami kata aql, kata benda yang memberi kita bentuk kata sifatnya yaitu aqli — yang telah saya terjemahkan dengan “intelektual.” Aql berarti intelek, intelegensi, pikiran, jiwa. Untuk memahami apa yang dimaksud suatu kata, kita perlu menelaah beberapa pengajaran dasar tradisi intelektual. Pengajaran ini menyediakan petunjuk ke arah pengetahuan yang dicoba oleh intelektual Muslim untuk diverifikasi dan disadari. Pengajaran-pengajaran itu tidak boleh disikapi sebagai suatu dogma, sebab tidak seorangpun dapat menyadari sesuatu dengan menghafal buku catatan. Untuk menyadari sesuatu seseorang harus menemukan jatidirinya sendiri.
Tentang Jiwa Manusia
Subtansi yang mendasari manusia disebut nafs, suatu kata yang berfungsi sebagai kata ganti refleksif yang sangat penting dalam bahasa Arab. Nafs umumnya diterjemahkan baik dengan “diri” atau pun “jiwa.” Dalam pengertian filosofisnya, ia menunjukkan sesuatu yang tidak kelihatan yang membuat penampakan sesuatu di dalam kosmos di mana saja ada kehidupan, dan oleh karena itu ia dianggap menjadi asal bagi setiap benda-benda hidup.
Memverifikasi sifat alami jiwa adalah suatu aktivitas mendasar bagi intelektual seorang Muslim. Suatu cara standar untuk melakukan hal itu yaitu dimulai dengan menginvestigasi penampakan jiwa pada dunia nyata. Realitas yang tampak merupakan suatu konglomerasi penampakan-penampakan yang mentubuh, meskipun kita secara instingtif membedakan di antara benda-benda dalam pengertian modalitas penampakannya. Kita mengetahui perbedaan antara benda hidup dan benda mati dengan tepat dengan melihat penampakannya. “Jiwa” adalah nama generik untuk kekuatan yang tak nampak yang menunjukkan dirinya sendiri ketika kita mengenali kehidupan dan kesadaran. Selanjutnya, dalam tindakan mengenali jiwa di dalam benda-benda lain, kita secara simultan mengenalinya di dalam diri kita sendiri. Untuk mengetahui penampakan jiwa di dunia luar, kita harus mengalami jiwa di dunia bagian dalam. Kehidupan dan kesadaran adalah kualitas-kualitas yang dapat kita temukan dalam diri kita dan di dalam tindak pengamatan kualitas-kualitas itu pada diri yang lain.
Terdapat tingkatan jiwa yang dapat dikatakan bahwa kekuatan yang tak tampak ini lebih kuat dan berpengaruh pada beberapa benda dibandingkan benda yang lainnya.18 Pengklasifikasian makhluk menjadi benda mati, tanaman, hewan, manusia dan malaikat adalah satu cara pengakuan terhadap tingkatan itu. Jiwa yang paling kuat dan pada saat yang sama yang paling kompleks dan berlapis-lapis ditemukan pada manusia. Dari sisi luar, hal ini nampak di dalam diversitas aktivitas-aktivitasnya yang tak terbatas yang dengan jelas berkaitan dengan berbagai perbedaan dalam hal bakat dan kemampuan. Oleh karena kekuatan yang beragam dan komprehensif dari jiwanya, manusia dapat memahami dan mereplikasi seluruh aktivitas yang hadir di dunia dengan menggunakan modalitas-modalitas jiwa lainnya.
Dalam diskusi jiwa manusia, teks-teks seringkali mengelaborasi hubungan yang erat antara jiwa dan kosmos. Kesamaan antara jiwa dan dunia dapat dianggap sebagai bayangan-banyangan dalam cermin. Sebagai dua bayangan yang terefleksikan secara mutual, maka mereka seringkali disebut “mikrokosmos” dan “makrokosmos.”
Korespondensi antara mikrokosmos dan makrokosmos dipahami sebagai sesuatu yang seperti hubungan subjek-objek. Jiwa manusia adalah subjek yang sadar yang dapat memahami objeknya yaitu dunia secara keseluruhan. Karena jalinan yang erat antara jiwa dan alam semesta – dalam terminologi Tu Weiming – maka hubungan keduanya dapat kita sebut “organismik”. Jiwa manusia dan dunia dapat dilihat sebagai satu organisme dengan dua wajah. Hal ini berdasar pada kenyataan bahwa tidak akan dapat ada mikrokosmos tanpa makrokosmos, dan tidak ada makrokosmos tanpa mikrokosmos. Peranan vital kosmik manusia adalah sesuatu yang tak terbantah. Telah diketahui bahwa makrokosmos hadir dalam realitas yang terindera sebelum manusia, tetapi dipahami juga bahwa makrokosmos dicipta sebagai eksisten secara tepat agar ia memungkinkan bagi manusia untuk hadir dan kemudian belajar bagaimana menjadi manusia. Tanpa kehadiran manusia (atau seorang yang dapat menerawang keberadaan-keberadaan analogi), maka tidak ada alasan bagi alam semesta untuk eksis pada urutan yang pertama. Teleologi selalu diakui.
Dalam bahasa yang lebih religius, hal ini dapat dikatakan bahwa Tuhan telah menciptakan dunia dengan tujuan penobatan yang spesifik ketercapaiannya kepada manusia; yang hanya dialah yang diciptakan secara utuh dari citra-Nya dan mampu berfungsi sebagai khalifah. Hanya mereka yang dapat mencintai Tuhan, sebab cinta yang sejati membutuhkan cinta si pencinta untuk dirinya sendiri. Jika seseorang mencintai Tuhan dengan tujuan untuk memperoleh suatu hadiah atau keuntungan, maka dia pada hakekatnya tidak mencintai Tuhan tapi mencintai hadiah atau keuntungan itu.19 Tak satupun yang dapat mencintai Tuhan seperti apa yang dimaksud Tuhan sendiri dan tanpa sedikitpun motif yang tersembunyi kecuali sesuatu yang telah diciptakan dari citra-Nya. Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna sedemikian sehingga manusia dapat memverifikasi dan menyadari citra Tuhannya dan mencintai Khaliqnya yang bermuara pada tercelupnya manusia dalam Rahmat yang tak terbatas dan tak pernah habis.
Bagi tradisi intelektual, kegunaan mempelajari makrokosmos adalah untuk memahami kekuatan dan kapabilitas mikrokosmos. Dengan memahami objek, secara simultan kita memahami kapasitas dan potensialitas subjek. Kita tidak dapat mempelajari alam dunia tanpa belajar tentang diri kita sendiri, dan kita tidak dapat mempelajari diri kita sendiri tanpa memahami hikmah yang inheren dalam alam dunia.
Relaitas sosial seringkali dipelajari dengan tujuan yang sama – sebagaimana tujuan dalam memahami jiwa manusia. Sesuatu yang umum bagi filosof Muslim untuk memberikan gambaran cita-cita suatu masyarakat. Akan tetapi mereka tidak tertarik pada mimpi-mimpi yang utopis yang seringkali mengikat perhatian pakar politik modern. Sebaliknya, mereka lebih ingin memahami dan menggambarkan berbagai potensialitas jiwa manusia yang memanifestasi melalui aktivitas sosial dan politik. Mereka tidak ingin memformulasikan suatu program, tetapi sebaliknya mereka mengilustrasikan ketertarikan para filosof bahwa setiap sifat dan kekuatan jiwa, setiap sifat bawaan yang baik dan buruk dapat dikenali dalam keragaman tipe-tipe manusia. Ketika para pencari hikmah mengenali diri mereka sendiri sebagai mikrokosmos suatu masyarakat, maka mereka dapat mengetahui dan menyadari kekuasaan jiwa, raja filosof yang sejati, intelek yang mempunyai tugas untuk mengatur baik jiwa maupun tubuh dengan hikmah dan kasih sayang.
Jika para filosof menganalisa jiwa tumbuhan, binatang dan bahkan malaikat, dan jika mereka menggambarkan seluruh kemungkinan kemenjadian manusia dalam terminologi etika dan sosial, kegunaannya adalah untuk mengintegrasikan segala sesuatu di alam semesta ke dalam keagungan visi hierarkis tauhid. Adalah swabukti bagi filosof bahwa intelek dalam diri kita — cahaya jiwa yang cemerlang dan terpahami — adalah dimensi substansi manusia yang paling tinggi dan komperehensif. Hanya intelek yang dapat melihat, memahami, memverifikasi dan menyadari. Hanya intelek yang memberi kehidupan, kesadaran, dan pemahaman yang tidak hanya bagi jiwa kita sendiri tapi kepada seluruh jiwa. Hanya intelek yang mampu untuk memahami dan menyadari kegunaan kehidupan manusia dan seluruh kehidupan yang lain.
Kemudian apa yang dimaksud dengan intelek yang merupakan asal dan tujuan pembelajaran intelektual? Adalah tidak mungkin untuk mendefinisikannya, sebab inteleklah yang memberikan seluruh kesadaran dan pemahaman seluruh definisi. Ia tidak dapat dibatasi dan dikurung oleh pancaran atau cahayanya sendiri. Akan tetapi, kita dapat menggambarkannya dalam pengertian peranannya dalam kosmogenesis, dengan jalan mana seluruh benda-benda diciptakan melaluinya. Dan kita dapat juga menggambarkannya dalam pengertian kembalinya manusia kepada Tuhan, yang dapat dialami dalam kesempurnaannya hanya dengan mengaktualkan intelek, yang merupakan swacitra Tuhan. Izinkan saya untuk membahas kosmogenesis terlebih dahulu.
Secara khusus tradisi hikmah memulai dengan diskusi kelahiran kosmos dalam pengertian kreasi Tuhan atau emanasi makhluk pertama yang diberi berbagai nama dalam teks seperti intelek, spirit, firman, pena, cahaya dan realitas Muhammad. Benda-benda hadir dari Prinsip Pertama dalam suatu urutan yang pasti dan terpahami, dan berdasarkan hierarki yang diketahui dan tertentu (diketahui bermakna kepada Tuhan dan intelek, tetapi tidak penting bagi kita). Sudah jelas bagi pemikir-pemikir Muslim bahwa Tuhan yang Esa mencipta dengan cerdas, dan memanifestasikan realitas-Nya yang pertama, kontingensi yang paling dekat dengan Ketunggalan-Nya, tingkat aktualitas tercipta yang paling dekat kepada kesederhanaan yang sempurna dan absolut, adalah kecerdasan dan kesadaran yang murni. Di dalam kesadaran ini diciptakan alam semesta dan jiwa manusia.
Kecerdasan yang hidup itu adalah instrumen yang digunakan Tuhan untuk merencanakan, mengatur, menyusun, dan menetapkan seluruh ciptaan, dan ia terbentang pada akar setiap subjek dan objek. Ia adalah suatu realitas tunggal yang merupakan prinsip alam semesta dan jiwa manusia yang swatahu (self-aware) dan swasadar (self-conscious). Di antara seluruh ciptaan, hanya manusia yang memanifeskan cahayanya yang murni dan sempurna, suatu cahaya yang dalam bahasa al-Quran disebut “Ruh yang ditiupkan Tuhan ke dalam diri Adam.” “Kejatuhan” Adam tidak bermakna apa pun kecuali peredupan cahaya ini.
Ketika melihat pada intelek dari pandangan manusia yang kembali kepada Tuhan, kita melihat bahwa tujuan eksistensi manusia adalah untuk mengingat Tuhan dan untuk mengumpulkan kembali citra Ketuhanan kita dengan membangunkan intelek dari dalam. Tugas para pencari hikmah adalah untuk menemukan kembali di dalam dirinya sendiri kesadaran yang tercerahkan yang mengisi alam semesta. Penemuan ini adalah ketercapaian dan realisasi kemungkinan manusia. Meskipun intelek sudah redup di dalam setiap jiwa manusia atau yang lainnya, hanya di dalam manusia ia merupakan benih yang dapat ditaburkan dan dibiakkan, dipelihara, dikuatkan dan diaktualkan secara sempurna.
Meskipun jiwa manusia adalah suatu subjek yang tahu dan sadar yang mempunyai kapasitas untuk memahami objeknya sebagai alam semesta secara keseluruhan dan segala sesuatu di dalamnya, secara khusus ia buta terhadap kemungkinan-kemungkinannya sendiri, dan ia memunculkan warna jiwa yang tidak sepenuhnya manusia. Jiwa perlu belajar bagaimana menjadi manusia, dan menjadi manusia bukanlah sesuatu yang mudah bagi jiwa. Sebagian dari kita harus diingatkan oleh nabi tentang apa yang ada di dalam diri manusia, dan bahkan dengan mematangkan “intelektual”, dengan seluruh berkah mereka, untuk melintasi suatu jalan yang terjal dan penuh dengan kerikil tajam di hadapan mereka jika mereka ingin mencapai tujuan itu.
Tradisi intelektual memegang salah satu cara yang paling baik untuk memulai mempelajari bagaimana menjadi manusia yaitu dengan membedakan kualitas-kualitas jiwa manusia dari kualitas jiwa yang lainnya. Di sini kita kembali kepada diskusi tentang tanaman, binatang yang merepresentasikan eksistensi kejiwaan yang mempunyai kemungkinan serba kurang dan terbatas. Seluruh instruksi-instruksi moral untuk mengatasi insting binatang yang muncul dari pemahaman binatang yang tidak dapat memanifestasikan kemungkinan-kemungkinan intelektual dan ontologis secara sempurna. Hal ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan kualitas-kualitas binatang, karena mereka selalu memainkan peranan penting pada jiwa manusia. Persoalan tersebut lebih dilihat sebagai suatu prioritas. Manusia perlu meletakkan benda-benda pada tempatnya yang tepat. Mereka harus memerintah dunia dan tujuan mereka sendiri dengan cara yang cerdas dan hal ini berarti mereka harus memahami segala sesuatu dalam terminologi hukum kebenaran kosmos, dan yang pertama dari hal itu adalah tauhid.
Selanjutnya jiwa adalah kutub subjektif manifestasi realitas, dan pasangannya yaitu alam semesta adalah kutub objektif. Jiwa dalam bentuk manusia mempunyai kapasitas yang unik untuk mengetahui benda-benda. Akan tetapi, pengetahuan jiwa terhadap seluruh benda-benda hanyalah potensial. Hal itu bukanlah pengetahuan yang aktual. Aktualitas adalah suatu kualitas intelek. Setiap tindakan mengetahui mengaktualisasikan potensi jiwa untuk mengetahui dan membawanya dekat kepada cahaya yang cemerlang dan terpahami pada intinya. Akan tetapi apa yang sesungguhnya menjadi pembatas potensi jiwa? Apa yang ia dapat ketahui? Apa yang sebaiknya ia upayakan untuk diketahui? Tradisi intelektual menjawab bahwa tidak ada batasan terhadap potensi jiwa, sebab tidak ada yang eksis yang menyebabkan jiwa tidak dapat mengetahui. Tujuan belajar adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang mempunyai kemungkinan untuk diketahui. Akan tetapi, benda-benda yang dapat diketahui perlu diprioritaskan. Jika kita tidak melakukan penelitian untuk memahami dengan cara yang benar dan urutan-urutan yang tepat, tujuan tetap tidak akan dapat tercapai selamanya.
Sepanjang jiwa tetap berada pada kondisi penelitian terhadap hikmah dan belum mengaktualisasi potensinya secara sempurna, ia tetap menjadi suatu jiwa – yang merupakan suatu swasadar dengan kemungkinan perolehan kesadaran yang tinggi. Hanya ketika ia mencapai aktualitas seluruh pengetahuan di dalam pusat yang paling dalam dari keberadaannya, maka ia dapat disebut “intelek” dalam pengertiannya yang tepat. Pada titik ini ia mengetahui dirinya sendiri sebagaimana ia menjadi. Ia menemukan kembali kebenaran alaminya, dan ia kembali pada tempatnya yang tepat dalam hierarki kosmik.
Para filosof Muslim dan orang-orang yang bijak seringkali merujuk aktualisasi intelek dengan terminologi al-Quran yaitu keselamatan (najat) dan kebahagiaan (sa´adah). Mereka akan setuju dengan Tu Weiming yang menulis, “Keselamatan bermakna realisasi realitas antropokosmik yang sempurna yang inheren dalam sifat kemanusiaan kita.”21 Bagi mereka, realitas antropokosmik ini adalah intelek yang memberi kelahiran kepada makrokosmos dan mikrokosmos dan yang inheren dalam sifat kemanusiaan, yaitu suatu sifat yang dibuat dalam citra Tuhan dan identik dengan cahaya-Nya yang cemerlang dan terpahami.
Jika para filosof Muslim melihat pencarian hikmah sebagai penelitian untuk mengetahui seluruh benda-benda, dapatkah kita menyimpulkan bahwa mereka mengikuti Aristoteles yang mengatakan hal yang serupa dengan mereka pada awal metafisikanya? Saya kira tidak demikian. Mereka akan mengatakan bahwa mereka mencoba untuk menyempurnakan potensi kemanusiaan, tetapi adalah tepat untuk bertanya mengapa mereka menghormati Aristoteles dengan menyebutnya Guru Pertama (al-mu´allim al-awwal). Mereka mengingatkan kita bahwa al-Quran mendiskusikan potensi manusia dengan terminologi yang agak eksplisit. Setelah itu, ia menceritakan kepada kita bahwa Tuhan mengajari Adam seluruh nama-nama (QS al-Baqarah [2]:31), tidak hanya sebagian. Mereka juga mungkin menunjukkan bahwa pencarian ini untuk memperoleh keterlimpahan keadaan mengetahui segala sesuatu (omniscience) yang diakui secara implisit — jika bukan eksplisit — tidak hanya oleh kata-kata dalam tradisi hikmah, tetapi juga oleh seluruh kinerja ilmu modern. Tetapi dari perspektif mereka omniscience hanya dapat ditemukan dalam upaya yang keras untuk mengetahui segala sesuatu (omniscient), dan hanya benda yang diciptakan yang omniscient dalam setiap pengertian yang real yang merupakan aktualisai sempurna intelek, pancaran Kalam Tuhan. Dengan kata lain omniscience tidak akan pernah dapat ditemukan dalam kompilasi data, kumpulan fakta dan pintalan teori-teori. Ia bukan hanya suatu realitas “objektif”, tetapi juga suatu pengalaman “subjektif” – tidak ada distingsi yang dapat digambarkan antara subjek dan objek dalam keberadaan yang hakiki dari omniscience.
Pencarian intelektual islami tidak terbedakan dari apa yang dilakukan oleh keilmuan modern dan tujuan-tujuan kesarjanaan lebih jelas dari perbedaan interpretasi tentang pencarian bagi omniscience. Bila ilmuwan modern berupaya keras mencari segala sesuatu, intelektual Muslim melakukannya dengan mengamati akar, prinsip dan nomena dan dengan berupaya keras untuk penyintesisan dan penyatuan subjek pengetahuan. Sebaliknya ilmuwan modern mengamati cabang, aplikasi, dan fenomena dan berupaya keras untuk menganalisis objek-objek dan membiakkan data.
Intelektual tradisional melakukan pencarian untuk omniscience sebagai seorang individu yang mengetahui bahwa dia harus menyelesaikan tugas dalam dirinya sendiri, dan bahwa dia hanya dapat melakukan yang demikian itu dengan mencapai kesempurnaan kemanusiaannya, dengan segala sesuatu yang dibutuhkan secara moral dan secara etis. Para ilmuwan modern yang melakukan pencarian fakta-fakta dan informasi sebagai suatu perlakuan yang kolektif, mengetahui bahwa dia adalah suatu lokomotif yang penting dalam gugusan aparatus yang sangat besar. Dia melihat omniscience sebagai sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan Science dengan S (baca S kapital, penerj.). Hanya Science yang mempunyai metodologi yang istimewa, unik dengan instrumen yang sangat canggih. Dia jarang memberi suatu pemikiran terhadap kemungkinan bahwa setiap pengetahuan membuat kebutuhan etik terhadap orang yang mengetahui. Jika dia betul-betul memberi suatu pemikiran tentang hal itu, dia melakukan yang demikian itu bukan sebagai ilmuwan, tetapi sebagai seorang moralis atau seorang filosof atau sebagai seorang rohaniwan. Tidak ada ruang dalam Science bagi etika.
Para pencari hikmah bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi kecerdasaannya secara sempurna untuk memahami segala sesuatu yang penting bagi akhir kehidupan manusia, akhir kehidupan ini didefinisikan dalam pengertian metafika, kosmologi, psikologi dan etika yang mengambil Realitas Paripurna sebagai ukuran manusia. Para pencari fakta-fakta modern bertujuan untuk mengakumulasi informasi dan melengkapi bahkan pada teori-teori yang canggih untuk mencapai apa yang mereka sebut “kemajuan”. Dengan kata lain, mereka ingin mencapai suatu transformasi ras manusia yang didasarkan pada kemutlakan semu keilmuan jika bukan ideologi politik.
Pencarian hikmah adalah suatu yang kualitatif, sebab ia ditujukan pada aktualisasi seluruh kualitas keberadaan secara utuh dalam citra Tuhan dan dinamai dengan nama-nama Tuhan. Pencari pengetahuan modern dan kecakapan teoritis adalah sesuatu yang kuantitatif, sebab ia ditujukan untuk memahami dan mengontrol setiap perkembangbiakan keserbaragaman benda-benda.
Semakin tradisional intelektual mencari omniscience, dia semakin mampu menemukan kesatuan jiwanya sendiri dan hubungan organismiknya sendiri dengan dunia. Semakin modern seorang ilmuwan mencari data, dia semakin mendekati dispersi dan inkoherensi, meskipun klaimnya menyebutkan bahwa ketercapaian teori-teori yang ada akan memungkinkan pada suatu hari nanti untuk menerangkan segala sesuatu.
Pencarian secara tradisional terhadap hikmah menghasilkan integrasi, sintesis visi antroposentris yang menjadi sesuatu yang global. Pencarian secara modern terhadap informasi dan kontrol menghasilkan gundukan fakta-fakta yang menjamur dan perkembangbiakan pengajaran yang lebih terspesialisasi dan sempit. Hasil pencarian modern adalah partikulasi, pendivisian, pempetak-petakan, pemisahan dan inkoherensi, inkompreshensi mutual dan kekacaun. Tak seorang pun yang tahu kebenaran pernyataan ini lebih baik dari profesor-profesor yang ada di universitas yang seringkali terspesialisasi dengan sangat sempit yang tidak dapat menerangkan penelitiannya kepada teman sejawatnya sendiri di dalam satu departemen – semakin para bila diperhadapkan dengan teman sejawatnya di lain departemen.
Izinkan saya merangkum kesimpulan saya sebagai berikut. Bagi tradisi intelektual Islam, penelitian tentang alam semesta merupakan eksperimen yang holistik dan bercabang dua. Pada satu sisi tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menerangkan dunia penampakan. Sisi yang lainnya tujuannya adalah memahami realitas terdalam baik penampakan-penampakan atau orang yang mengetahui penampakan-penampakan itu. Guru utama disiplin ini selalu memahami bahwa tidak mungkin memahami objek eksternal tanpa memahami subjek yang memahami. Hal ini bermakna bahwa metafisika, kosmologi dan psikologi merupakan bagian essensial dari pencarian intelektual. Tujuannya adalah untuk melihat penampakan-penampakan yang membumi, prinsip-prinsip yang terpahami dan kecerdasan diri dalam sesuatu yang terintegrasi dan visi yang simultan. Telah dipahami bahwa kecerdasan bukan hanya memahami dan meliputi realitas karakter benda-benda, tetapi juga yang memberi kelahiran benda-benda pada tempatnya yang pertama. Segala sesuatu yang dapat diketahui adalah sesuatu yang laten dalam akal, sebab seluruh benda-benda muncul dari akal dalam proses kosmogenik.
Visi antroposentrik menyediakan tidak adanya dikotomi realitas antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Struktur dan tujuan kinerja intelektual mencegah hilangnya persepsi jalinan ontologis yang mengikat subjek dan objek. Hal itu terjadi karena melupakan tauhid dan jatuh ke dalam kekacauan dispersi dan egosentrisitas. Mengabaikan realitas orang yang mengetahui menyebabkan penggunaan pengetahuan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang sesat, dan mengabaikan realitas yang diketahui membalikkan dunia menjadi benda-benda dan objek-objek yang dapat dimanipulasi oleh tujuan-tujuan yang terpisah jauh dari visi karakter kemanusiaan yang benar.
Kemungkinan-kemungkinan pemahaman manusia menentukan kemungkinan-kemungkinan manusia dalam proses menjadi. Mengetahui adalah menjadi. Mengabaikan realitas baik objek maupun subjek sama dengan jatuh ke dalam kebodohan, kesalahan dan tahayul. Memiskinkan dan merusak alam semesta adalah cermin suatu pemiskinan dan perusakan jiwa. Pemiskinan dan perusakan jiwa lebih berarti pembodohan akal daripada kematian Tuhan karena hal itu tidak mungkin. Kerusakan ekologis adalah konsekuensi yang tak terelakkan dari kerusakan psikis dan spiritual. Dunia dan diri adalah dua realtitas yang tak terpisahkan, tetapi merupakan dua sisi koin yang sama, suatu koin yang diciptakan di dalam citra Tuhan.[]
Diterjemahkan oleh Khusnul Yaqin dari The Anthropocosmic Vision in Islamic Thought by Willian C. Chittick dalam Konferensi Internasional, “God, Life and Cosmos, Theistic Perspective”, Islamabad, Pakistan, 6-9 November, 2000.
Daftar Pustaka
1. Sebaliknya Tu memakai kata “antropokosmik” dari Mircea Eliade. Tu, Centrality and Commonality: An Eassay on Confucian Religiousness (Albany: SUNY Press, 1989), p. 126. Makalah ini sebagiannya bagian dari Dialog Konfusu-Islam yang sedang berjalan yang diawali lima tahun yang lalu oleh Tu dan Seyyed Hossein Nasr, di mana saya menjadi partisipan regulernya. Makalah ini juga merupakan hasil dari in-house dialogue dengan istri saya, Sachiko Murata, yang telah berlangsung lebih dari lima tahun yang lalu. Saya tidak bermaksud menunjukkan dengan catatan ini bahwa saya sekarang menafsirkan tradisi Islam dengan kategorisasi Cina. Saya kutip Tu Weiming untuk mengakui pengaruh tertentu pada konseptualisasi saya tentang benda-benda dan untuk menunjukkan tidak ada sesuatu yang ganjil dalam pandangan dunia Islam. Satu hal yang dapat menjadi alasan adalah visi antropokosmik yang saya diskusikan di sini merupakan suatu perspektif dalam versi Islam yang bersifat normatif bagi ras manusia. Jika terdapat suatu keganjilan, hal itu karena ilmu alam dunia Barat – berikut semangat kebangkitannya – dan disiplin-disiplin lain pada akademi modern. Pertanyaan yang sebenarnya bukan pada mengapa Konfusisme dan Islam mempunyai common vision yang sama, tetapi mengapa Barat telah terpisah dari pola perenial. Yang janggal adalah Barat dan cara berfikirnya, bukan visi holistik peradaban dan kebudayaan pra-modern.
2. Ibid. h. 10.
3. Sarjana Barat jarang melihat ke Asia Timur untuk membantu penginterpretasian cara berfikir dalam Islam. Satu alasan untuk ini adalah kita sedang berbicara tentang sarjana “Barat” dengan seluruh bias prasangka dan interpretasinya yang mengemuka. Di samping itu, sarjana Barat telah memberikan perhatiannya terutama pada situasi cara berfikir Islam dalam konteks sejarahnya, bukan pada pemahaman tentang apa yang telah dicoba diteorikan oleh pemikir Muslim yang mempunyai banyak sekali kesamaan dengan apa yang ada dalam tradisi Yahudi-Kristen dan Helenistik Barat. Saya tidak sedang menolak nilai penting beberapa penelitian dunia Barat, tetapi pendekatan penelitian-penelitian ini mempunyai makna bahwa interpreter intelektualitas Islam secara khusus tidak sensitif terhadap dimensi-dimensi tertentu pemikiran Islam yang tampak mempunyai resonansi yang dalam dengan tradisi Asia Timur. Sebagian besar sarjana Islam sekarang ini membebek kepada model Barat atau mengambil suatu sikap apologetik dan reaktif vis-à-vis sarjana Barat, sedemikian sehingga mereka juga tidak memperhatikan Asia Timur. Namun demikian, tidak ada alasan untuk mengandaikan bahwa pemikiran Islam pada setiap esensinya tidak sejalan dengan tradisi Asia Timur, sebagaimana telah diilustrasikan oleh Sachiko Murata di dalam penelitiannya, The Tao of Islam (Albany: SUNY Press, 1992). Penelitiannya yang lebih baru menunjukkan bahwa Sarjana Muslim di Cina merasa nyaman dalam suasana pandangan dunia Neo-Konfusu yang sangat antropokosmik, dan mereka menggunakan pengertian teknisnya untuk mengekspresikan visi realitas yang Islamo-Konfusu. Lihat Murata, Chinese Glems of Sufi Light (Albany: SUNY Press, 2000).
4. Ambil contoh surat dalam QS Ali Imran [3]:83, “Maka apakah mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal kepada-Nyalah menyerahkan diri (Islam) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa.” Untuk makna-makna yang berbeda tentang kata Islam dalam al-Quran dan tradisi Islam, lihat Sachiko Murata dan William C. Chittick, The Vision of Islam (New York: Paragon, 1994), h. 3-7.
5. Tentu saja, kecuali dalam pengertian bahwa sebelumnya terdapat keharusan menjadi realitas yang bergantung kepada kebenaran untuk mencari ekspresi di dalam alam semesta. Pemikir-pemikir Muslim seringkali berkata bahwa Keesaan Tuhan (wahdah atau ahadiyyah) hanya tertuju kepada Tuhan, yang mentransendensi seluruh kemungkinan dan seluruh sifat-sifat yang tercipta, sedangkan tauhid adalah respon manusia terhadap Keesaan itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa respon manusia itu hanya mungkin karena realitas Tuhan sendiri mendeklarasikan Keesaan-Nya sendiri – sebagaimana yang disebutkan QS Ali Imran [3]:18, “Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia” Inilah mengapa kadang-kadang disebutkan bahwa tak seorang pun yang mempunyai suara tauhid kecuali Tuhan sendiri, dan setiap pernyataan manusia tentang Keesaan Tuhan hanya dapat menjadi refleksi yang brilian yang hanya dimungkinkan oleh manusia yang menjadi citra Tuhan.
6. Surat dalam al-Quran yang spesifik yang muncul dalam benak saya yaitu QS al-Anbiya [21]:25, “Dan Kami tidak pernah mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan. Bahwasanya tidak ada Tuhan malainkan Aku, maka sembahlah Aku”. Kalau seorang mengklaim bahwa pernyataan tauhid itu pada dirinya sendiri merupakan bagian dari sejarah, kami perlu mengingatkan bahwa formulasi linguistik bukanlah titik persoalannya, tetapi titik persoalannya lebih terletak pada realitas tunggal yang unik yang menjadi sebab keberadaan alam semesta. Catatan juga bahwa al-Quran mengatakan bahwa Tuhan mengutus setiap rasul dengan bahasa kaumnya (QS Ibrahim [14]:4), oleh karena itu diakui bahwa Tuhan berbicara dengan berbagai bahasa, untuk “Setiap kaum mempunyai seorang rasul” (QS. 10:47). Dengan cara pandang seperti ini terhadap benda-benda, apa yang berbeda dalam setiap wahyu bukanlah tauhid, tetapi lebih pada cara pengajaran tertentu dan praktik-praktik yang diperlukan oleh konteks sejarah masyarakat yang menerima pesan yang telah diwahyukan itu. Tentu saja, hal itu dapat ditolak bahwa Keesaan realitas pada dirinya sendiri merupakan bagian dari sejarah, sebab ia ditemukan dalam benak manusia. Orang-orang yang berpegangan pada pandangan seperti ini masih harus memberikan alasannya, dan masih perlu alasan metafisik seperti: pada basis apa kita mendeklarasikan sejarah, bahasa, politik, gender, atom, energi, otak, atau apa saja yang bersifat fundamental?
7. Inilah yang menjadi sebab mengapa beberapa pemikir Muslim tertentu (seperti Ibn al-Árabi, sebagaimana dikutip dalam Chittick, The Sufi Path of Knowledge [Albany: SUNY Press, 1989], h. 296) dapat mengatasi bahkan “kealpaan” Adam (nisyan) yang menyebabkan kejatuhannya, yang berkaitan dengan citra Ketuhanan yang menentukan karakteristik ras manusia. Pengetahuan riwayat yang mendukung gagasan ini adalah ayat al-Quran, “Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan meraka” (QS 9:67). Jika Tuhan “lupa” maka “kelupaan” adalah suatu sifat Allah. Adam “telah lupa” sebab dia dibuat dari citra Tuhan. Hal ini merupakan cara yang agak berani dengan menguraikan sesuatu yang dapat diterangkan dengan mengatakan bahwa manusia memanifestasikan setiap sifat yang mengkonfigurasi citra Tuhannya. Tuhan selain Maha Pemurah juga Maha Pemarah. Karena manusia mengalami realitas kemarahan-Nya, mereka membuat jarak dengan Tuhan, Sumber pengetahuan dan hikmah, dalam keadaan seperti ini pemahamannya menjadi kabur. Karena mereka mengalami realitas kemurahan-Nya, mereka menjadi dekat dengan-Nya dan berada di dalam Kesadaran, Ketercerahan dan keagungan-Nya.
8. Beberapa diskusi yang terarah pada hubungan antara dua jenis pengetahuan mungkin mengingatkan kita tentang debat yang terjadi di antara teoritikus yang terdidik dari golongan penghafal atau budaya harfiah (pengetahuan riwayat) dan golongan pemikir kritis atau kreatif (pengetahuan intelektual). Seperti halnya peradaban tradisional yang lainnya, Islam memberi penekanan bahwa pengajaran riwayat merupakan dasar bagi seluruh pemahaman realitas. Hal ini menjelaskan mengapa proses belajar dimulai pada saat umur yang masih muda dengan menghafal al-Quran.
9. Saya sedang memfokuskan pada tauhid, prinsip pertama keyakinan Islam. Harus dicatat bahwa para filosof juga menginvestigasi dua prinsip-prinsip keyakinan Islam yang lainnya —“kenabian” (nubuwwah) dan “kembali” kepada Tuhan, atau eskatologi (ma´ad)— sebagai bagian pembahasan intelektual dari pada riwayat. Mereka tidak secara khusus tertarik pada kejadian-kejadian sejarah di sekitar Muhammad dan nabi-nabi yang lain, atau pada detail-detail kitab suci yang diwahyukan. Bukankah pada periode awal mereka mempertahankan penggambaran harfiah al-Quran tentang kehidupan akhirat sebagai sesuatu yang tidak lebih dari keperluan retorik. Akan tetapi mereka tertarik pada “kenabian” sebagai bentuk tertinggi penyempurnaan manusia, dan mereka secara khusus mengarahkan pada imortalitas jiwa, suatu imortalitas yang dicapai melalui penyempurnaan intelektual. Karena mereka mendiskusikan tiga prinsip keyakinan dengan rujukan yang eksplisit pada pengajaran riwayat dalam jumlah yang sedikit dan lebih banyak menyebutkan tokoh-tokohYunani, beberapa ahli sejarah yang telah menemukannya tidak segan-segan mengesampingkan tulisan-tulisan mereka yang teliti dan Islami itu. Ketika para filosof seringkali dikritik oleh sarjana Muslim yang lain terhadap posisi yang mereka ambil dalam prinsip-prinsip keyakinan, hal itu karena interpretasi mereka tidak sebangun dengan bacaan-bacaan teologis dan dogmatis. Dengan mengansumsikan bahwa sifat polemik teologis adalah benar, kritisisme seringkali dituduh sebagai sesuatu yang kafir. Akan tetapi, dalam pandangan yang lebih luas, terdapat kesepakatan antara filsafat dan teologi terutama jika kita membandingkan posisi mereka dengan kaum agamawan yang terasuki cara berfikir yang sangat modern.
10. Confucian Thought: Selfhood as Creative Transformation (Albany: SUNY Press, 1985), h. 137.
11. Centrality and Commonality, h. 102.
12. Tentu saja saya tidak menyimpulkan bahwa swabukti itu ada pada setiap orang, tetapi dibandingkan dengan kebenaran matematika, swabukti lebih tampak ada pada setiap orang. Apa yang ingin saya sebutkan adalah lebih pada posisi tradisi intelektual tentang tauhid yang ketika ia dipahami, maka ia tidak bisa ditolak. Ketika seseorang memahami tauhid, maka orang itu tahu bahwa ia bersemayam dalam jiwanya. Hal inilah makna sebenarnya dari “zikir”.
13. Saya tidak sedang menolak bahwa terdapat penurunan. Dengan sederhana saya mengatakan bahwa dengan membuat kriteria pengukuran “kemajuan ilmiah” atau kekurangannya, kita sedang menerima prasangka ideologi saintisisme. Mengapa keganjilan sejarah dianggap sebagai kriteria universal dengan mana seluruh peradaban diukur? Jika kita melihat kriteria Islam (seperti pengikutan terhadap tauhid, al-Quran dan Sunnah) terdapat penurunan yang sangat serius dalam peradaban Islam, khususnya dalam tradisi intelektual, tetapi hal itu terjadi sangat lebih lambat dibandingkan dengan tradisi yang dipertahankan sejarah.
14. Confucian Thought, h. 46-47.
15. Saya tidak bermaksud menyimpulkan bahwa intelektual Muslim tidak menerima Muhammad sebagai nabi atau al-Quran sebagai buku petunjuk. Para filosof melihat bahwa tidak ada alasan untuk mempertanyakan dasar-dasar dogma dari pengetahuan riwayat, sebab mereka menganggap pengajaran yang bersifat religius akan memberikan kemanfaatan bagi setiap orang, dan secara pasti akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Hikmah – pengajaran intelektual yang sebenarnya – dengan sifat alaminya disediakan bagi mereka yang mempunyai kualitas yang tinggi, orang-orang ini jumlahnya sangat sedikit. Posisi yang tidak “demokratis” dan “elitis” ini didasarkan pada kenyataan bahwa ideologi politik tidak mempengaruhi pandangannnya terhadap realitas sosial. Mereka menganggap manusia sebagaimana mereka (manusia) adanya, bukan sebagaimana yang mereka inginkan untuk menjadi.
16. Adalah penting untuk tidak mencampuradukkan pembahasan tahqiq dengan ijtihad. Dua kata itu digunakan sebagai lawan dari taqlid. Akan tetapi, tahqiq berkaitan dengan ilmu intelektual, dan ia bermakna untuk menemukan kebenaran dan realitas seluruh benda-benda dengan dirinya dan di dalam dirinya sendiri. Ijtihad digunakan dalam merujuk ilmu riwayat, terutama fiqh atau jurisprudensi. Ijtihad adalah untuk memperoleh suatu penguasaan syariah yang tidak mengikuti opini para ahli hukum sebelumnya (taqlid). Untuk beberapa abad lamanya, banyak pakar hukum menganggap bahwa “pintu gerbang ijtihad” telah ditutup. Akan tetapi “pintu gerbang” tahqiq tidak pernah ditutup, sebab adalah kewajiban bagi setiap Muslim untuk memahami Tuhan dan hal-hal lain tentang keyakinannya bagi dirinya sendiri. “Keyakinan kepada Tuhan” dengan cara meniru adalah bukan keyakinan itu sendiri.
17. Kebenaran saintisme – kepercayaan yang kokoh kepada reliabilitas pengetahuan ilmiah yang bersifat empiris – membenam dalam budaya modern, sangat sulit bagi kaum modernis untuk mengingat bahwa seluruh bangunan besar sain dibangun dengan dasar pengajaran riwayat. Meskipun seluruh pembicaraan tenatang “verifikasi empiris” terdapat dalam penemuan-penemuan ilmiah, verifikasi ini tidak dimungkinkan kecuali bagi sejumlah kecil pakar, karena sebagian besar ras manusia tidak memperoleh pelatihan yang diperlukan. Sebagai akibatnya, setiap orang tidak harus menerima verifikasi empiris yang didasarkan pada keyakinannya (taqlid). Selanjutnya, sejumlah kecil verifikasi yang dapat dikerjakan oleh setiap individu ilmuwan dengan mengikuti “metode ilmiah” yang diakui bahwa ia didasarkan pada “rasionalitas instrumental”. Beberapa percobaan menunjukkan bahwa kondisi dan tujuan tertentu telah dikonstruksi secara deterministik, sehingga y selalu akan mengikuti x. Tidak ada keraguan terhadap penemuan kebenaran akhir benda-benda, sebab rata-rata adalah sesuatu yang tidak memadai, dan tak seorang ilmuwan pun – qua ilmuwan – dapat mengklaim bahwa rata-rata adalah sesuatu yang memadai. Jika dia sungguh mengklaim bahwa rata-rata adalah sesuatu yang memadai, maka dia melakukan sesuatu sebagaimana seorang penganut kepercayaan dalam saintisme atau sebagai seorang filosof, bukan seorang ilmuwan. Dalam terminologi saintisme — bukan sains —orang-orang mendeklarasikan bahwa tidak ada sesuatu yang disebut “jiwa” atau “realitas absolut”. Baik sain dan saintisme tidak akan memimpikan pengakuan apa yang telah muncul sebagai suatu fakta yang sederhana kepada tradisi hikmah dalam seluruh peradaban pre-dominan: waktu, ruang, sejarah, kejiwaan, energi, pemikiran, malaikat, dan bahkan tuhan-tuhan (Bukan Tuhan dalam pengertian yang sebenarnya) yang mentransendensi dalam kemungkinan-kemunkinan di dalam diri manusia.
18. Hal ini tidak untuk mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang disebut sebagai “kejahatan”. Pembahasan tentang pendedahan kebenaran “kejahatan” adalah salah satu dimensi tahqiq yang lebih jelimet. Pengenalan kebenaran benda-benda mungkin memerlukan pengakuan bahwa bagian peranannya yang tepat adalah menjadi alasan bagi kejahatan (kejahatan adalah maujud yang tergantung pada wujud kebenaran, penerj.) dan respon manusia yang tepat adalah menghindarinya. Kebutuhan yang mendesak untuk menghindari kejahatan mengubah kita untuk menjadi sesuatu yang mempunyai peranan penting dalam kosmos.
19. Bandingkan dengan penggambaran Tu Weiming tentang spiritualitas yang dilihat dalam visi Konfusu: “Batu, tumbuhan, binatang, manusia, dan malaikat yang merepresentasikan tingkat spritualitas yang berbeda yang didasarkan pada berbagai komposisi ch´i” (Confucian Thought, h. 44). Dalam versi yang khas Islam, ch´i atau kekuatan yang tak tampak yang menghidupkan batu disebut “alam” (tabi´a). Hanya pada tingkat tanaman yang merupakan suatu modalitas ch´i yang kedua, disebut “jiwa”, ditambahkan ke yang pertama. Bebatuan tidak dimaksudkan hanya sebagai materi. Dalam hilomorfisme yang diadopsi oleh tradisi intelektual, peranan materi (maddah) sangat konseptual, sebab tidak ada materi per se. Secara sederhana “materi” adalah nama yang diberikan kepada sesuatu yang tercerap dari hasil observasi bagi forma (tsurah) yang menampak. Forma pada dirinya sendiri adalah sesuatu realitas yang terpahami dan bersifat spiritual yang turun ke dalam domain kenampakan dari spirit atau intelek dan akhirnya dari Tuhan yang dalam bahasa al-Quran, disebut “Pemberi forma” (al-musawir). Karena seluruh benda-benda adalah “forma-forma”, tidak ada yang ada di alam ini yang sungguh tidak memanifestasikan keadaan kehidupan intelegen dan sesuatu yang terpahami.
20. Kepada orang yang mengetahui tradisi Islam, hal ini akan terdengar sebagai ide “sufistik” daripada posisi filosofis. Akan tetapi perlu dicatat apa yang dikatakan Ibn Sina: “Orang yang mengetahui (`arif) menginginkan Realitas, Yang pertama, hanya untuk Keinginan-Nya, bukan untuk keinginan yang lainnya. Dia tidak memilih apapun selain untuk mencapai pengetahuan yang benar tentang-Nya. Ibadahnya diarahkan hanya kepada-Nya, karena Dia yang layak untuk disembah dan karena menyembah adalah suatu hubungan yang agung dengan-Nya. Pada saat yang sama, orang yang mengetahui tidak punya keinginan dan tidak punya rasa takut. Jika dia mengingkan hal-hal lain selain Tuhan, objek keinginan atau ketakutannya adalah motivasinya, dan motivasi ini menjadi tujuannya. Selanjutnya Yang Mahanyata bukanlah tujuannya tetapi lebih kepada keinginan terhadap yang lainnya — sesuatu yang tidak nyata — yang akan menjadi tujuan dan objek.” Al-Isyarat wa al-Tanbihat, diedit oleh S. Dunya (Cairo, 1947), vol. 3, h. 227.
21. Tradisi filsafat seringkali menyebut jiwa manusia sebagai suatu “intelek yang potensial” (´aql bi al-quwwah) atau suatu “intelek yang mentubuh” (`aql hayulani), yang dinyatakan bahwa ia mempunyai kapasitas untuk mengetahui segala sesuatu. Jiwa yang bergerak ke atas melalui berbagai maqam aktualisasi kesadarannya dan yang memperoleh kesempurnaannya sendiri yang inheren dalam dirinya selanjutnya disebut “intelek yang telah teraktualisasi” (´aql bi al-fi´l).
22. Tu, Confucian Thought, h. 64.
source : alhassanain