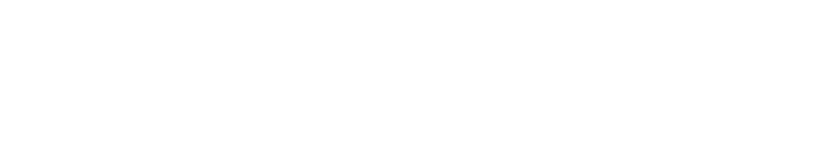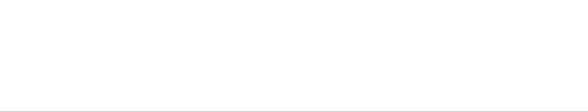Sebagaimana kebanyakan ending cerita yang berakhir kebahagiaan, begitupun novel ini. Namun kebahagiaan para tokoh yang diceritakan bukan karena telah mendapatkan apa yang diinginkan dan yang telah diimpikan sedemikian lama, namun kebahagiaan yang berlatar keyakinan yang mendalam, bahwa Tuhan tidaklah melulu memberikan apa yang diinginkan, namun memberikan sesuai apa yang dibutuhkan, dan selalu saja lebih baik.
Dari Jendela HauzahPenerbit : MizaniaPengarang : Otong SulaemanHalaman : 460 halISBN : 978-602-8236-64-5
"Kebahagiaan adalah seekor kupu-kupu, kejarlah maka dia akan lari darimu. Duduklah dengan tenang, maka dia akan hinggap di pundakmu." -Anthony de Mello-
-sebuah resensi-
“Ogho-ye Oosep Mohammad?” Tanya pria beserban putih tak berjanggut itu terbata, sambil membaca map berisi data-data tentang diriku. Suaranya yang sengau terdengar geli di telingaku.
“No…no…my name is Asep…Aaaaa…sep,” jawabku.
“Yes…yes…Oosep,” jawabnya.
Demikian sepenggal kutipan kata-kata yang menjadi pembuka fragmen dan alur kisah dalam novel Dari Jendela Hauzah. Begitu membuka halaman pertama, Otong Sulaeman, penulisnya, dengan kata-kata yang dipilihnya, langsung menarik pembaca ke dalam pusaran cerita yang disusunnya. Imajinasi pembaca, serta merta ikut terseret mengikuti langkah-langkah gontai Asep Muhammad, tokoh utama dalam novel ini, dari satu ruangan ke ruangan lainnya, demi diterima sebagai pelajar di sebuah Hauzah di Qom Iran. Kesulitan lidah orang Iran untuk menyebut vokal “a” dan mengubahnya menjadi “o”, urusan birokrasi Iran yang berbelit-belit dan berliku, serta keruwetan aturan administrasinya, diceritakan penulis secara telanjang dan gamblang di bab pertama. Menariknya, ini semacam pemantik rasa penasaran pembaca, untuk tidak berhenti membuka lembaran-lembaran selanjutnya. Keunikan dan keanehan apa lagi yang dipunyai Iran?, negeri yang sedemikian getol dimusuhi dan dibenci Amerika.
Dengan bersetting negara para Mullah, Iran, novel ini berkisah tentang perjalanan hidup Asep Muhammad, seorang pemuda yang baru menyelesaikan kuliah dan telah menyandang gelar sarjana. Namun merasa belum cukup, ia tertarik untuk memperdalam ilmu keagamaannya dan memilih Iran sebagai tempatnya melakukan pengembaraan spiritual. Konflik batin Asep bermula, ketika calon mertuanya, memiliki perencanaan sendiri untuk masa depan Asep. Ia ditawari pekerjaan mapan di sebuah perusahaan tekstil yang termasuk terbesar di Jawa Barat. Namun, secara tegas Asep menolaknya, ia memaparkan perencanaan konsep hidupnya sendiri, ia berencana ke Iran, melanjutkan studi. Pilihan dilematis yang berakibat fatal, calon mertua yang baru saja ingin memberikan restunya naik pitam, dan melarang hubungan apapun terjalin antara Asep dan Alifia, anaknya. Sangat berat bagi Asep untuk meninggalkan Alifia yang telah terlanjur dicintainya, apalagi melupakannya. Namun keinginan yang menggebu untuk juga turut merasakan atmosfer pendidikan di negeri para Mullah, tak bisa terbendung lagi. Ia menetapkan pilihannya untuk tetap ke Iran. Pilihan yang tentu saja bukan tanpa resiko, bayangan wajah kekasih yang dirindukannya, ibarat musik instrumental yang tak pernah berhenti berkonser dalam simfoni kehidupannya, selalu ada dan tergiang riuh di hari-hari perkuliahannya. Dengan bahasa sendu, penulis menggambarkan suasana hati Asep, “Hingga kini, aku merasa ada bagian dari diriku yang tertinggal di Indonesia.” (hal. 8).
Menurut saya, Dari Jendela Hauzah pada dasarnya hendak berbicara soal ketegasan menentukan sikap, keberanian mengambil keputusan. Setiap manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam setiap sekuel kehidupannya. Di hadapan pilihan-pilihan itulah, manusia mesti sigap menentukan sikap. Setiap tokoh dalam novel ini memiliki persoalan sendiri, dipertentangkan dengan pilihan-pilihan yang ruwet dan dilematis. Ada tokoh Daniel Nikbakht seorang Yahudi Iran yang jatuh cinta pada Wafa, seorang muslimah berjilbab berkebangsaan Lebanon dan berasal dari keluarga yang taat beragama. Sejak mengenalnya, Daniel yang sebelumnya sangat acuh terhadap agama dan hal-hal yang bersifat religius menjadi tertarik untuk mendalami Islam lebih jauh. Namun ketika ia telah menetapkan diri untuk berpindah agama dan memeluk Islam untuk kemudian melamar wafa, kejadian serba tiba-tiba merusak segala rencana dan impiannya. Kekerasan dan teror atas nama agama terjadi di depan matanya, kedua orangtuanya tewas dalam peristiwa itu dan ia dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan yang tidak pernah ia mengerti. Sejak itu, agama dan Tuhan menjadi bahan olok-olokan dan hujatannya. Sampai ia terjebak dalam labirin keputus-asaan yang memutuskan dirinya untuk berniat mengakhiri hidupnya.
Masih dalam suasana berkabung karena kematian tiba-tiba kedua orangtuanya, Dewa Darmawangsa diminta untuk memberi kesaksian dalam kasus yang menyeret sahabatnya, Daniel, sebagai tersangka. Dewa terjebak dalam pilihan, antara kesetiakawanan, kepentingan diri sendiri, kelanjutan hubungannya dengan Sinta kekasihnya, atau melupakan saja keberadaan Daniel dan kasus yang menimpanya, terlebih lagi Daniel hanyalah seorang sahabat sepintas yang baru dua kali ditemuinya. Dengan batok kepala yang penuh dengan problema dan kepentingan pribadi, Dewa pada akhirnya membuat keputusan setengah gila, terbang ke Iran untuk menemui sahabatnya yang terjebak dalam keangkeran penjara di negeri para Mullah.
Penulis juga bercerita tentang Muhammad Syafiq yang juga memiliki perjalanan hidup dengan romansa cinta yang satire dan memilukan. Ia sahabat dekat tokoh utama, Asep Muhammad, seorang berkebangsaan Afrika Selatan. Kesalahan fatal yang dilakukannya sewaktu menjalankan ritualitas Haji, harus dibayar mahal dengan ketidak harmonisan keluarganya. Sepulangnya dari Mekah, hari-harinya diisi dengan kepiluan, nestapa dan rasa bersalah yang sangat besar terhadap istrinya. Sampai akhirnya istri yang dicintainya memilih laki-laki lainnya untuk menggantikan posisinya sebagai suami. Istrinya menikah lagi selagi ia berada jauh di Iran. Ia bisa saja menuntut dan memperkarakan kelakuan istrinya sebab ia masih dalam ikatan suami istri. Namun Muhammad Syafiq memilih untuk tidak melakukannya. Ia ikhlas dan ridha atas semua itu, karena dibalik luka percintaan itu ada semangat besar untuk tetap berpegang pada aturan fiqh yang diyakininya. Ia mencintai istri dan keluarganya, lebih dari itu, cintanya lebih terpaut kepada Allah, lebih dari segalanya.
Novel ini lebih dalam mengajarkan, bahwa seseorang harus berani mengambil keputusan sendiri, tanpa campur tangan orang lain lewat ketokohan Mohsen, seorang petugas kepolisian Iran yang mendapat tugas untuk menangani kasus spionase keluarga Daniel. Meskipun tahu, Maryam calon istrinya terkena penyakit berbahaya akibat efek bom kimia semasa perang Irak-Iran, ia tetap nekad menyuntingnya. Alasannya untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak wajar -lewat ketokohan Mohsen- digambarkan penulis dalam kata-kata, “Saya sangat percaya adanya kehidupan yang abadi dan hakiki setelah kehidupan di dunia ini. Penderitaan sangat berat dan bertahun-tahun yang ditanggung Maryam akan dibalas oleh Allah dengan derajat yang mulia di alam akhirat nanti. Saya tidak tahu nasib saya di akhirat nanti. Tapi dengan mempersunting dan mendampingi Maryam sampai detik-detik terakhir kehidupannya, saya berharap ini akan menjadi kebaikan sendiri dalam pandangan Allah.” (hal. 384).
Lewat novelnya, Otong Sulaeman tidak hanya menjadikan sastra sebagai hasil karya yang berkaitan erat dengan masalah kreativitas dan intens dengan wilayah imajiner belaka, namun lebih dari itu, sastra olehnya disulap menjadi semacam diktat kuliah yang informatif dan mencerahkan. Penjabaran pembuktian keberadaan Tuhan yang menggunakan istilah-istilah filsafat yang rumit disajikan secara renyah dan sederhana dalam bentuk dialog-dialog dalam kelas. Lewat materi-materi kuliah yang disampaikan Syaikh Abdullah, Sayid Nabawi dan Syaikh Bahjat seakan-akan kita berada dalam ruang kuliah bersama para talabeh (pelajar) hauzah dan mendapat sajian kuliah aqidah, akhlak dan Irfan. Kita kembali dipertemukan dengan istilah-istilah teologi dalam pembahasan ma’rifatullah yang telah lama disingkirkan dalam pelajaran-pelajaran agama di mayoritas lembaga pendidikan keagamaan kita, semisal wajibul wujud, ‘illiyah, sifat fi’li, sifat dzati, pengenalan Allah lewat fitrah dan argumentasi logis dan sebagainya. Dengan latar pendidikan sastra Arab dan sastra Persia dilengkapi pengalaman intelektualnya menuntut ilmu keagamaan di Hauzah Ilmiyah Qom Iran, membuatnya mampu membedakan antara teks khotbah dan teks sastra secara elegan. Soalan bagaimana mempertemukan antara ketegasan doktrin agama dan imajinasi seni-sastra, diramunya layak tabib professional yang berhasil menyuguhkan bacaan bernas, menyegarkan sekaligus menyembuhkan. Sebuah kerja literer yang tentu saja tak mudah. Kendati dihamparkan dengan plot yang linier, gaya bercerita yang monoton, terkesan dingin dan cenderung membosankan, karya ini tetap menggoda untuk dituntaskan pembacaannya.
Sebagaimana kebanyakan ending cerita yang berakhir kebahagiaan, begitupun novel ini. Namun kebahagiaan para tokoh yang diceritakan bukan karena telah mendapatkan apa yang diinginkan dan yang telah diimpikan sedemikian lama, namun kebahagiaan yang berlatar keyakinan yang mendalam, bahwa Tuhan tidaklah melulu memberikan apa yang diinginkan, namun memberikan sesuai apa yang dibutuhkan, dan selalu saja lebih baik. Ketika penulis mengakhiri runtutan ceritanya, dengan kata-kata, “Kami semua tersenyum.” Saya lantas teringat penggalan bait puisi Rendra, Sajak Seorang Tua untuk Istrinya, “Kita tersenyum bukanlah kerna bersandiwara/bukan kerna senyuman adalah suatu kedok/tetapi kerna senyuman adalah suatu sikap/sikap kita untuk Tuhan, manusia sesama, nasib dan kehidupan”. Saya pikir, penulispun memberikan penafsiran senyum, sebagaimana yang dipikirkan Rendra. Apapun pilihan hidupmu, tetaplah tersenyum menghadapinya, demikianlah kira-kira yang ingin dipesankan Kang Otong –demikian ia akrab dipanggil-. Senyum atas kehadiran novel ini.
source : abna24