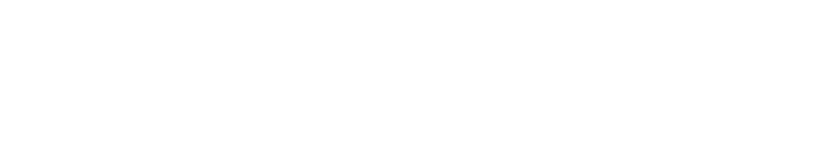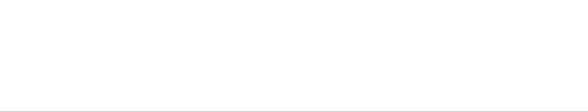Tahun 2017 menjadi momentum yang menggenapkan penderitaan bagi bangsa Palestina di bawah penjajahan Zionis-Israel. Pada tahun ini, 50 tahun sudah tanah mereka di Tepi Barat, jalur Gaza, dan Yarusalem Timur secara efektif dikendalikan rezim pendudukan Israel setelah perang 6 hari pada 1967 (diperingati sebagai “Naksa Day”). Tahun ini juga menandai 69 tahun gelombang pengusiran bangsa Palestina dari negeri mereka setelah Israel resmi mendeklarasikan diri pada 1948 (diperingati sebagai “Nakba Day”). Pada tahun ini pula, mereka akan mengenang 100 tahun Deklarasi Balfour 1917, cikal bakal rencana kolonisasi Palestina yang dirumuskan Inggris dan Zionis Eropa.
Ironisnya, pada tahun ini atau setidaknya dalam empat tahun terakhir, isu penjajahan Israel atas Palestina seperti berada di samping jalan. Berbagai perkembangan politik di Timur Tengah menyusul apa yang disebut “Musim Semi Arab” seperti menenggelamkan isu Palestina. Aktor politik negara maupun non negara di dunia Arab dan Islam, pada khususnya, serta komunitas Internasional seakan tersedot ke sejumlah persoalaan lain, baik langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap gerakan perlawanan Palestina.
Catatan Politik
Di internal Palestina, upaya Fatah dan Hamas dua faksi politik terbesar di Palestina terus gagal membentuk pemerintahan bersatu hingga 2016. Kegagalan rekonsiliasi disebabkan utamanya oleh pengaruh negatif Amerika Serikat terhadap kepemimpinan Mohmoud Abbas dari Fatah. Amerika menuntut Abbas menekan Hamas untuk mengakui Israel sebagai rekonsiliasi.
Kegagalan rekonsiliasi ini berdampak negatif terhadap perjuangan Palestina di forum politik Internasional. Otoritas Nasional Palestina yang dikendalikan Abbas kian melemah, tak lagi memiliki legitimasi di mata rakyat Palestina, terutama karena mandatnya telah habis pada 2019 dan tak pernah mampu menyelenggarakan pemilu di seluruh wilayah administratifnya sejak saat itu. Di sisi lain, meskipun popular di kalangan akar rumput, terutama di jalur Gaza, Hamas kian terkucil di forum internasional, apalagi dengan krisis diplomatik yang terjadi antara Qatar dengan sejumlah negara Teluk.
Kevakuman kendali politik di internal Palestina dimanfaatkan dengan baik oleh Israel. Pada awal 2017, Israel sudah memutuskan untuk membangun 4.000 unit pemukiman ilegal di tepi Barat dan Yerusalem Timur. Perubahan demografis pun terjadi di wilayah ini, ketika koloni-koloni di dalamnya mulai dihuni sekitar 590.000 pemukiman ilegal Yahudi, angka perpindahan pemukiman ilegal terbesar yang pernah terjadi dalam 20 tahun terakhir.
Perkembangan politik eksternal pun mempengaruhi politik di internal Palestina, hubungan Palestina dengan negara-negara Arab dan Muslim, serta relasi isu Palestina dengan komunitas internasional. Perkembangan utama yang terjadi adalah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada akhir 2016.
Sejak kampanye, Trump tak sungkan menunjukkan dirinya sebagai kandidat pro-Israel. Dia, misalnya, berjanji akan memindahkan Kedutaan Besar Amerika di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Suatu langkah yang bisa memicu kemarahan bukan hanya Palestina dan Arab, tapi juga umat Islam. Namun, mendekati tenggat, seperti presiden sebelumnya, Trump ternyata menunda pemberlakuan Jarusalem Act hingga enam bulan ke depan.
Pengaruh besar Trump lainnya adalah upayanya dalam Konferensi Saudi-Amerika, Arab-Amerika, dan Islam-Amerika di Riyadh, Arab Saudi, pada akhir Mei lalu. Dalam forum itu, Trump sukses mengucilkan sejumlah negara (di antaranya Iran dan Qatar) dengan dalih “perang melawan terror”.
Saudi, yang selama kampanyenya, kerap dia sebut sebagai negara pendukung teroris justru dia tempatkan sebagai pemimpin utama perang Amerika melawan terror di Timur Tengah dan dunia Islam. Menyusul konferensi itu, pecahlah krisis diplomatik sejumlah negara Teluk pimpinan Saudi dengan Qatar. Negara Teluk terakhir ini dikucilkan karena dianggap melindungi Ikhwanul Muslimin dan Hamas, dua organisasi yang oleh Saudi dan Amerika dimasukkan ke dalam “daftar hitam” teroris.
Pengucilan Qatar oleh Saudi dan sekutunya berdampak terhadap Hamas, faksi perlawanan terbesar di Palestina. Qatar dilaporkan menjadi penyokong utama finansial Hamas menyusul dinginnya hubungan Hamas dengan Iran setelah pecahnya perang di Suriah.
Situasi politik di internal Palestina pun terbelah dalam menyikapi keputusan Saudi dan sekutunya. Meskipun tidak secara eksplisit, Fatah sepertinya mendukung keputusan Saudi sedangkan Hamas mengecam langkah Saudi itu sebagai hal yang tak sesuai dengan kebijakan kerajaan itu terkait isu Palestina.
Yang tak kalah penting dari manuver Trump adalah kian mendekatnya sejumlah negara Arab dengan Israel. Saudi dikabarkan mulai menimbang membangun relasi ekonomi dengan negara Zionis itu. Negara-negara Arab, terutama Saudi dan Mesir, tampaknya memandang relasi dengan Israel sebagai pintu masuk menjalin kemesraan dengan rezim Trump, yang pada gilirannya akan memberi mereka jaminan kekuasaan bagi rezim di negara masing-masing menyusul dunia Arab yang masih belum stabil.
Luka yang ditimbulkan di Timur Tengah oleh krisis di timur Tengah, khususnya di Suriah, juga belum benar-benar pulih. Isu Palestina semakin meredup dan potensi normalisasi relasi Arab-Israel kian meningkat sementara, negara Muslim non-Arab, seperti Iran dan Turki, pun tampaknya lebih disibukkan dengan perang dan sejumlah konflik di sekitar wilayah mereka.
Hubungan Hamas dengan Iran dan Hizbullah di Lebanon dingin sejak perang di Suriah terjadi. Meskipun beberapa tahun terakhir, kedua pihak berupaya memperbaiki hubungan itu (terutama dengan rencana kunjungan pemimpin baru Hamas Ismail Haniyah ke Teheran), masih perlu dilihat hasil akhirnya. Selain itu, juga masih perlu dianalisis, apa pengaruh krisis diplomatik Qatar terhadap hubungan antara Hamas, Iran, Qatar, dan Hizbullah.
Catatan Perlawanan Militer
Berbeda dengan aktor politik, aktor perlawanan bersenjata anti-Israel di lapangan bisa dikatakan lebih sedikit terpengaruh dengan perkembangan konflik di Timur Tengah. Di tengah berkecamuknya perang di Suriah, pemimpin sayap militer Hamas Brigade Izzuddin al-Qassam, Mohammade al-Deif, masih sempat berkirim surat kepada pemimpin Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrullah, pada Januari 2015.
Dalam suratnya, al-Deif mengucapkan belasungkawa atas terbunuhnya anggota Hizbullah di Quneitra oleh Israel. Al-Deif juga menyerukan pentingnya persatuan antara faksi-faksi perlawanan untuk menghadapi kemungkinan perang baru Israel. Seruan yang sama disampaikan pemimpin Jihad Islam Ramadan Abdullah Shalah pada Februari 2017 dalam sebuah konferensi di Teheran.
Juru bicara Popular Resistance Committees – faksi militer yang menyempal dari sayap militer Fatah, Brigade Martir Al-Aqsha – Abu Mujahid mengatakan, meskipun disibukkan oleh perang di Suriah, Hizbullah masih menjalin koordinasi dengan faksi perlawanan Palestina, terutama di jalur Gaza. Abu Mujahid juga menyerukan agar faksi-faksi perlawanan di Gaza dan Hizbullah membuka sejumlah Front pertempuran dengan Israel jika militer negara Zionis itu melancarkan serangan baru, baik atas Gaza maupun Lebanon.
Catatan Perlawanan Sipil
Yang patut dicatat dari perlawanan sipil tak bersenjata atas Israel pada 2017 adalah mogok makan sekitar 1.500 tahan Palestina di penjara Israel. Mogok makan ini dipimpin tokoh legendaris Fatah di dalam penjara Israel Marwan Barghouti. Mogok makan massal oleh tahanan politik di penjara-penjara Israel sebagai bagian dari perlawanan sipil yang dikenal dengan intifada ke-3 atau intifada al-Quds di wilayah Tepi Barat.
Marwan merupakan sedikit tokoh Fatah yang dengan integritas teruji. Dia pun berawal dari perlawanan bersenjata dan dijebloskan ke penjara karena tuduhan pembunuhan. Namun, seperti idolanya Nelson Mandela, Marwan tetap tak menolak perjuangan bersenjata yang menurutnya merupakan hak setiap bangsa terjajah.
Di sinilah letak titik temu antara perlawanan tak bersenjata dengan perlawanan militer. Keduanya kerap coba dipisahkan oleh sejumlah kalangan. Mereka menilai perlawanan bersenjata menghasilkan citra buruk bagi perjuangan bangsa Palestina. Namun, kehadiran Marwan Barghouti menjadi bukti bahwa perlawanan, entah bersenjata ataupun tidak, menjadi dua sisi dari koin yang sama untuk mengakhiri penjajahan Israel.
Perkembangan penting lain dari perlawanan sipil adalah kian terkucilnya Israel di mata gerakan-gerakan masyarakat sipil. Resolusi Dewan HAM PBB terkait “daftar hitam” perusahaan yang beroperasi di Wilayah pendudukan dan resolusi UNESCO tentang Yerusalem sebagai “Situs Suci Umat Islam” adalah sedikit hasil dari perjuangan masyarakat sipil.
Selain itu, agresivitas Israel dalam mengolonisasi wilayah Palestina kian menipiskan harapan dari apa yang disebut sebagai “Solusi dua Negara”. Organisasi masyarakat sipil internasional kini mulai memandang bahwa solusi satu-satunya untuk mengakhiri penjajahan Israel adalah solusi seperti yang terjadi terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan, yakni bubarnya negara rasis Israel.
Rekomendasi
1. Penting untuk memformulasikan tujuan dan kampanye bersama organisasi perlawanan masyarakat sipil anti Israel, terutama karena afiliasi mereka dengan kekuatan politik tertentu, organisasi-organisasi, mulai disibukkan dengan konflik bernuansa sektarian di Timur Tengah.
2. Penting bagi masyarakat sipil di Indonesia untuk merapatkan kembali dukungannya terhadap bangsa Palestina setelah beberapa tahun terakhir terpolarisasi akibat misinformasi atas konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara.
3. Pentingnya bagi pemerintah Indonesia untuk mengisi kevakuman peran negara-negara Arab dalam mempersatukan faksi-faksi politik di internal Palestina.
4. Pentingnya bagi organisasi masyarakat sipil untuk mendesakkan agenda pengucilan Israel di dunia internasional.
5. Pentingnya untuk mendesak pemerintah Indonesia meninjau kembali dukungannya kepada konsep “Solusi Dua Negara” yang semakin terlihat tak realistis.