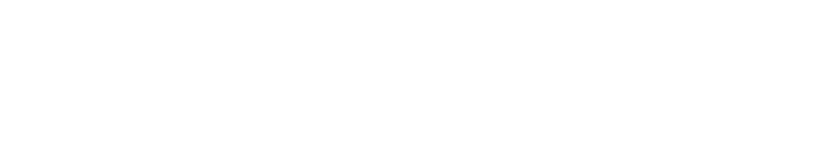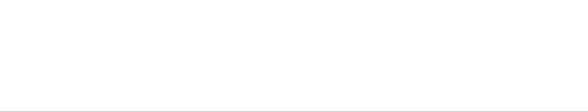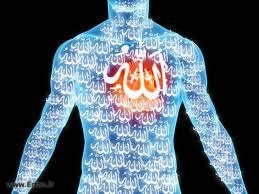
Jalaluddin Rumi, seorang sufi dari Persia, bercerita bahwa ada orang India membawa seekor gajah ke suatu negeri yang penduduknya belum pernah melihatnya. Mereka tempatkan gajah itu di sebuah rumah yang gelap tanpa cahaya. Lalu, orang-orang pun masuk ke rumah itu satu demi satu untuk merabanya.
Begitu mereka keluar dari rumah itu, masing-masing pun bercerita tentang apa yang ditangkap indera perabanya. Salah seorang yang tangannya meraba belalai mengatakan: gajah itu seperti terompet! Yang meraba telinganya mengatakan: gajah itu seperti kipas! Orang tinggi yang bisa meraba punggungnya mengatakan: gajah itu seperti kasur! Sedang si pendek yang hanya bisa meraba kaki-kakinya mengatakan: gajah itu seperti tiang!
Mereka semua tidak bersepakat. Masing-masing meyakini bahwa apa yang dirabanya itu benar-benar mewakili makhluk gajah tersebut. Mereka pun saling klaim dan saling gugat.
Dari cerita Rumi tersebut tampak bahwa pemahaman setiap orang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh penangkapan yang bersifat parsial sehingga wujud-mutlak yang ada dalam ruang dan waktu terbatasi dengan tabir-gelap yang melingkupi para penafsir (peraba).
Faktor kegelapan ruang dan waktu inilah yang mengakibatkan mereka saling memunculkan temuan dan pemahamannya yang beragam. Padahal, kalau saja ada pelita (di dalam ruang dan waktu yang gelap itu) pasti mereka akan paham dan mengerti bahwa wujud-mutlak (gajah di atas) adalah kesatuan dari temuan-temuan mereka.
Pendeknya, realitas-hakikiyah dapat diketahui dan dipahami ketika ada cahaya yang menerangi dan membuka tabir-gelap yang membatasi pancaindra dan akal pikiran kita.